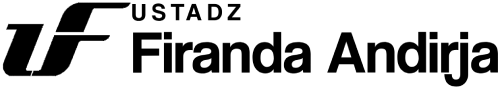Hajr Bukan Merupakan Ghoyah (Tujuan), Akan Tetapi Merupakan Wasilah
Sebagian saudara-saudara kita mempraktekan hajr kepada Ahlul Bid’ah secara sembrono tanpa melihat dan menimbang antara maslahat dan mudhorot, mereka menyangka bahwasanya hajr yang mereka selalu terapkan tersebut adalah tujuan. Praktek hajr secara sembrono tersebut banyak menimbulkan mafsadah dan menyebabkan terhalangnya dakwah ahlus sunnah, dan semakin membuat image pada masyarakat bahwa dakwah Ahlu Sunnah adalah dakwah yang sangar dan keras.
Ibnu Taimiyyah berkata ((Hajr ini bervariasi penerapannya, sesuai dengan kondisi para pelaksananya, tergantung kuat atau lemahnya kekuatan mereka. Demikian juga banyak atau sedikitnya jumlah mereka. Sebab, tujuan dari hajr adalah memberi hukuman dan pelajaran bagi orang yang di-hajr, sekaligus agar orang umum tidak melakukan seperti perbuatan orang yang di-hajr. Jika maslahatnya lebih besar -dimana praktek hajr terhadap pelaku maksiat mengakibatkan berkurangnya keburukan- maka kala itu hajr disyari’atkan. Namun, apabila orang yang di-hajr, demikian juga orang lain tidak berhenti dari kemaksiatannya, bahkan semakin menjadi-jadi, dan pelaku hajr itu sendiri lemah, sehingga mudharat yang timbul lebih besar daripada kemaslahatan, maka hajr tidaklah disyari’atkan, bahkan sikap lemah lembut kepada sebagian orang lebih bermanfaat daripada penerapan hajr untuk kondisi semacam ini.
Terkadang, penerapan hajr kepada sebagian orang lebih bermanfaat dibandingkan bersikap lemah lembut.
Karena itulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap lembut kepada sebagian orang (yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan) dan meng-hajr sebagian yang lain. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meng-hajr tiga orang yang tidak ikut jihad dalam perang tabuk, padahal mereka lebih baik daripada kebanyakan mu-allaf yang sedang dibujuk hatinya. Namun, mengingat para mu-allaf tersebut adalah para pemuka di kabilah-kabilah mereka dan ditaati, maka kemaslahatan agama diraih dengan cara bersikap lemah lembut kepada mereka. Adapun tiga orang yang tidak ikut jihad pada perang tabuk, maka mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman selain mereka banyak jumlahnya, sehingga dengan meng-hajr mereka tampaklah kekuatan dan kemuliaan agama, sekaligus untuk membersihkan mereka dari dosa.
Hal ini seperti halnya bersikap terhadap musuh. Terkadang disyari’atkan perang, terkadang damai dengan mereka, dan terkadang dengan menerima jizyah dari mereka, semua itu tergantung kondisi dan kemaslahatan.
Jawaban Imam Ahmad dan para imam yang lain tentang permasalahan hajr dibangun di atas landasan ini (yaitu membandingkan antara mashlahat dan mudharat, pen). Oleh karena itu, Imam Ahmad membedakan (penerapan hajr) di daerah-daerah yang banyak timbul bid’ah –sebagaimana halnya bid’ah qadariyyah dan tanjim di Khurasan, serta bid’ah tasyayyu’ (syi’ah) di Kufah- dengan daerah-daerah yang tidak banyak timbul bid’ah. Beliau juga membedakan antara para gembong bid’ah yang menjadi panutan dengan selain mereka.
Jika seseorang sudah mengetahui tujuan syari’at, maka seharusnya ia berusaha mencapai tujuan tersebut dengan menempuh jalan yang paling cepat mengantarkannya kepada tujuan tadi)) (Majmuu’ al-Fataawa XXVIII/206-207)
Perhatikanlah para pembaca penjelasan Ibnu Taimiyyah di atas, sangatlah jelas beliau menegaskan bahwa pelaksanaan hajr dibangun diatas menimbang antara mashlahat dan mudhorot. Diantara hal-hal yang semakin memperkuat bahwasanya praktek hajr harus dibangun diatas kaidah menimbang antara maslahat dan mudhorot adalah
Pertama : Hajr Termasuk Praktek Nahi Munkar
Merupakan kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, bahwsanya penerapan pengingkaran terhadap suatu kemungkaran dibangun diatas menimbang kemaslahatan, jika ternyata pengingkaran terhadap suatu kemungkaran semakin menambah kemudhorotan dan semakin menambah kemungkaran maka pengingkaran tersebut hukumnya haram.
Hajr –sebagaiamana penjelasan Ibnu Taimiyyah- merupakan salah satu bentuk penerapan nahi mungkar, jika perkaranya demikian maka harus dibangun diatas menimbang antara kemaslahatan dan kemudhorotan.
Ibnu Taimiyyah berkata ((Hajr ini seperti halnya hukuman ta’zir. Sedangkan ta’zir hanyalah diterapkan kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram, seperti meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, melakukan tindakan kezhaliman, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, dan menyeru kepada bid’ah yang menyelisihi al-Qur-an, Sunnah, serta ijma’ para Salaf yang menjelaskan kebid’ahannya.
Inilah hakikat perkataan sebagian Salaf dan para Imam, “Para penyeru kepada bid’ah tidak diterima persaksian mereka, tidak shalat di belakang mereka (tidak dijadikan imam shalat), tidak mengambil ilmu dari mereka, dan tidak menikahkan (muslimah) dengan mereka.”
Ini merupakan hukuman bagi mereka hingga mereka berhenti. Karena itu, para Imam Salaf membedakan antara ahli bid’ah yang menyeru kepada bid’ahnya dan ahli bid’ah yang tidak menyeru kepada bid’ahnya. Sebab, ahli bid’ah yang menyeru kepada bid’ahnya menampakkan kemungkaran, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang berbeda dengan orang yang menyembunyikan kemungkaran yang dilakukannya, karena ia tidak lebih buruk dibandingkan orang-orang munafik yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima hukum zhahir yang mereka tampakkan, dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan hal-hal yang tidak tampak dari mereka kepada Allah, padahal beliau mengetahui kondisi kebanyakan mereka.
Disebutkan dalam sebuah hadits: “Sesungguhnya jika orang-orang melihat adanya kemungkaran kemudian mereka tidak berusaha mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman secara merata kepada mereka.” (Hadits ini shahih. Lihat as-Shahiihah (1564).
Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan wajib diingkari, berbeda dengan yang tersembunyi. Sebab, kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi, maka Allah akan menimpakan hukuman kepada pelakunya secara khusus.)) (Majmuu’ Al-fataawaa 28/205)
Kedua : Menghajr Pelaku Maksiat Juga Disyari’atkan Sebagaimana Menghajr Mubtadi’
Merupakan hal yang sering dilupakan bahwasanya menghajr pelaku maksiat juga disyari’atkan. Diantara dalil yang sangat masyhuur adalah kisah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya yang menghajr Ka’b bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk selama 50 hari.
Tentunya kita semua paham bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Ka’b bin Malik dan dua sahabatnya bukanlah suatu bid’ah, akan tetapi merupakan kemaksiatan karena mereka tidak serta ikut dalam perang Tabuk. Dalil ini digunakan oleh para ulama –diantaranya Ibnu Taimiyyah rahimahullah- tentang disyari’atkannya menghajr mubtadi’. Karenanya asalnya adalah penerapan hajr terhadap pelaku maksiat, karena itulah yang terjadi di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian dalil tentang sikap hajr terhadap pelaku maksiat dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukan disyari’atkannya menghajr pelaku bid’ah.
Namun kalau kita mau menerapkan praktek hajr terhadap pelaku maksiat di zaman kita sekarang ini maka perkaranya sangatlah sulit, karena pelaku maksiat lebih banyak daripada pelaku ketaatan. Dan kalau kita tetap mau mempraktekan hajr terhadap pelaku maksiat dengan memboikot mereka dan tidak mengajak berbicara dengan mereka tentunya kita akan bingung mau tinggal di mana…, apakah kita harus tinggal di atas gunung yang jauh dari para pelaku maksiat…??, kita mau belanja ke pasar juga sulit, karena banyak penjual adalah wanita yang tidak memakai jilbab…??. Mau ke tempat pengajian saja sulit, karena kalau naik angkot harus satu angkot dengan para pelaku maksiat…!!. Mau makan juga sulit k
arena mungkin penjual makanan adalah pelaku maksiat…!!!.
Oleh karenanya secara umum praktek hajr terhadap para pelaku maksiat di zaman ini kurang bisa diterapkan karena tidak ada kemaslahatannya. Akan tetapi jika memang hajr terhadap pelaku maksiat ada maslahatanya dalam raung lingkup tertentu –misalnya ayah menghajr istri atau anaknya yang bermaksiat- maka silahkan untuk diterapkan.
Dari dua perkara di atas maka jelas bahwasanya praktek hajr harus dibangun diatas melihat dan menimbang antara maslahat dan mudhorot.
Para pembaca sekalian…
Tujuan dari menghajr halul bid’ah adalah untuk mencapai kemaslahatan, yaitu: (1) agar pelaku bid’ah tersebut berhenti dari bid’ahnya, atau bid’ahnya berkurang, atau (2) masyarakat tidak terjatuh dalam bid’ah tersebut.
Hajr merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan. Ia bukanlah ghayah (tujuan), namun hanyalah wasilah (sarana). Wasilah hanyalah disyari’atkan apabila mengantarkan kepada tujuan yang baik. Sebaliknya, jika tidak mengantarkan kepada tujuan yang baik, maka tidak disyari’atkan. Karena itu, sekarang kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang menganggap hajr adalah ghayah (tujuan) bukan wasilah (sarana). Ia menganggap bahwa dzat hajr itu sendiri merupakan maslahat, bahwa hajr merupakan ibadah li dzatihi (dzatnya itu sendiri merupakan ibadah) bukan li ghairihi (bernilai ibadah disebabkan adanya perkara yang lain), akhirnya hajr itu dipraktekkan tanpa kaidah, tanpa menimbang antara maslahat dan mudharat.
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Kondisi hajr ada tiga:
1. Maslahat lebih kuat dibandingkan kerusakan, maka hajr tersebut dituntut (untuk diterapkan)
2. Atau kerusakan yang lebih kuat, maka penerapan hajr tanpa diragukan lagi adalah dilarang
3. Atau belum dapat ditentukan manakah yang lebih kuat antara kerusakan maupun maslahat, maka yang lebih dekat (kepada kebenaran) adalah dilarangnya penerapan hajr, karena keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ
“Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling, begitu juga yang lainnya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam.” (HR Al-Bukhari (V/2302) (5879) dan Muslim (IV/1984) (2560), adapun perkataan Syaikh utsaimin dalam Majmuu’ Fataawa Syaikh Ibnu ‘Utsaimin (III/17) soal no (385). Selain karena keumuman hadits tersebut, juga karena hukum asal dalam dakwah adalah dengan kelembutan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama Salaf.)
Beliau juga berkata, “Ketahuilah, bahwa hajr itu seperti obat, jika memberikan faedah maka gunakanlah. Adapun jika semakin menambah penyakit maka jangan digunakan…. Jika engkau meng-hajr-nya tetapi ia justru semakin menjadi-jadi dan membencimu… maka janganlah engkau meng-hajr-nya” (Liqaa’ al-Baab al-Maftuuh, no (200).
Beliau juga berkata berkata, “Ahli bid’ah, jika ia menyeru kepada bid’ahnya dan ada maslahat dengan meng-hajr-nya, maka janganlah disalami. Namun jika tidak ada maslahat dengan meng-hajr-nya maka berilah salam kepadanya.” (Liqaa’ al-Baab al-Maftuuh, no (145).
Mengingat hajr dibangun atas landasan maslahat dan mudharat, maka tidak semua orang yang melakukan kemaksiatan di-hajr. Begitu juga dengan para pelaku bid’ah. Semua ini kembali kepada maslahat dan mudharat.
Syaikh Shalih Alu Syaikh berkata, “Keadaan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama para pelaku maksiat orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik bervariasi. Yang di-hajr oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah sebagian pelaku kemaksiatan, tidak semuanya, hanya sebagian saja. Demikian juga dengan orang-orang munafik, mereka tidaklah di-hajr oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang-orang musyrik yang datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidaklah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meng-hajr mereka. Begitu pula dengan orang-orang Nasrani yang datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidaklah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menghajr mereka. Hal ini menunjukkan kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ilmu dan para imam dari kalangan muhaqqiqin, sebagaimana juga dipaparkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di sejumlah pernyataan beliau, bahwa hajr itu mengikuti maslahat yang syar’i. Orang yang di-hajr hanyalah yang bisa mendapat manfaat dari hajr tersebut. Adapun orang yang tidak bisa mengambil faedah dari hajr, maka ia tidak di-hajr. Sebab hajr adalah hukuman untuk meluruskan. Jika hukuman tidak bermanfaat maka tidak disyari’atkan, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah meng-hajr seluruh (pelaku kemaksiatan).” (Dari ceramah beliau yang berjudul an-Nashiihah lisy Sysabaab)
Menimbang Kemaslahatan Tatkala Menghajr
Kemaslahatan hajr dapat diprediksi dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Kekuatan pihak yang melakukan hajr, misalnya dengan melihat jumlahnya. Jika jumlahnya lebih sedikit maka maslahat yang diharapkan sulit tercapai.
2. Pengaruh pelaku hajr. Pihak yang melakukan hajr hendaknya mampu memberikan pengaruh kepada orang yang di-hajr sehingga ia berhenti dari kesalahannya, atau mengurangi kemaksiatan yang ia lakukan, atau paling tidak pengaruhnya tersebut bisa mempengaruhi masyarakat untuk meninggalkan orang yang di-hajr meskipun objek yang di-hajr tidak berhenti dari perbuatannya. Karena itu, termasuk kesalahan apabila sebagian orang hidup di suatu kampung yang penuh dengan ahli bid’ah, gembong bid’ahnya adalah individu yang memiliki pengaruh, misalnya da’i kondang atau seorang lurah, lantas mereka meng-hajr ahli bid’ah tadi, padahal masyarakat masih memberikan dukungan terhadap ahli bid’ah tersebut, atau bahkan merupakan pengikutnya, sehingga kemashlahatan yang diharapkan sama sekali tidak terealisir, bahkan justru pelaku hajr yang terusir dari kampung tersebut dan tidak lagi bisa berdakwah di tempat itu. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya oleh Ishaq bin Manshur, “Apakah seorang Ahlus Sunnah menampakkan permusuhan terhadap mereka (sekte Jahmiyyah yang menyatakan al-Qur-an adalah makhluq di negeri Khurasan), ataukah ia melakukan mudarah?” Imam Ahmad menjawab, “Penduduk (Ahlus Sunnah di) negeri Khurasan tidak mampu berhadapan dengan mereka (Jahmiyyah).” Oleh karena itu, hajr jenis ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya boleh dilakukan oleh orang yang mampu membandingkan antara maslahat dan mudharat. Sangat disayangkan, ada orang yang baru ikut ngaji, belum mampu menimbang maslahat dan mudharat, tetapi nekat ikut-ikutan menerapkan hajr terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai ahli bid’ah –meski tuduhan ahli bid’ah tersebut pun belum tentu benar-, sehingga yang terjadi hanyalah fitnah, dan dakwah Ahlus Sunnah semakin terhambat. Ini adalah kesalahan yang harus diperbaiki.
Syaikh Ibnu Baaz berkata, “Jika penerapan hajr terhadap seseorang mengakibatkan perkara yang lebih mungkar daripada perbuatannya, karena orang tersebut memiliki kedudukan di negara atau di kabilahnya, maka tidak diterapkan hajr pada dirinya. Dia disikapi dengan mu’amalah yang terbaik serta disikapi dengan kelembutan sehingga tidak mengakibatkan keburukan yang lebih parah atau menimbulkan perkara yang lebih buruk daripada amalannya. Dalilnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyikapi gembong orang-orang munafik, ‘Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana sikap beliau kepada tiga orang sahabat beliau, yaitu Ka’b (bin Malik) dan kedua sahabatnya. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap lembut kepada ‘Abdullah bin Ubay dan tidak meng-hajr-nya, karena ia adalah pemimpin kaumnya. Dikhawatirkan apabila ia dipenj
ara dan di-hajr maka akan menimbulkan fitnah bagi jama’ahnya di Madinah. Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap lembut kepadanya hingga ia mati di atas kemunafikannya. Kepada Allah-lah kita memohon keselamatan. Dan ada kondisi-kondisi lainnya dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak meng-hajr sejumlah orang, bahkan beliau bersikap lembut sehingga Allah pun memberi petunjuk kepada mereka. Karena itu sikap lembut dalam dakwah termasuk perkara yang paling lazim (paling urgen).” (Majmuu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (IV/234-235), soal no (8).
Renungan
Karena hanya membaca buku-buku yang memuat sikap keras Salaf kepada ahli bid’ah maka sebagian orang pun lantas ikut-ikutan mengambil sikap keras, beralasan dengan sikap Salaf tersebut. Ia berdalil dengan sikap Imam Ahmad yang keras, begitu juga dengan sikap para Imam yang lain. Padahal seharusnya ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, diantaranya:
a. Zaman para Salaf dahulu tidaklah seperti zaman kita sekarang ini. Secara umum bisa dikatakan bahwa zaman Salaf adalah zaman tersebarnya Sunnah, berbeda dengan zaman kita ini.
Syaikh Abdul Malik Romadhoni pernah bertanya kepada Syaikh Al-Albani, “Bagaimanakah cara bermu’amalah dengan penyelisih (manhaj salaf) antara sikap mereka yang bermudah-mudahan sehingga sikap tersebut mengantarkan mereka kepada sikap tamayyu’, dengan mereka yang bersikap berlebih-lebihan (keras) sehingga mengantarkan sikap tersebut pada sikap tidak menegakkan hujah (kepada penyelisih tersebut) –sebagaimana yang sering engkau sebutkan…akan tetapi ada sebagian syubhat dari sikap-sikap salaf (yang menjadikan mereka bersikap keras terhadap para penyelisih-pen) seperti perkataan sebagian salaf الْقُلُوْبُ ضَعِيْفَةٌ والشُّبْهَةُ خَطَّافَةٌ Hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar yaitu tatkala bermajelis dengan ahlul bid’ah. Demikian juga sikap Imam Ahmad yang menjauhkan umat dari Al-Harits Al-Muhasibi…demikian juga sikap sebagian salaf yang menjauhkan umat dari para ahlul bid’ah meskipun para ahlul bid’ah tersebut memiliki kebaikan?”
Syaikh berkata, ((Pendapatku –wallahu A’lam- bahwasanya perkataan salaf (yang keras terhadap ahlul bid’ah-pen) berlaku pada al-Jau as-Salafi (hawa/kondisi salafi). Yaitu pada kondisi yang penuh dengan keimanan yang kuat dan ittiba’ yang shahih terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. Permasalahan ini sama persisi dengan permasalahan sikap muqotho’ah (menghajr) seroang muslim terhadap seorang muslim yang lain dalam rangka mendidiknya dan memberi pelajaran baginya. Ini merupakan sunnah yang ma’ruf. Akan tetapi keyakinanku –dan aku sering sekali di tanya tentang hal ini- aku katakan bahwa zaman kita ini tidak cocok untuk diterapkan muqotho’ah (hajr). Zaman kita ini tidak cocok untuk memuqotho’ah para ahlil bid’ah, karena maknanya (jika engkau menghajr ahlul bid’ah-pen) berarti engkau akan tinggal di atas puncak gunung, engkau menjauh dari masyarakat. Hal ini dikarenakan tatkala engkau menghajr masyarakat –karena kafasikan mereka atau karena kebid’ahan mereka- tidaklah hal itu memberi pengaruh (positif) sebagaimana pengaruh yang timbul di zaman salaf yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut (yaitu kalimat-kalimat keras terhadap ahlul bid’ah) dan dorongan meraka (salaf) terhadap masyarakat untuk menjauhi para ahlul bid’ah…)) (Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 511)
b. Pihak yang menerapkan hajr adalah para imam Salaf yang memiliki kedudukan. Suara mereka didengar oleh masyarakat. Bahkan sebagian imam Salaf disegani oleh para pejabat di zamannya. Jika kondisinya demikian, maka penerapan hajr yang mereka lakukan memang akan membuahkan hasil yang baik. Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang menerapkan hajr, sementara mereka tidak memiliki pengaruh, tidak didengar, bahkan terkadang dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang buruk, lantas maslahat apakah yang bisa diharapkan dengan hajr yang ia terapkan?
Syaikh ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad berkata, “Hajr yang bermanfaat di kalangan Ahlus Sunnah adalah hajr yang bermanfaat bagi objek yang di-hajr. Seperti seorang bapak yang meng-hajr anaknya dan guru menghajr muridnya. Demikian juga apabila hajr dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan pamor yang tinggi, maka hajr yang dilakukan oleh mereka bermanfaat bagi objek yang di-hajr. Berbeda jika hajr dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu kepada para penuntut ilmu yang lain –terutama pada perkara yang tidak dibenarkan praktek hajr disebabkan perkara tersebut- maka praktek hajr tersebut sama sekali tidaklah memberi faedah bagi objek yang di-hajr. Bahkan mengakibatkan timbulnya ketidakcocokan, sikap saling menjauh, dan saling memutuskan hubungan.” (Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, hal 56)
Ada sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada Syaikh al-Albani, “Apakah benar yang kami dengar dari Syaikh bahwa meng-hajr ahli bid’ah pada zaman ini tidak bisa diterapkan?”
Syaikh al-Albani menjawab, “Penanya ingin mengatakan bahwa apakah praktek hajr tidak layak (tidak maslahat) untuk diterapkan? apakah benar memang demikian??
(Jawabannya adalah benar) praktek hajr memang tidak (layak) diterapkan. Karena sekarang ini para mubtadi’, orang-orang fasiq, dan orang-orang fajir merekalah yang mendominasi.
(sipenanya) ingin mengatakan, “Tidak layak” untuk diterapkan.
Tatkala bertanya seakan-akan penanya memaksudkan diriku dengan pertanyaan tersebut. Maka jawabannya adalah, “Memang benar sebagaimana yang ia tanyakan, bahwasanya hajr tidak layak untuk diterapkan, dan aku baru saja mengatakannya dengan jelas tatkala aku menyebutkan pepatah Syam yaitu
أَنْتَ مُسَكِّر وَأَنا مُبَطِّل
“Engkau menutup (pintu masjid) maka aku tidak shalat”.
((Pepatah ini berkaitan dengan seseorang yang fasiq lagi meninggalkan shalat. Lalu pada suatu saat ia ingin bertaubat dan ingin shalat untuk pertama kalinya, maka ia pun melangkahkan kakinya menuju masjid. Namun tatkala ia tiba di masjid ia mendapati masjid dalam keadaan tertutup. Maka ia pun berkata, “Engkau menutup (pintu masjid), maka aku tidak jadi shalat.” Maksud pepatah ini, banyak orang yang melakukan kemaksiatan atau kebid’ahan tidak jadi kembali kepada jalan yang lurus dan benar, atau tidak jadi meninggalkan kemaksiatan atau kebid’ahan mereka, karena mendapati sikap keras dari orang-orang yang istiqamah. Lihat penjelasan Syaikh al-Albani terhadap pepatah ini dalam Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no (735)-pen))
Penanya berkata, “Wahai Syaikh, namun seandainya ada sebuah tempat yang Ahlus Sunnah dominan di tempat tersebut, kemudian ada sekelompok orang yang berbuat bid’ah, maka apakah praktek hajr diterapkan atau tidak…?”
Syaikh al-Albani berkata, “Apakah kelompok yang berbuat bid’ah tersebut berasal dari tempat itu juga?”
“Iya, benar, yaitu di tempat yang dominan di dalamnya kebenaran, lalu timbul kebatilan atau bid’ah, maka pada kondisi seperti ini apakah diterapkan hajr atau tidak…?”
Syaikh al-Albani berkata, “Yang wajib dilakukan adalah menggunakan hikmah. Jika kelompok yang kuat yaitu yang dominan meng-hajr kelompok yang menyimpang –maka kembali kepada pembicaraan lalu- apakah hal ini akan memberikan manfaat kepada kelompok yang berpegang teguh (dengan Sunnah) ataukah justru menimbulkan mudharat? Ini dari satu sisi.
Kemudian dari sisi yang lain, apakah hajr yang diterapkan oleh ath-Tha-ifah al-Manshurah (Ahlus Sunnah) bermanfaat bagi kelompok yang di-hajr? ataukah justru menimbulkan mudharat bagi mereka? Hal ini telah dijawab sebelumnya.
Dalam permasalahan-permasalahan seperti ini janganlah kita mengambil sikap berdasarkan hamasah (semangat) dan perasaan. Namun harus dengan sikap hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan
hikmah. Misalnya kita di sini, ada salah seorang dari mereka menyelisihi jama’ah, (lalu apakah akan kita katakan), “Wahai orang-orang yang memiliki ghirah lakukanlah hajr terhadapnya??!” Tentu tidak, namun hendaklah kalian bersikap lembut kepadanya, nasehatilah dia, bimbinglah dan temani dia, dan seterusnya. Jika dia memang tidak bisa diharapkan lagi (untuk berubah menjadi baik), ini poin yang pertama; lalu yang kedua dikhawatirkan (keburukannya) akan menular kepada Zaid, Bakr, dan lain-lain, maka pada kondisi seperti ini dia di-hajr, jika memang kuat dugaan bahwa hajr (bermanfaat) ketika itu. Sebagaimana dikatakan bahwa obat yang terakhir adalah kay.”
((Kay adalah pengobatan dengan besi yang sudah dipanaskan, kemudian diletakkan pada bagian tubuh yang sakit. Perkataan Syaikh al-Albani ini menunjukan bahwa beliau tidak menafikan penerapan hajr secara total. Hanya saja beliau memandang bahwa di zaman ini mayoritas penerapan hajr tidak menghasilkan maslahat. Mengenai perkataan Syaikh al-Albani, “Obat yang terakhir adalah kay,” maksudnya solusi terakhir adalah hajr. Artinya, Syaikh memandang bahwa untuk zaman ini hajr itu sebisa mungkin tidak diterapkan, melihat banyaknya mudharat yang timbul di lapangan disebabkan penerapan hajr. Tentunya Syaikh menyatakan yang demikian setelah pengamatan beliau yang lama di medan dakwah-pen))
Selanjutnya Syaikh al-Albani berkata, “Secara umum, pada zaman ini aku sama sekali tidak menasehatkan untuk menggunakan metode penerapan hajr sebagai solusi, karena mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Bukti yang paling besar adalah fitnah yang terjadi sekarang ini terjadi di Hijaz (Arab Saudi). (Awalnya) mereka semua disatukan oleh dakwah tauhid, yaitu dakwah kepada al-Kitab dan as-Sunnah. Namun karena sebagian mereka memiliki kegiatan khusus, baik dalam bidang politik, atau mereka memiliki beberapa pemikiran yang sebelumnya tidak dikenal oleh seorang pun dari kalangan ahli ilmu. Terkadang pemikiran tersebut salah dan terkadang benar. Karena sikap kita yang tidak sabar untuk mendengar sesuatu yang baru, terutama jika perkara baru tersebut adalah suatu perkara yang tampak oleh kita sebagai suatu kemungkaran. Sehingga kitapun langsung memeranginya. Ini adalah sikap yang keliru, wahai saudaraku!! Ini adalah kekeliruan!!
Apakah engkau mengharapkan memiliki seorang sahabat yang tidak ada mempunyai aib sama sekali??! Apakah engkau menginginkan kayu gaharu mengeluarkan bau harumnya tanpa disertai asap??!
Kami berangan-angan sekiranya saudara-saudara kita sesama muslim tersebut hanya sama seperti kita dalam masalah tauhid. Itu saja (sudah cukup)… Hanya sama dalam tauhid saja!! sehingga kalian bisa bersama mereka. (Sebab) mereka tidak ridha untuk bersama kita, bahkan dalam masalah ‘aqidah. Mereka mengatakan bahwa menghidupkan khilaf-khilaf hanya mencerai-beraikan barisan, dan seterusnya.
Mereka, yaitu saudara-saudara kita tersebut (di Arab Saudi), terpecahlah dari mereka sebuah jama’ah, atau merekalah yang memisahkan diri dari jama’ah –wallaahu a’lam- , mereka itu sama dengan kita, mereka di atas jalan yang kita tempuh yaitu al-Kitab, Sunnah, dan di atas manhaj as-Salafus Shalih. Hanya saja mereka membawa suatu pemikiran baru yang kenyataannya sebagiannya salah dan sebagiannya benar. Lalu mengapa kita sekarang ini menyebarkan perpecahan, sikap berkelompok-kelompok, dan ta’ashshub (fanatisme) di antara kita, yaitu sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Padahal dahulunya kita, Ahlus Sunnah, hanya satu kelompok. Lalu kemudian menjadi dua kelompok, kemudian menjadi tiga kelompok. Jadilah Ahlus Sunnah safariyyin, sururiyyin, dan seterusnya. Allaahu Akbar. Yang membuat mereka terpecah belah hanyalah dikarenakan suatu perkara yang sangat tidak layak untuk menjadi sebab mereka berpecah. Perselisihan mereka bukan pada perkara-perkara yang besar -tidak terbayangkan bahwa Salafiyyun akan berselisih di dalam masalah semacam itu-. Kita sama-sama tahu bahwa para Sahabat berselisih pada beberapa masalah, namun manhaj mereka tetap satu. Oleh karena itu, apabila ada jama’ah Ahlus Sunnah atau ath-Tha-ifah al-Manshurah, kemudian ada sejumlah orang yang nyeleneh dari mereka, maka hendaknya kita menyikapi mereka dengan lembut dan halus. Kita berusaha menjaga mereka agar terus bersama jama’ah (Ahlus Sunnah). Kita tidak memboikot dan meng-hajr mereka, kecuali jika kita khawatir timbul sesuatu (keburukan) dari mereka. Namun kekawatiran ini tidaklah langsung muncul dan tampak begitu saja. Tidak sekedar seseorang menampakan sebuah pendapat yang nyeleneh dari jama’ah lalu kita langsung memboikotnya. Kita teliti lebih dahulu (duduk masalahnya). Hendaknya kita tidak bersikap tergesa-gesa. Semoga Allah memberi petunjuk kepada hatinya, atau kemudian jelas bagi kita bahwa mengeluarkannya (meng-hajr-nya) ternyata lebih baik.” (Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no (666); 7 sya’ban 1413 H)
Pertanyaan lain pernah ditujukan kepada Syaikh al-Albani, “Wahai Syaikh, engkau memandang tidak bolehnya penerapan hajr terhadap ahli bid’ah, memusuhi mereka, dan tidak berbicara dengan mereka?”
Syaikh al-Albani menjawab, “Kami tidak memandang bolehnya penerapan hal ini…. Kalau kita sekarang ingin menerapkan manhaj Salaf yang kita warisi dari sebagian ulama kita, dari para Salaf, berupa sikap keras terhadap ahli bid’ah, meng-hajr mereka, memboikot mereka, dan tidak mendengarkan mereka, maka kita akan kembali mundur ke belakang.
((Camkanlah perkataan Syaikh al-Albani tersebut. Maksud beliau, apabila kita bersikap keras sebagaimana ulama Salaf dahulu, padahal kondisi kita saat ini berbeda dengan mereka, maka dakwah kita akan kembali mundur, karena perkembangan dakwah dibangun di atas sikap yang berlandaskan hikmah dan maslahat. Wallaahu a’lam-pen.))
Sebagaimana kami katakan, seandainya kita memiliki seorang teman -misalnya- yang bersama kita di atas satu jalan lalu ia menyimpang hingga akhirnya tidak shalat “apakah kita kemudian memboikotnya?” Pertanyaan semodel ini banyak terlontar dari orang-orang yang memiliki semangat keislaman yang tinggi. Kami katakan: “ Bahwa kita tidak memboikotnya. Namun perhatikanlah dia dengan terus memberikan nasehat dan peringatan…” Kami pernah menceritakan kepada kalian tentang sebuah pepatah Suria tentang seseorang yang tidak shalat. Namun ketika dia hendak melaksanakan shalat untuk pertama kalinya ia mendapati masjid tertutup, lalu ia berkata, ‘Kalian menutup masjid maka aku tidak jadi shalat.’ … maka wajib meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang meninggalkan shalat… apabila kita memboikotnya berarti kita menjadikan dia semakin sesat. Yang harus kita lakukan adalah terus memberikan nasehat dan peringatan kepadanya, bersikap lembut serta halus kepadanya, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada orang Yahudi. Hal yang sama juga kita terapkan kepada para ahli bid’ah. Kalau kita tinggalkan mereka, kita biarkan begitu saja dengan kondisi dan kesesatan mereka, maka siapakah yang akan berusaha memberi hidayah kepada mereka??”
((Karena itu merupakan perkara yang aneh apabila ada seorang da’i bermanhaj Salaf diberi kesempatan untuk berdakwah di tempat hizbiyyin namun ia malah meninggalkan kesempatan emas ini. Semestinya jika ada kesempatan emas terbuka untuk menampakan kebenaran di hadapan hizbiyyin maka jangan sampai disia-siakan. Lebih aneh lagi sikap sebagian orang yang men-tahdzir saudaranya yang berkesempatan dakwah di lingkungan ahli bid’ah. Merupakan perkara yang menggelikan kalau kita hanya berharap ahli bid’ah di zaman kita ini datang menemui kita dan ikut mendengarkan pengajian kita. Bukankah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Nabi lainnya mendatangi tempat-tempat kesyirikan untuk menyampaikan kebenaran? Mereka tidak hanya diam di masjid menunggu orang-orang musyrik datang mendengarkan kebenaran yang mereka sampaikan. -pen.)).
Penanya berkata, “Jika demikian, maka tidak boleh meng-hajr mereka (a
hli bid’ah)?”
Syaikh al-Albani rahimahullah menjawab, “Untuk masa sekarang ini tidak boleh.” (Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no. (611).
(Demikianlah penjelasan Syaikh Al-albani )
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata, “Pada masa ini, kebanyakan pelaku kemaksiatan, apabila di-hajr justru semakin sombong dan menjadi-jadi dalam kemaksiatan, semakin jauh dari ahli ilmu sekaligus semakin menjauhkan (orang lain) dari ahli ilmu, sehingga penerapan hajr terhadap mereka tidak memberikan faedah bagi mereka, juga bagi selain mereka.” (Majmuu’ Fataawa (III/11) soal no. (382).
3. Kondisi pihak yang di-hajr. Sebab, kadar kerasnya hajr, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, harus disesuaikan dengan kondisi pihak yang di-hajr. Kadar hajr tidak boleh kurang dari yang seharusnya, sehingga pihak yang di-hajr tidak jera. Begitu juga sebaliknya, kadarnya tidak boleh terlalu tinggi, sehingga memudharatkannya. Ibnul Qayyim berkata,
… وَيَكُوْنُ هُجْرَانُهُ دَوَاءً لَهُ بِحَيْثُ لاَ يَضْعُفُ عَنْ حُصُوْلِ الشِّفَاءِ بِهِ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْكَمِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ عَلَيْهِ فَيُهْلِكَهُ إِذ الْمُرَادُ تَأْدِيْبُهُ لاَ إِتْلاَفُهُ ….
“… agar hajr tersebut menjadi obat bagi pihak yang di-hajr. Obat tersebut tidak boleh lemah sehingga tidak menghasilkan kesembuhan. Sebaliknya, kadarnya juga tidak berlebihan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga membinasakan pihak yang di-hajr, karena maksud dari hajr adalah untuk memberi pelajaran kepadanya bukan untuk merusaknya.” (Zaadul Ma’aad (III/578).
Termasuk penerapan hajr yang salah adalah hajr yang dilakukan oleh sebagian orang dengan satu kondisi saja, yaitu keras dan terus menerus, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi orang yang di-hajr. Kadar hajr yang mereka lakukan melebihi batas yang diperlukan, sehingga sering kita dapati orang yang di-hajr akhirnya tidak mau ikut pengajian sama sekali, bahkan ada yang sampai kembali mengerjakan perbuatan maksiat. Hajr yang seperti ini jelas merupakan hajr yang merusak, bukan hajr yang membangun dan mendidik. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang selalu lemah dalam menghajr tanpa memperhatikan kondisi orang yang di-hajr, sehingga akhirnya hajr yang dilakukannya mentah dan tidak bisa mengobati. Hajr yang benar adalah hajr yang memperhatikan kemaslahatan, sekaligus memandang situasi dan kondisi objek yang di-hajr.
Oleh karenanya :
Terkadang Sikap Lembut Terhadap Ahlul Bid’ah Lebih Bermanfaat
Bisa jadi sikap lemah lembut kepada ahli bid’ah lebih bermanfaat dibandingkan sikap keras, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, “Apabila orang yang di-hajr, begitu juga orang lain, tidak berhenti dari kemaksiatannya, bahkan semakin menjadi-jadi, dan pelaku hajr juga lemah kondisinya, dimana mudharat yang timbul lebih besar daripada maslahat, maka hajr tidaklah disyari’atkan. Bahkan pada kondisi ini sikap lemah lembut kepada sebagian orang lebih bermanfaat daripada penerapan hajr.” (Majmuu’ Fataawa (XXVIII/206)
Pertanyaan yang patut kita renungkan, berapa banyak ahli bid’ah dan hizbiyyin yang sadar dan kembali kepada Sunnah disebabkan hajr dari seorang Ahlus Sunnah? Ataukah yang terjadi justru sebaliknya, mereka semakin jauh dari Sunnah dan semakin menjadi-jadi?. Tentunya kita semua mengetahui jawabannya. Bukankah kita saksikan di zaman ini bahwa mayoritas –atau bisa jadi seluruh- ahli bid’ah dan hizbiyyin yang mendapatkan hidayah adalah disebabkan kelembutan Ahlus Sunnah yang menjelaskan kebenaran kepada mereka.
Oleh karena itu, sikap lembut merupakan wasilah terbesar dalam keberhasilan dakwah.
Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata, “Terdapat kondisi-kondisi dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak meng-hajr sebagian orang, bahkan beliau bersikap lembut kepada mereka, sehingga Allah pun memberi petunjuk kepada mereka. Maka sikap lembut dalam dakwah termasuk perkara yang paling paling urgen.” (Majmuu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (IV/235), soal no (8).
Allah berfirman:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS. 3:159)
Perhatikanlah wahai saudaraku. Para sahabat telah mengenal kepribadian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka mengenal bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang benar, jujur, amanah, dan menghendaki kebaikan bagi umatnya. Selanjutnya, para sahabat sendiri merupakan generasi terbaik umat ini, memiliki akhlak mulia, mengedepankan kebenaran, rela berjuang membela Islam, dan mempercayai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Meskipun demikian, Allah k menyatakan bahwa sekiranya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap keras lagi berhati kasar maka para sahabat akan menjauh dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Kemudian cobalah bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Kondisi kita tentu sangat jauh di bawah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam -bahkan tidak mungkin dapat dibandingkan- sementara orang-orang yang kita dakwahi juga tidak bisa dibandingkan dengan kondisi para sahabat. Disamping itu, mereka belum tentu percaya dengan kita. Kalau demikian keadaannya, maka apakah yang akan terjadi sekiranya kita bersikap kasar dalam berdakwah? Kalau para sahabat saja bisa jadi menjauhi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sekiranya beliau bersikap kasar dalam dakwah, lalu bagaimanakah dengan orang-orang di zaman ini?!
Syaikh Shalih Alu Syaikh berkata, “Diantara adab seorang da’i, hendaklah ia merupakan seorang penyayang dan lemah lembut. Sikap rahmat, kasih sayang dan kelembutan merupakan buah dari keikhlasan dan kemurnian (dalam dakwah kepada Allah). Sekiranya seseorang itu bersih dalam berdakwah kepada Allah, atau dalam melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, jika ia ikhlas, niscaya ia akan menjadi seorang yang penyayang dan lemah lembut…. Allah berfirman dalam rangka memberi perintah kepada Nabi Musa ‘alaihissalam dan saudaranya Harun:
فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut. (QS. Thahaa: 44)
Allah juga mensifati Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan firman-Nya,
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu’min. (QS. at-Taubah: 128)
Jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang welas asih lagi penyayang, maka mengapa kita tidak meneladaninya?
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) har
i kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzaab: 21)
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Shahiih-nya:
إنمَّا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء
“Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah di kalangan hamba-hamba-Nya adalah para penyayang.”
Dalam hadits lain dalam kitab-kitab Sunan disebutkan:
الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهًمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الأرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
“Para penyayang disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi niscaya Dzat yang di langit akan menyayangi kalian.” (HR Abu Dawud (IV/285) no (4941) dan at-Tirmidzi (IV/323) no (1924), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam as-Shahiihah (II/594) no (935).
Sikap kasih sayang harus dimiliki. Engkau harus menyayangi orang yang kau dakwahi. Tatkala engkau berdakwah, apa yang kau kehendaki dengan dakwahmu? Bukankah kau ingin ia mendapatkan hidayah? Bukankah kau ingin memperbaiki kondisinya? Bukankah kau menginginkannya agar istiqamah? Bukankah kau ingin hatinya istiqamah? Jika demikian, lantas kenapa engkau tidak berkasih sayang kepadanya? Kenapa engkau harus bersikap keras, bersikap kasar yang bukan pada tempatnya? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadits yang terdapat dalam as-Shahihain dari Aisyah:
يا عائشةُ، إِنَّ الرِّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ، وَلا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إلا شَانَه
“Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan memburukkannya.”
Kelembutan, jika terdapat pada seluruh perkara niscaya akan menghiasinya, dan jika dicabut dari perkara apapun niscaya akan memburukkannya. Diantaranya adalah perkara dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar. Karena itu keduanya harus dibarengi dengan sikap kelembutan. Sikap kasar dalam hal ini adalah tercela. Allah k berfirman:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS. Ali ‘Imran: 159)
Para ahli ilmu berkata, ‘Mengenai firman Allah:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَه
Maknanya adalah: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.” Sebab huruf (ما) dalam firman Allah (فَبِمَا) merupakan shilah, dan shilah adalah penguat makna, sehingga maknanya seperti mengulang-ngulang pembicaraan.
Jika demikian, maka bagaimanakah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersifat lembut kepada mereka? Jawabnya dengan sikap kasih sayang.
Suatu ketika Harun ar-Rasyid rahimahullah melakukan thawaf di Ka’bah. Lalu ada seseorang yang mengenalnya dan berkata, “Wahai Harun, aku akan berbicara denganmu dan akan menekanmu, aku adalah pemberi nasehat kepadamu….” Maka Harun ar-Rasyid berkata, “Wahai Fulan aku tidak mau mendengar perkataanmu. Sebab aku tidaklah lebih buruk daripada Fir’aun dan engkau tidaklah lebih baik dari Nabi Musa ‘alaihissalam. Sedangkan Allah telah memerintahkan Musa untuk berkata kepada Fir’aun dengan perkataan yang lembut.” (Lihat kisah ini dalam Al-Muntadzom fi taariikhil khulafaa’ wal umam (VIII/328) dan Taariikh At-Thobari (V/22)
Jika demikian, maka awal mulanya adalah perkataan yang lembut dan kasih sayang. Apabila kemudian tampak kesombongan serta pertentangannya, dan ia jelek bagi kebaikan serta agama Islam, tampak bahwa ia mengejek ayat-ayat Allah maka tidak ada kemuliaan baginya. Prinsip al-wala’ wal bara’ mengharuskan agar orang tersebut dijauhi. Karena itulah Nabi Musa ‘alaihissalam pada awal dakwahnya berkata dengan perkataan yang lembut. Namun tatkala telah tampak bahwa Fir’aun tidak mau tunduk, Musa berkata:
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُوراً
“Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir’aun, adalah seorang yang binasa.” (QS. al-Israa’: 102).
Dengan ucapan tersebut tampaklah kejayaan dan kekuatan, namun hal ini bukanlah di awal perkara….
Perkara ini aku ulangi-ulangi sebagai peringatan agar diperhatikan. Sebab kita sedang kehilangan perkara ini. Ada seseorang yang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, berdakwah, sementara ia sendiri tidak pernah memohon kepada Allah agar Allah memberi petunjuk kepada orang yang didakwahinya tersebut….
Seseorang bercerita, “Suatu saat ada seorang jama’ah masjid keluar menemui kami. Kala itu kami sedang duduk berkumpul. Ia menasehati kami dan memerintahkan kami untuk shalat dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka semuanya pun mengejeknya, kecuali aku dan sahabatku. Mereka mengejek dan mengolok-oloknya. Namun orang itu tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mengulang-ngulang perkataannya…. Mereka terus mengejeknya namun ia tetap sabar mendakwahi mereka dengan kelembutan…. Selanjutnya aku dan sahabatku menemuinya dan memohon maaf…. Kami mohon maaf kepadanya atas perbuatan teman-teman kami. Maka ia pun berkata kepada kami, ‘Apakah kalian berdua menyangka aku terpengaruh, sedih, atau dadaku terasa sempit disebabkan ejekan-ejekan mereka? Sama sekali tidak. Sebab aku berdakwah karena mengharapkan pahala. Tatkala aku diam aku mengharapkan pahala, begitu juga tatkala aku berbicara dan memaafkan, lantas kenapa aku harus bersedih?’
وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ
“Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.” (QS. an-Nahl: 127)
Perkataannya tersebut sangat menyentuh hatiku, lebih dari tatkala melihatnya bersabar dalam menasehati kami….”
Bagaimanakah cara agar engkau dapat memberi manfaat bagi masyarakat? Apakah engkau memberi manfaat kepada mereka dengan menguasai (bersikap keras kepada) mereka? Anakmu saja –padahal ia adalah anakmu, di rumahmu, yang keluar dari tulang sulbimu, yang dididik oleh dirimu sendiri-, jika engkau menggunakan sikap keras kepadanya niscaya ia tidak ridha, maka bagaimanakah lagi dengan orang lain?” (Dari ceramah beliau yang berjudul Ahkam al-Amr bil Ma’ruf wan Nahy ‘anil Munkar)
Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, “Banyak saudara-saudara kita, yang semangat dalam ber-Islam dengan keislaman yang benar, tatkala melihat kaum muslimin lain yang menyimpang dari al-Kitab dan Sunnah karena kebodohan, maka kita dapati sikap penghinaan, perendahan, dengki, dan kebencian (dari mereka) terhadap orang-orang yang menyimpang tersebut. (Padahal), banyak Syaikh (yang menyimpang) membolehkan istighasah kepada para wali dan orang-orang shalih, apalagi yang (kesesatannya) kurang dari itu, seperti ber-tawassul kepada mereka…. Mereka juga membolehkan untuk melakukan wisata berulang-ulang ke kuburan-kuburan dan ber-tabarruk (ngalap berkah) dengannya. Demikian seterusnya. Sebagian lain melarang untuk mengikuti al-Kitab dan Sunnah dengan alasan bahwa orang awam tidak memahami al-Kitab dan Sunnah, sehingga mereka diwajibkan untuk taqlid. Maka jadilah sikap suatu kelompok, yang mereka bersama-sama dengan kita di atas al-Kitab dan Sunnah dengan manhaj as-Salafus shalih, adalah memusuhi dan membenci mereka dengan kebencian yang sangat, sehingga tidak mungkin bertemu antara yang satu dengan yan
g lain. Ini adalah kesalahan. Aku katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat dari kebenaran, mereka menyelisihi al-Kitab dan Sunnah, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah sesat…. Jika perkaranya demikian, maka mereka adalah orang-orang sakit yang wajib bagi kita untuk mengasihani dan prihatin kepada mereka, kita bermu’amalah mereka dengan kelembutan, kita dakwahi mereka sebagaimana dalam ayat yang lalu.
ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (an-Nahl: 125)
Kita terus bersikap demikian sehingga jelas bagi kita bahwa salah seorang dari mereka bersikeras (dalam kesesatannya) dan menentang kebenaran, sikap lembut sama sekali tidak memberikan faedah kepadanya, maka tatkala itu kita menerapkan firman Allah
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
“Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (al-A’raaf: 199) (Silsilah al-Huda wan Nuur, kaset no (735)
Peringatan
Penjelasan diatas tidaklah menunjukan seorang dai tidak boleh menggunakan kekerasan dalam berdakwah, karena sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, demikian juga para salaf juga terkadang menggunakan sikap keras dalam berdakwah jika memang hal itu mendatangkan maslahat (contoh paling nyata adalah praktek hajr yang mereka lakukan). Namun penjelasan diatas menunjukan bahwa asal dalam berdakwah adalah bersikap lembut, yang menunjukan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, dan para salaf asal dakwah mereka adalah dengan kelembutan, namun terkadang mereka bersikap keras karena kemaslahatan dakwah yang menuntut hal itu.
Hal ini menunjukan bahwa bukanlah dakwah yang terbaik adalah dakwah yang paling keras, sebagaimana juga sebaliknya bukanlah dakwah yang paling lembut adalah dakwah yang terbaik, namun yang benar adalah masing-masing diletakkan pada tempatnya.
Ibnu Taimiyyah berkata, “Dan syaitan menghendaki agar manusia bersikap berlebih-lebihan dalam segala perkara, jika syaitan melihatnya condong kepada sikap rahmat (kelmbutan) maka syaitanpun menghias-hiasi kelembutan tersebut hingga iapun tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah dan tidak timbul rasa ghirohnya (marahnya) dengan apa yang membuat Allah marah. Dan jika syaitan melihatnya condong kepada sikap kekerasan maka syaitanpun menghias-hiasi sikap keras tersebut pada perkara-perkara yang bukan karena Allah hingga iapun meninggalkan sikap ihsan, berbuat baik, kelembutan, menjalin silaturahmi, kasih sayang yang telah diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Ia melampaui batas dalam bersikap keras, maka diapun berlebihan dalam mencela, membenci, dan menghukumi lebih dari apa yang disukai oleh Allah dan RasulNya. Orang ini telah meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah berupa kasih sayang dan sikap ihsan (berbuat baik) maka jadilah ia tercela dalam hal ini. Ia juga telah bersikap berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang disyari’atkan oleh Allah dan RasulNya untuk bersikap keras hingga melampaui batas…” (Majmu’ Fatawa XV/292-293)
Oleh karena itu yang benar adalah bersikap lembut pada tempatnya dan sikap keras pada tempatnya, namun ingat asal dalam dakwah adalah sikap lembut.
Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata, “Sesungguhnya syari’at Islam yang sempurna datang dengan sikap lembut pada tempatnya, juga sikap kasar dan keras pada tempatnya yang sesuai. Disyari’atkan bagi seorang da’i yang menyeru kepada Allah agar bersifat lembut, halus, bijak, dan sabar, karena hal itu adalah lebih sempurna dalam memberikan manfaat dan pengaruh melalui dakwahnya, sebagaimana Allah telah memerintahkan hal ini dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membimbing kita dalam hal ini. Hendaknya seorang da’i juga berada di atas ilmu dan petunjuk pada perkara-perkara yang ia dakwahkan dan pada perkara-perkara ia larang, karena Allah berfirman:
قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
Katakanlah, “Inilah jalanku (agamaku). Aku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata” (Yusuf: 108)
Tidak semestinya seorang da’i untuk bersandar kepada sikap keras dan kasar, kecuali (1) tatkala dibutuhkan dan dalam keadaan darurat, dan (2) jalan pertama -yaitu dengan kelembutan- tidak berhasil mengantarkan pada tujuan. Dengan demikian seorang da’i yang menyeru kepada Allah melaksanakan dua aspek tersebut –yaitu sikap keras dan lembut- sesuai dengan haknya, dan berjalan di atas petunjuk syari’at dalam dua aspek tersebut.” (Majmuu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (III/207)
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin v berkata, “Apabila maslahat terdapat pada sikap kasar dan keras, maka wajib bagimu untuk menggunakannya. Jika sebaliknya, maka wajib bagimu untuk bersikap lembut dan halus. Jika perkaranya seimbang antara sikap lembut serta halus dan sikap kasar serta keras, maka wajib bagimu untuk bersikap lembut. Sebab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya Allah lembut dan menyukai kelembutan dalam semua perkara….'” (Syarh al-Arba’iin an-Nawawiyyah, hal 223)
Sebagian orang menjadikan prinsip asal dalam dakwahnya adalah sikap keras. Bahkan mereka menganggap sikap keras itulah yang paling benar. Semakin keras seseorang dalam dakwah maka semakin benarlah dakwahnya. Hal ini tampak dalam praktek dakwah yang mereka lakukan (lisaanul haal), meskipun lisan mereka mengingkari hal ini. Bahkan mereka mencela orang yang lembut dalam berdakwah. Mereka tidak ridha kecuali semua orang berdakwah seperti cara mereka. Lalu mereka menuduh orang yang berdakwah secara lembut dengan tuduhan yang beraneka ragam.
Hal ini telah disinggung oleh Syaikh as-Sa’di rahimahullah. Tatkala mengomentari ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap lembut Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau berkata, “Inilah akhlak Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang merupakan akhlak yang paling sempurna, yang dengan akhlak tersebut diperoleh masalahat-maslahat yang sangat besar dan berbagai mudharat tertolak dengannya. Hal ini bisa dilihat dalam praktek nyata. Lalu apakah layak bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya `, mengaku bahwa ia ber-ittiba’ dan meneladani Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian ia menjadi beban berat bagi kaum muslimin, berakhlak jelek, keras kepada kaum muslimin, berhati keras, juga berkata kasar dan keras? Jika ia melihat kaum muslimin melakukan suatu kemaksiatan atau adab yang jelek, ia pun segera meng-hajr mereka, murka, dan benci kepada mereka. Tidak ada sikap lembut dan halus pada dirinya, tidak memiliki adab, dan tidak mendapatkan taufiq. Akibatnya, timbul berbagai kerusakan akibat model mu’amalah semacam ini, juga mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan-kemaslahatan, sebagaimana yang terjadi. Sudah demikian (kondisinya), engkau masih mendapatinya merendahkan orang yang memiliki sifat-sifat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia justru menuduh orang tersebut memiliki sifat kemunafikan atau mudahanah, sementara ia sendiri menganggap dirinya sempurna dan mengangkat dirinya. Ia takjub dengan amalannya sendiri. Hal ini tidaklah timbul pada dirinya kecuali disebabkan kebodohan dan karena setan menghiasi amalannya serta menipunya.” (Taisir al-Kariim ar-Rahmaan fi Tafsiir Kalaam al-Mannaan, hal. 599, tafs
ir surat asy-Syuraa: 215)
Peringatan
Tujuan dari hajr adalah untuk berbuat ihsan dan kasih sayang kepada orang yang dihajr dan bukan untuk memuaskan hati atau membalas dendam.
Ibnu Taimiyyah berkata, “Dan demikianlah juga perihal membantah ahlul bid’ah baik dari kalangan Rofidhoh atau selain mereka, jika bantahan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan maksud bukan untuk menjelaskan kebenaran, memberi petunjuk kepada manusia, kasih sayang terhadap mereka, dan berbuat ihsan (kebaikan) kepada mereka, maka amal tersebut bukanlah amal sholeh…dan terkadang seseorang dihajr sebagai hukuman dan ta’ziir baginya dan maksud dari praktek hajr tersebut adalah agar dia dan juga orang-orang yang semisalnya berhenti dari perbuatan mereka, karena kasih sayang dan sikap ihsan (terhadap mereka yang dihajr) bukan untuk memuaskan hati dan membalas dendam” (Minhajus Sunnah V/239)
Beliau juga berkata, “Oleh karena itu hendaknya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa yang mereka lakukan hendaknya dia memaksudkan dengan hukumannya tersebut adalah untuk berbuat ihsan kepada mereka serta sikap kasih sayang kepada mereka sebagaimana seorang bapak tatkala memberi hukuman kepada anaknya, sebagaimana seorang dokter tatkala mengobati pasiennya. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata, إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ “Sesungguhnya aku bagi kalian seperti seorang ayah” (HR Abu Dawud I/3 no 8 dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani). Allah telah berfirman
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. (QS. 33:6)
…Sesungguhnya istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hanyalah menjadi ibu-ibu kaum mukminin karena mengikuti (posisi) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (yang merupakan ayah kaum mukminin). Kalau bukan karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti ayah maka tidaklah istri-istri beliau seperti para ibu. Para Nabi adalah para dokter dalam bidang agama, dan Al-Qur’an diturunkan sebagai obat bagi penyakit yang terdapat di hati. Seseorang yang menghukumi manusia dengan hukuman yang syar’i hanyalah merupakan wakil Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallammaka hendaknya ia bersikap sebagaimana sikap yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam” Minhajus Sunnah V/237-238
Abu ‘Abdilmuhsin Firanda Andirja
Artikel: www.firanda.com