BAHASAN KEDUA
RINCIAN MASALAH BERHUKUM DENGAN SELAIN YANG ALLOH TURUNKAN
Ada sembilan ( 9 ) keadaan ; enam ( 6 ) di antaranya adalah kufur akbar tanpa ikhtilaf, dan selebihnya ada tiga ( 3 ) yang diperselisihkan oleh sebagian mutaakhirin, dan yang benar bahwa ia termasuk kufur ashghor.
Keadaan Pertama : Istihlal ( menghalalkan )
Bentuknya : memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan dengan meyakini bahwa berhukum dengan selain yang Alloh turunkan adalah perkara yang boleh dan tidak diharamkan .
Hukumnya : para ulama sepakat bahwa ini adalah kufur akbar .
Dalilnya : ada dua ;
Pertama : kesepakatan Ahlus Sunnah atas kekafiran seorang yang menghalalkan sesuatu dari perkara haram. Berkata Ibnu Taimiyyah rahimahulloh : “ siapa saja yang melakukan keharaman dengan meyakini kehalalannya maka dia kafir dengan kesepakatan ( ulama ) . ( Sharim Maslul 3/ 971 )
Kedua : kesepakatan Ahlus Sunnah atas kafirnya seorang yang menghalalkan berhukum dengan selain yang Alloh turunkan .
Berkata Ibnu Taimiyah rahimahulloh : “ seseorang ketika menghalalkan sesuatu yang telah ada ijma’ atas keharamannya atau mengharamkan sesuatu yang ada ijma’ atas kehalalannya atau mengganti syariat yang telah disepakati, maka ia kafir murtad dengan kesepakatan fuqoha, dalam hal inilah turun firman Alloh Ta’ala – dalam salah satu dari dua pendapat – :
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 44 ), yakni ; dia adalah yang menghalalkan berhukum dengan selain yang Alloh turunkan ( Al Fatawa 3/267 ).
Keadaan pertama ini berkaitan dengan enam ( 6 ) masalah :
Masalah Pertama :
Menjadi kafir dalam keadaan ini walaupun tidak ( melakukannya yaitu ) memutuskan dengan selain apa yang Alloh turunkan, selam ia berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain yang Alloh turunkan .
Masalah Kedua :
Istihlal adalah perkara hati, sebab hakikat istihlal adalah : meyakini kehalalan sesuatu.
Berkata Ibnu Taimiyah rahimahulloh : “ dan istihlal adalah : meyakini bahwa hal tersebut halal baginya “ ( Sharim Maslul 3/971 ).
Berkata Ibnul Qayyim rahimahulloh : “ maka sesungguhnya Mustahill ( orang yang menganggap halal ) adalah : yang melakukan sesuatu dengan meyakini kehalalannya ( Ighatsatul Lahfan 1/382 ).
Berkata Ibnu Utsaimin rahimahulloh : “ al istihlal adalah seorang meyakini kehalalan sesuatu yang Alloh haramkan…dan adapun istihlal fi’ly maka dilihat : jika seseorang bermuamalah dengan riba dengan tidak meyakini halal tetapi terus-menerus melakukan ; maka ia tidak kafir ; karena tidak menghalalkannya “ ( Al Baab Al Maftuh 3/97 , liqa 50 , soal 1198 ).
· Saya berkata : maka karena ia merupakan perkara hati maka tidak dapat diketahui kecuali dengan penegasan lisan tentang apa yang ada dalam hatinya ( lihat masalah ketiga dan keempat ).
Masalah Ketiga :
Qarinah ( tanda-tanda ) tidak memiliki pengaruh dalam menghukumi istihlal terhadap seseorang, dalil hal itu adalah kisah seorang yang membunuh sekelompok kaum muslimin, saat Usamah bin Zaid radhiyallohu anhu berhasil mengalahkannya, ia segera mengucapkan syahadat, maka Usamah membunuhnya karena mengira bahwa orang tersebut mengucapkan syahadat hanyalah untuk meloloskan diri dari pedang. Maka hal ini diingkari oleh Nabi shollallohu alaihi wa sallam dengan sabda beliau : “ apakah engkau membunuhnya padahal ia telah mengucapkan La ilaha illalloh ?! “ ( Al Bukhary 4269, 6872 ). Berkata Usamah : beliau terus mengulang-ulanginya hingga aku berangan-angan jika baru hari itu aku masuk islam ( Al Bukhary 4269, 6872 , Muslim 273 ). Dalam lafadz lain : “ Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga bisa mengetahui apakah ia benar mengucapkan atau tidak ?! ( Muslim 273 ). Dan dalam satu riwayat : “ Bagaimana engkau akan berbuat dengan ( La ilaha illalloh ) jika kalimat ini datang di hari kiamat ?! ( Muslim 275 ).
· Saya berkata : jika diperkenankan menghukumi dengan qarinah sebagai tanda terhadap apa yang ada di hati tentu ijtihad Usamah bin Zaid dibenarkan, karena telah terkumpul banyak qarinah pada orang tersebut yang dapat menguatkan kesimpulan bahwa ia tidak benar-benar masuk islam, yang hampir tidak akan terdapat pada orang yang lain. Namun demikian, Nabi shollallohu alaihi wa sallam menyalahkan ijtihad shahabat mulia ini, dan beliau tidak menerima pengambilan qarinah sebagai dalil apa yang di hati, maka ijtihad selain shahabat tentu lebih berhak untuk disalahkan.
Berkata Al khathaby rahimahulloh : “ dalam sabda beliau ( apakah engkau telah membelah hatinya ) terdapat dalil bahwa hukum diambil dari zhahir, sedangkan sara’ir ( yang tersembunyi ) diserahkan kepada Alloh Subhanahu “ ( Ma’alimus Sunan 2/234 ).
Dan berkata Ibnu Taimiyah rahimahulloh : “ demikian pula iman ; ia memiliki permulaan dan kesempurnaan, zhahir dan bathin ; jika berkaitan dengan hukum duniawi berupa kewajiban dan hudud – seperti memelihara darah dan harta dan mawarits serta hukuman duniawi – ; maka dikaitkan dengan zhahir, tidak mungkin yang selain itu, sebab jika dikaitkan dengan bathin adalah mustahil, walau pun kadang dapat dilakukan, maka ia sangat sulit diketahui dan didapatkan, tidak diketahui dengan hasil yang didapat dengan melihat zhahir, dan tidak mungkin menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang tidak diketahui hal tersebut dalam bathinnya “ ( Al Fatawa 7/422 )
Dan berkata Ibnu Baz rahimahulloh tentang seorang yang tidak menghukumi dengan syariat Alloh : “ jika ia berdalih tidak menghalalkannya maka kita mengambil zhahir ucapannya dan tidak menghukuminya dengan kekafiran “ ( saya catat dari majlis beliau, syarh Al Baab At Tsalits min kitabil Iman Shahih Bukhary, tanggal 27/7/1417 h, dengan pembaca kitab Syaikh Abdul aziz As Sad-han waffaqohulloh ).
Masalah Keempat :
Istihlal tidak dapat dilihat dari perbuatan tidak pula dari pengulangan atau terus-menerus, hal ini dapat dibuktikan dari empat sisi :
– Sisi pertama : tidak ada seorang pun dari ulama terdahulu yang mengatakannya, jika baik tentu mereka telah mendahului kita
– Sisi kedua : hal itu berkonsekuensi adanya kontradiksi antara dua dalil dari Ijma’ :
1. Ijma’ tidak kafirnya seorang yang melakukan dosa , berkata Ibnu Abdil Barr rahimahulloh : “ telah bersepakat Ahlus Sunnah Wal Jamaah – mereka adalah ahli fiqh dan atsar – bahwa seorang tidak keluar dari islam dengan dosa – walau pun besar – ( Tamhied 16/315 ), dan ijma’ ini mutlak tidak memiliki qaid , sehingga umum mencakup orang yang mengulangi dan terus-menerus .
2. Ijma’ tentang kafirnya seorang yang menghalalkan dosa, berkata Ibnu Taimiyah rahimahulloh : “ barangsiapa melakukan keharaman dengan menghalalkannya maka dia kafir dengan kesepakatan ( ulama ). ( Sharim Maslul 3/971 ).
· Saya berkata : maka ketika mereka memutlakkan ijma’ ketidakkafirannya seorang yang melakukan dosa dan mutlaknya ijma’ kekafiran seorang yang menghalalkan suatu keharaman ; ini adalah dalil bahwa pengulangan dan terus-menerus tidak dianggap istihlal, ingatlah ini karena ia penting .
– Sisi ketiga : hal itu berkonsekuensi pengkafiran seluruh pelaku dosa, ini bertentangan dengan ijma Ahli Sunnah. Siapa
yang melakukan dosa sepanjang hayat dan terus-menerus mengulangi – perbuatannya – maka dia kafir menurut mereka, sebab telah dianggap menghalalkan apa yang Alloh haramkan, padahal dia tidak kafir berdasarkan Ijma’ Ahli Sunnah Wal Jamaah.
– Sisi keempat : hakikat istihlal adalah meyakini kehalalan sebagaimana telah lalu ( hal 11 ), dan tidak mungkin mengetahui keyakinan sesorang – dengan pasti – kecuali jika dia mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Karena itulah kita sering mendapati dari para pelaku maksiat berupa pengakuan dosa dan terpengaruhnya mereka dengan nasihat, dan terkadang ada dari mereka yang bertekad untuk bertaubat, sedangkan istihlal tidak mungkin disertai perasaan bersalah.
Masalah kelima :
Sebagian orang yang menyatakan bahwa istihlal dapat diketahui dengan perbuatan berdalil dengan hadits shahih tentang seorang yang menikahi istri ayahnya lalu Nabi Shollallohu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya.( Tirmidzy 1362, Nasa’iy 3331, Ibnu Majah 2607 ). Dalam sebagian lafadz hadits baliau memerintahkan untuk mengambil hartanya ( Abu Dawud 4475, Nasa’iy 3332 ), dan ada pula tambahan : ambillah khumus dari hartanya ( disandarkan oleh Ibnu Hajar dalam Ishabah kepada Nasa’iy dan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Khaitsumah dan Ibnu Sakan dan Al Barudy dan lainnya ), dan disandarkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma’ad kepada Ibnu Abi Khaitsumah dalam tarikhnya, namun saya tidak mendapatkan tambahan ini dalam Mujtaba Nasa’iy dan tidak pula dalam Sunan Ibnu Majah rahimallohul jamie’ ).
Hadits yang ada di dalamnya khumus ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim : berkata Yahya Ibnu Ma’in : Ini hadits shahih ( Zaadul Ma’ad 5/15 ), berkata Ibnu Hajar rahimahulloh : isnadnya hasan ( al Ishabah 1/314, dalam biografi Abu Qurrah Iyas ibnu Hilal Al Muzany radhiyallohu anhu ).
· Saya berkata : tambahan lafadz khumus menunjukkan beliau menganggapnya fai’, dan fai’ adalah seluruh harta yang diambil dari kaum kafir tanpa perang ( dikatakan oleh Ibnu Katsier rahimahulloh dalam tafsirnya 4/396, Al Hasyr 7 ), ini sekaligus menunjukkan bahwa ia dibunuh sebagi seorang murtad ( faidah ini disebutkan oleh Thahawy rahimahulloh dalam syarh ma’any al atsar 3/150 )
· Kemudian saya katakan : istidlal ( proses berdalil ) ini tidak benar : sebab Nabi Shollallohu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang itu menghalalkan dari dasar hatinya, hal ini ditunjukkan oleh empat hal :
Pertama : ahli jahiliyyah dahulu menghalalkan nikah dengan istri ayah ( ibu tiri ), dan menganggapnya sebagai bagian warisan, maka orang itu melakukan apa yang biasa dikerjakan ahli jahiliyah dengan meyakini kehalalannya.
Berkata As Sindy rahimahulloh: ( menikahi istri ayahnya ) : “ sesuai dengan kaidah hukum jahiliyah dimana mereka menikahi istri-istri ayah mereka dan menganggapnya termasuk warisan, karena itulah Alloh menyebutkan larangan hal ini secara khusus dalam firman-Nya :
{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]
Artinya : dan janganlah kalian menikahi wanita yang telah dinikahi ayah-ayah kalian ( QS. Nisa : 22 )
Maka lelaki ini mengikuti jalan mereka dengan meyakininya halal, sehingga ia menjadi murtad, dan dibunuh dengan sebabnya. Takwil hadits yang demikian ini bagi yang tidak berpendapat dengan zhahirnya ( Syarh Sunan Nasa’iy hadits No 3332 )
Kedua : para ulama rahimahumulloh membawa hadits ini kepada makna bahwa diketahui dari orang ini istihlal .
Berkata Ahmad rahimahulloh : “ kami berpendapat – Wallohu a’lam – bahwa ia melakukan itu dengan istihlal ( Masa’il Abdillah 3/1085/1498 ).
Berkata Thahawy rahimahulloh ; “ orang yang menikhi itu melakukannya dengan istihlal sebagaimana mereka biasa melakukan saat jahiliyah ; sehingga ia menjadi murtad , maka Rasululloh shollallohu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memperlakukannya seperti apa yang dilakukan kepada murtad ( Syarh ma’any al atsar 3/ 149 ).
Berkata Syaukany rahimahulloh : tidak bisa tidak harus membawa makna hadits ini bahwa orang tersebut … mengetahui keharaman dan melakukannya dengan istihlal , dan ini termasuk perkara yang mengkafirkan ) ( Naylul Author 7/131 ).
Ketiga : para ulama tidak mengkafirkan seorang yang berzina dengan ibu tirinya walau pun hal itu berulang kali !
· Saya berkata : jika kekufuran orang yang menikahi ibu tirinya ini hanya sekedar perbuatan bukan karena istihlal hati, maka tentu dikafirkan juga setiap yang berzina dengan ibu tirinya. Ingatlah poin penting ini .
Keempat : jika dianggap ; bahwa dalil ini tidak jelas maka harus dikembalikan kepada dalil muhkamah yang lain yang menjelaskan tidak dianggapnya qarinah untuk menyingkap apa yang ada dalam hati ; seperti hadits Usamah radhiyallohu anhu yang telah lalu ( hal 12 ), serta ijma Ahli Sunnah tetang ketidakkafiran pelaku maksiat walau pun besar dosanya dan ijma’ ulama tentang kekafiran siapa yang menghalalkan hal yang haram ( hal 11 ). Membawa dalil yang samar ( musytabah ) kepada yang jelas ( muhkam ) adalah metode Ahli Sunnah, berbeda dari Ahli Bid’ah. Alloh Ta’ala berfirman :
{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } [آل عمران: 7]
Artinya : Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal ( QS. Ali Imran : 7 ).
Masalah Keenam :
Terkadang para ulama mensifati sebagian ahli maksiat dengan ( istihlah ) menghalalkan dengan hanya melihat perbuatannya saja walau pun tidak disertai keyakinan ( halal ) di hati , namun mereka tidak mengkafirkannya, istilah ini ( menghalalkan –pent) walau pun memang ada namun sejatinya adalah perluasan dalam ungkapan yang tidak dimaksudkan takfier, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah .
Keadaan kedua : Al juhuud (menentang )
Bentuknya adalah : memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan disertai penentangan terhadap hukum Alloh.
Hukumnya : para ulama sepakat bahwa keadaan ini mengkafirkan dengan kufur akbar.
Dalil dalam hal ini ada dua :
Pertama : kesepakatan Ahli Sunnah atas kekafiran seorang yang menentang sesuatu dari agama Alloh, berkata Ibnu Baz rahimahulloh : “ demikianlah hukum bagi seorang yang menentang sesuatu dari apa yang Alloh wajibkan… maka ia kafir murtad dari islam…dengan ijma’ ahli ilmu “ ( Al Fatawa 7/78 )
Kedua : kesepakatan Ahli Sunnah atas kekafiran seorang yang menentang kewajiban berhukum dengan apa yang Alloh turunkan, berkata Muhammad ibnu Ibrahim rahimahulloh tentang keadaan ini : “ ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan di antara ulama…sesungguhnya ia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari agama “ ( Tahkimul Qawanien hal 14 ).
Ada empat ( 4 ) masalah yang berkaitan dengan keadaan kedua ini :
Masalah pertama :
Menjadi kafir dalam keadaan ini walau pun tidak memutuskan dengan selain apa yang Alloh turunkan, selam ia menentang hukum Alloh Ta’ala .
Masalah kedua :
Al Juhuud adalah masalah hati ; sebab hakikatnya adalah : mengingkari dengan dhahir namun mengakui dengan bathin. Alloh berfirman :
{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} [النمل: 14]
Artinya :dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) Padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan ( QS. Naml : 14 )
Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang menentang terkadangmasih meyakini dalam hatinya lawan dari apa yang ia tentang dengan dhahirnya.
Berkata Ar Raghib Al Ashfahani rahimahulloh : “ Juhuud : menafikan apa yang ditetapkan hati, dan menetapkan apa yang dinafikan hati “ ( Al Mufradat hal 95 , jahada ).
Berkata Al Fairuz Abady rahimahulloh : “jahadahu :…. mengingkari disertai ilmu “ ( Al Qamus Al Muhith 1/389 )
· Saya berkata : dan segala yang berupa perkara hati tidak dapat diketahui kecuali dengan penegasan tentang apa yang di dalam jiwa ( lihat tentang istihlal hal 11 dan seterusnya )
Masalah Ketiga :
Tidak ada pengaruh qarinah dalam menghukumi bahwa seseorang telah juhuud ( lihat kembali keterangan tentang istihlal halaman 12 dan seterusnya ).
Masalah Keempat :
Para ulama terkadang mensifati sebagian pelaku maksiat dengan juhuud, hanya dengan melihat perbuatannya walau pun tidak berkaitan dengan keyakinan hati, tetapi mereka tidak mengatakan kekafirannya. Maka ungkapan ini – walau memang ada – adalah perluasan istilah yang tidak dimaksudkan untuk takfier, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.
Keadaan ketiga : takdzieb ( mendustakan )
Bentuknya : berhukum dengan selain yang Alloh turunkan dengan mendustakan hukum Alloh .
Hukumnya : sepakat ahli sunnah atas kekafiran orang yang mendustakan Alloh dan Rasul-Nya .
Berkata ibnu taimiyah rahimahulloh : kemudian dikatakan : jika kalian berkata “ ia adalah pembenaran dengan hati atau dengan lisan atau dengan keduanya”, apakah itu tashdieq 9 pembenaran mujmal ) ? atau harus tafshiel ( rinci ) ? jika seorang membenarkan Muhammad sebagai utusan Alloh tetapi tidak mengetahui sifat-sifat Alloh, apakah menjadi mukmin ? atau tidak ? jika mereka menjadikannya mukmin, dikatakan : jika sampai hal itu lalu ia mendustakan, maka dia bukan mukmin dengan kesepakatan kaum muslimin “ ( Al Fatawa 7/152 )
Beliau juga berkata rahimahulloh : “setiap yang mendustakan apa yang dibawa para rasul maka ia kafir “ ( Al Fatawa 2/79 )
Keadaan ini terkait dengan beberapa masalah.
Masalah pertama :
Kafir dengan keadaan ini walau tidak memutuskan dengan selain apa yang Alloh turunkan, selama ia mendustakan hukum Alloh Ta’ala.
Masalah kedua : Alloh berfirman :
{فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: 33]
Artinya : karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah ( QS. Al An’am 33 )
Dalam ayat ini Alloh menafikan dari mereka takdzieb kepada Nabi shollallohu alaihi wa sallam dan menetapkan juhuud mereka, yang menunjukkan perbedaan antara takdzieb dengan juhuud. Termasuk di antara perbedaan antara keduanya adalah seorang yang juhuud meyakini dalam hatinya hal yang berbeda dari apa yang ia tentang, sebagaimana telah dijelaskan ( hal 16 ), adapun orang yang mendustakan maka dia tidak meyakini dalam hatinya selain apa yang ditampakkan dari pendustaan.
Masalah Ketiga :
Takdzieb adalah perkara hati, yang hakikatnya adalah ; mendustakan sesuatu dengan dzahirnya dan meyakini kedustaan itu dalam bathinnya.
Berkata Ibnul Qayyim rahimahulloh : “ adapun kufur takdzieb maka dia adalah meyakini kedustaan para rasul “ ( Madarijus Salikin 1/346 ).
· Saya berkata : dan karena ia adalah perkara hati maka tidak dapat diketahui kecuali dengan pernyataan tentang apa yang ada dalam hati ( lihat kembali bahasan istihlal hal 11 dan seterusnya )
Masalah Keempat :
Tidak ada pengaruh bagi qarinah dalam menghukumi pelaku suatu perbuatan bahwa ia mendustakan ( lihat keterangan istihlal hal 12 dan seterusnya )
Masalah Kelima :
Terkadang para ulama mensifati sebagian pelaku maksiat dengan takzieb dan itu adalah dengan sekedar melihat perbuatannya walaupun tidak berkaitan dengan keyakinan hati, tetapi mereka tidak mengkafirkannya. Maka ungkapan ini – walaupun memang ada – hanyalah perluasan dalam penggunaan istilah , yang tidak dimaksudkan untuk takfier, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.
Keadaan Keempat : Tafdhiel ( mengutamakan )
Bentuknya : memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan dengan meyakini bahwa hukum selain Alloh lebih afdhol / lebih baik dari hukum Alloh.
Hukumnya : para ulama sepakat bahwa keadaan ini mengkafirkan dengan kufur akbar.
Dalil masalah ini ada dua :
Pertama : seorang yang meyakini hal ini adalah mendustakan firman Alloh :
{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]
Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki ? ( Hukum ) siapakah yang lebih baik daripada ( hukum ) Alloh bagi orang-orang yang meyakini ( agamanya ) ? ( QS. Al Maidah : 50 ).
Yakni ; tidak ada seorang pun yang hukumnya lebih baik dari hukum Alloh.
Kedua : Ijma’, berkata ibnu Baz rahimahulloh : “ barangsiapa berhukum dengan selain yang Alloh turunkan dengan memandang hukum lebih baik dari syariat Alloh maka dia kafir menurut seluruh kaum muslimin “ ( Al Fatawa 4/416 ).
Hal ini berkaitan dengan tiga masalah .
Masalah pertama :
Dalam keadaan ini, pelakunya menjadi kafir walaupun tidak memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan, selama ia meyakini bahwa hukum selain Alloh Ta’ala lebih baik dari hukum Alloh Ta’ala.
Masalah kedua :
Tafdhiel adalah perkara hati; sebab hakikatnya adalah : meyakini lebih baiknya sesuatu daripada yang lain.
· Saya berkata : selama hal ini adalah perkara hati, maka tidak dapat diketahui kecuali jika ditegaskan dengan ucapan tentang apa yang di hati itu ( lihat rincian hal ini dalam istihlal hal 11 dan seterusnya ) .
Masalah Ketiga :
Tidak bisa menghukumi seorang dengan tafdhiel sekedar dari tanda-tanda ( qarinah ).
Masalah Keempat :
Terkadang para ulama mensifati sebagian pelaku maksiat dengan ta
fdhiel atau mendahulukan taat kepada syaithon di atas ketaatan kepada Alloh, dan hal itu adalah dengan sekedar melihat perbuatan tanpa mengaitkan dengan keyakinan hati, namun mereka tidak mengkafirkannya. Maka ungkapan ini – walaupun memang ada – hanya perluasan istilah yang tidak dimaksud untuk mengkafirkan, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.
Keadaan kelima : Musaawaah ( menyamakan )
Bentuknya : memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan dengan meyakini persamaan hukum selain Alloh dengan hukum Alloh .
Hukumnya : para ulama sepakat bahwa keadaan ini menyebabkan kafir dengan kufur akbar.
Dalilnya : seorang yang meyakini hal ini berarti mendustakan firman Alloh Azza Wa Jalla :
{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]
Artinya : ( Hukum ) siapakah yang lebih baik daripada ( hukum ) Alloh bagi orang-orang yang meyakini ( agamanya ) ? ( QS. Al Maidah : 50 ).
Yakni ; tidak ada seorangpun yang lebih baik hukumnya daripada hukum Alloh.
Berkata Syaikh Bin Baz rahimahulloh saat menjelaskan pembatal keempat dari pembatal islam : “ termasuk bagian keempat ini : setiap yang berkeyakinan bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat manusia itu lebih baik dari syariat islam, atau SAMA, atau boleh mengambil hukum kepadanya… “( Al Fatawa 1/132 ).
Hal ini berkaitan dengan empat masalah .
Masalah pertama :
Menjadi kafir dalam keadaan ini walaupun tidak melakukan tindakan berhukum dengan selain yang Alloh turunkan, selama meyakini persamaan hukum selain Alloh Ta’ala dengan hukum Alloh Ta’ala.
Masalah kedua :
Meyakini persamaan adalah perkara hati ; sebab hakikatnya adalah : hati meyakini persamaan antara keduanya.
· Saya berkata : karena ia merupakan perkara hati maka tidak dapat diketahui kecuali dengan pernyataan tentang apa yang di dalam hati ( lihat kembali rincian istihlal hal 11 )
Masalah ketiga :
Qarinah tidak memiliki pengaruh dalam menghukumi seorang bahwa dia meyakini persamaan ( lihat masalah istihlal hal 12 dan seterusnya ).
Masalah keempat :
Sebagian ulama kadang mensifati sebagian pelaku maksiat dengan kata menyamakan ketaatan kepada syaithon dengan ketaatan kepada Alloh hanya dengan melihat perbuatan dan tidak dikaitkan dengan keyakinan hati, namun mereka tidak mengkafirkannya. Maka istilah ini – walaupun digunakan- merupakan perluasan penggunaan istilah yang dimaklumi dan tidak dimaksudkan untuk mengkafirkan, sehingga nukilan semacam ini tidak bisa dijadikan hujjah.
Keadaan Keenam : Tabdiel ( merubah )
Bentuknya : memutuskan hukum dengan selain yang Alloh turunkan dengan mengira bahwa keputusan itu adalah hukum Alloh.
Hukumnya : para ulama bersepakat bahwa hal ini mengkafirkan dengan kufur akbar.
Dalilnya adalah : Ijma’, berkata Ibnu Taimiyah rahimahulloh : “ dan seseorang kapan saja menghalalkan yang haram yang disepakati keharamannya, atau mengharamkan yang halal yang disepakati kehalalannya, atau mentabdiel ( merubah ) syariat yang telah disepakati maka ia kafir murtad dengan kesepakatan fuqoha “ ( Al Fatawa 3/267 ).
Hal ini berkaiatan dengan enam masalah :
Masalah pertama :
Kekufuran dalam keadaan pertama ini memiliki kaitan dengan keadaan juhuud ; sebab ketika seorang menisbatkan hukumnya kepada hukum Alloh maka sesungguhnya ia menentang hukum Alloh yang ditinggalkan .
Masalah kedua :
Pemerintah menjadi kafir dalam keadaan ini jika mentabdil dalam satu masalah, atau sekali, dan tidak diperhitungan jumlahnya, karena ijma’ tidak dikaitkan dengannya, dan tidak boleh membatasi dalil tan[pa dalil.
Masalah ketiga :
Sebagian salah ketika mengira bahwa tabdiel tidak berkaitan dengan penisbatan hukum baru kepada agama, hal ini akan dijelaskan dalam empat sisi berikut :
– Sisi pertama : Ibnul Araby berkata – dan ini dinukil oleh Syinqithy dari Qurthuby dan beliau menyetujuinya – : “ jika menghukumi dengan hukum sendiri dengan anggapan itu dari sisi Alloh maka inilah tabdiel yang berkonsekuensi kufur “ ( Ahkamul Quran 2/625 ), ( Adhwa’ul Bayan 1/407 )
– Sisi kedua : berkata Ibnu Taimiyah rahimahulloh : “ Syara’ Mubaddal : adalah dusta atas nama Alloh dan Rasulnya , atau atas manusia dengan persaksian palsu dan semisalnya dan kezaliman yang jelas. Barangsiapa berkata : “ sungguh ini dari syariat Alloh “ , maka dia kafir tanpa perselisihan “ ( Al Fatawa 3/268 )
· Saya berkata : beliau mentafsirkan tabdiel sebagail hukum yang disangka dari sisi Alloh, dan disebut sebagai kedustaan atas nama alloh dan Rasul-Nya, dengan menyebut ucapan pentabdil : “ ini dari syariat Alloh “.
– Sisi ketiga : jika sekedar merubah saja ( tanpa menganggap dari Alloh –pent ) adalah tabdiel tentu menyebabkan kontradiksi antara dua Ijma :
1.Ijma’ atas kafir orang yang mentabdiel, dan ini adalah ijma mutlak yang tidak memiliki qaid ( syarat tertentu ), berkata Ibnu Taimiyyah rahimahulloh : “ dan seseorang kapan saja menghalalkan yang haram yang disepakati keharamannya, atau mengharamkan yang halal yang disepakati kehalalannya, atau mentabdiel ( merubah ) syariat yang telah disepakati maka ia kafir murtad dengan kesepakatan fuqoha “ ( Al Fatawa 3/267 ).
2. Ijma’ atas ketidakkafirannya seorang yang berbuat dzalim dalam hukum. Berkata Ibnu Abdil Barr rahimahulloh : “ dan para ulama telah berijma’ bahwa kedzaliman dalam hukum termasuk dosa besar bagi yang menyengaja melakukan dalam keadaan ia mengetahui “ ( Tamhied 16/ 358 ).
* Saya berkata : maka dapat kita pastikan bahwa tabdiel bukan sekedar mengganti saja, sebab ijma’ memutlakkan kekufuran dengan sebab tabdiel, dan ijma ketidakkafiran perilaku dzalim yang merupakan mengganti / merubah tanpa menisbatkan hukum yang baru itu kepada agama. Ingatlah poin penting ini .
– Sisi keempat : ini berkaitan dengan yang sebelumnya yaitu : jika tabdil adalah sama dengan istibdal, maka harus mengkafirkan pelaku dosa, seperti orang yang mencukur habis jenggotnya dan yang isbal dengan sombong ; karena keduanya juga mengganti ( istibdal ) , dimana mengganti hukum Alloh dengan hukum hawa nafsunya .
Berkata Ibnu Hazm rahimahulloh : “ Alloh berfirman :
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 44 )
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim ( QS. Al Maidah : 45 )
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq ( QS. Al Maidah : 47 )
( Ibnu H
azm berkata ) : “ maka wajib bagi Mu’tazilah untuk menegaskan kekafiran setiap pelaku maksiat dan dzalim dan fasiq, karena setiap yang melakukan maksiat telah berhukum dengan selain yang Alloh turunkan “ ( Alfashl 3/278 ).
Masalah keempat : sebagian tokoh yang memiliki keutamaan menyangkal penjelasan bentuk tabdiel yang demikian dengan mengatakan bahwa hal seperti itu tidak ada dalam kenyataan. Sangkalan ini terbantah dengan dua hal :
1. Pendapat bahwa hal ini tidak ada dalam kenyataan hari ini, memilki nilai kebenaran, namun mengatakan bahwa hal ini tidak ada dalam kenyataan samasekali maka tidaklah benar ; sebab hal ini dahulu terjadi pada Yahudi berupa hukuman tahmiem ( menghitami ) wajah pezina dan meninggalkan hukum had, maka Naby shollallohu alaihi wa sallam bertanya kepada mereka : “ apakah yang kalian dapati dalam Taurat tentang rajam ? mereka menjawab : “ mempermalukan mereka, dan mereka dicambuk ( Bukhary 3635 ), dalam sebuah lafadz : “ kalian tidak mendapati rajam dalam taurat ? mereka mengatakan : kami tidak menemukannya sama sekali ( Bukhary 4556 ), maka saat seorang pembaca mereka dipeintah untuk membaca taurat, ia meletakkan tangannya ( untuk menutupi ) ayat rajam, ia melewati ayat tersebut ( Bukhary 4556 ), jadi mereka menentang hukum Alloh dan merubah dengan hukum lain dengan menganggapnya sebagai hukum Alloh .
2. Tujuan perincian hal ini adalah bukan untuk mencocokkan tabdiel dengan kenyataan pemerintah hari ini, melainkan meneliti bentuk tabdiel yang dimaksud oleh ulama terdahulu, walau kenyataannya sedikit terjadi atau jarang atau bahkan tidak ada.
Masalah kelima :
Sebagian yang menyelisihi gambaran tabdiel diatas, berdalil dengan ucapan Bukhary rahimahulloh : “ maka Abu Bakar tidak menoleh kepada musyawarah sebab beliau memiliki hukum Rasululloh shollallohu alaihi wa sallam pada orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat serta ingin mengganti ( tabdiel ) agama “ ( Shahih Bukhary sebelum hadits no 7369 ).
Sejatinya, pendalilan ini tidak benar , sebab Bukhary bermaksud terhadap suatu kaum yang terjatuh dalam tabdiel yang saya jelaskan, sebab mereka mengira meninggalkan zakat adalah agama, mereka berdalil bahwa zakat tidak ditunaikan kecuali kepada Rasul shollallohu alaihi wa sallam, dengandasar firman Alloh :
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } [التوبة: 103]
Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka ( QS. Taubah 103 ).
Hal ini dibuktikan oleh apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahulloh : “ berkata Qadhy Iyadh dan selainnya : Ahli Riddah ada tiga jenis ….. dan jenis ketiga mereka masih di atas islam namun menetang zakat, mereka mentakwil bahwa zakat khusus di zaman Nabi shllallohu alaihi wa sallam, merekalah yang dahulu Umar mendebat Abu bakar saat hendak memerangi mereka seperti tercantum dalam hadits bab ini “ ( Fathul Bari 12/288, sebelum hadits no 2924 ).
Keadaan Ketujuh : Istibdal ( mengganti )
Bentuknya : memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan tanpa sifat yang telah lalu .
Yaitu mengganti hukum Alloh dengan hukum selain-Nya, tanpa istihlal, tanpa juhuud, tanpa takdzieb, tanpa tafdhiel, tanpa musawaah dan tanpa menisbatkan hukum itu kepada agama Alloh .
Hukumnya : kufur ashghar ( = tidak mengeluarkan dari agama islam ) .
Dalilnya ; dua hal, yaitu :
1. Ijma’ mereka atas ketidakkafiran pemimpin dzalim, berkata ibnu Abdil Barr rahimahulloh : “ dan para ulama telah berijma bahwa kedzaliman dalam hukum termasuk dosa besar bagi yang menyengaja melakukan dalam keadaan ia mengetahui “ ( Tamhied 16/ 358 ), seorang yang memutuskan dengan dzalim adalah melakukan istibdal ( penggantian ), sebab tidak ada perbedaan antara keduanya , dimana dia menjadi dzalim tentunya setelah mengganti hukum Alloh dengan hukum selainnya.
2. Tidak ada dalil yang menunjukkan kufur akbar, sehingga bisa menolak ijma yang telah disebutkan dan dikafirkan muslim yang telah ditetapkan keislamannya dengan yakin ini.
Ada enam masalah yang berkaitan dengan keadaan ini .
Masalah Pertama :
Terdapat perbedaan dalam hal mengganti hukum Alloh antara istilah tabdiel dan istibdal, sebagaimana telah lalu ( hal 20 dan seterusnya ), dapat dijelaskan secara umum perbedaan tersebut dari dua sisi :
Pertama : dalam gambaran masalah, dimana tabdiel disertai persangkaan bahwa yang diputuskan itu adalah hukum Alloh Ta’ala, adapun istibdal maka tidak terdapat persangkaan itu.
Kedua : dalam vonis hukum, yang melakukan tabdiel adalah kafir dengan ijma ulama, adapun yang melakukan istibdal maka tidak ada dalil tentang kekafirannya.
Masalah kedua :
Barangsiapa mengkafirkan dengan istibdal maka ia wajib mengkafirkan dengan sekedar meninggalkan berhukum dengan apa yang Alloh turunkan, sebab tidak tergambar adanya seorang menjadi penguasa dan meninggalkan hukum Alloh Azza Wa Jalla, kemudian duduk tanpa memutuskan apapun ! maka hukum istibdal seperti hukum meninggalkan tanpa perbedaan .
· Saya berkata : dan takfir dengan sebab tark mujarrod ( sekedar meninggalkan, bukanlah pendapat seorang pun dari ahli sunnah wal jamaah, bahkan bertentangan dengan atsar Abdullah ibnu Syaqiq rahimahulloh : “ dahulu para shahabat Muhammad shollallohu alaihi wa sallam tidak melihat suatu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir selain shalat “ ( Tirmidzy 2622, Alhakim 1/7/12. Al Marwazy dalam “Ta’dziem qardi shalat “ 948, dishahihkan Al Hakim dengan syarat Syaikhain, disepakati Dzahaby, sebagaimana dishahihkan Al Albany dalam shahih targhib 564 ).
Jika dikatakan : bukankah takfir dengan meninggalkan ( tark ) adalah zhahir firman Alloh :
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]
Jawab : benar, itulah zhahir ayat, namun ahli sunnah wal jamaah telah berijma’ untuk tidak mengambil zhahir ayat ini, bahkan menetapkan bahwa siapa yang mengambil ayat ini dari dhahir saja maka ia adalah Khawarij dan Mu’tazilah .
Berkata Al Ajjury rahimahulloh ; “ dan termasuk ayat mutasyabihat yang diikuti Haruriyah adalah firman Alloh Azza Wa :
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]
Kemudian mereka membaca bersama firman Alloh :
{ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1]
Artinya : Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka ( QS. Al An’am 1 ).
Maka jika mereka melihat pemimpin memutuskan tanpa haq , mereka berkata : dia kafir ! dan barangsiapa kafir maka telah berbuat syirik ! maka para pemimpin itu musyrikun ! lalu mereka memberontak dan melakukan apa yang engkau lihat, karena mentakwilkan ayat ini “ ( As Syariah 44 ).
Berkata Ibnu Abdil Barr rahimahulloh : “ dan telah sesat sekelompok dari ahli bid’ah dari kalangan khawarij dan mu’tazilah dalam masalah ini, maka mereka berhujah dengan atsar ini dan yang semisalnya untuk mengkafirkan pelaku dosa, mereka berhujah dari kitabulloh dengan ayat-ayat yang semestinya tidak difahami dengan dzahir saja seperti firman Alloh Azza Wa Jalla : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, Maka mereka itu a
dalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 44 )
Berkata Al Qurthuby rahimahulloh : “ Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 44 ), yang berhujjah dengan dhahir ayat ini adalah yang mengkafirkan dengan dosa-dosa yaitu kaum khawarij, dan sejatinya mereka tidak memiliki hujjah di dalamnya “ ( Al Mufhim 5/117 ).
Berkata Abu Hayyan Al Andalusi rahimahulloh : “ dan khawarij berhujjah dengan ayat ini bahwa setiap yang bermaksiat kepada Alloh Ta’ala adalah kafir, mereka mengatakan : ini adalah nash bagi setiap orang yang memutuskan hukum dengan selain yang Alloh turunkan ; maka dia kafir , dan setiap yang berdosa maka berarti telah memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan : maka wajib menjadi kafir “ ( Al Bahrul Al Muhith 3/493 ).
Dan berkata muhammad Rasyid Ridha rahimahulloh : “ adapun dhahir ayat ini maka tidak ada seorangpun dari imam fiqih yang masyhur berpendapat dengannya, bahkan tidak ada seorang pun[1] berkata denga ( dzahir ) nya “ ( Tafsir Al Manar 6/336 ).
Masalah Ketiga :
Barangsiapa dikafirkan dengan istibdal maka harus dikafirkan dengan semua bentuk berhukum dengan selain yang Alloh turunkan, dan ini adalah perkara yang Ahli Sunnah berijma dalam menyelisihinya, ini dapat dibuktikan dengan dua sisi :
1. Mereka telah sepakat bahwa di antara bentuk berhukum dengan selain yang Alloh turunkan ada yang bukan kufur akbar, berkata Ibnu abdil Barr rahimahulloh : “ dan para ulam telah berijma bahwa kedzaliman dalam hukum termasuk dosa besar bagi yang sengaja lagi mengetahui “ ( Tamhied 16/358 ).
2. Bahwa setiap yang memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan pasti melakukan istibdal ( penggantian ) hukum Alloh dengan hukum selain-Nya, selalu disifati istibdal padanya.
Masalah keempat :
Siapa yang mengkafirkan dengan istibdal berarti harus mengkafirkan orang yang Ahli Sunnah telah berijma’ akan ketidakkafirannya, yaitu para pelaku dosa, sebab seorang yang bermaksiat tentu telah mengganti hukum Alloh dengan hukum selain-Nya ( = hawa nafsu dan syaithon ).
Berkata Ibnu Hazm rahimahulloh : “ maka sungguh Alloh Azza Wa Jalla berfirman : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 44), Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim( QS. Al Maidah : 45 ) , Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq ( QS. Al Maidah : 47), maka menjadi suatu keharusan Muktazilah untuk menegaskan bahwa setiap pelaku maksiat dan pendzalim serta fasiq adalah kafir, sebab setiap yang melakukan maksiat berarti tidak berhukum dengan apa yang Alloh turunkan “ ( Al Fashl 3/278 ).
Masalah kelima :
Sebagian orang yang utama berpendapat bahwa pemerintah yang melakukan istibdal menjadi kafir kufur akbar jika ia mengganti semua syariah, dan ini terbantah ; karena dalil-dalil syar’iy tidak menyebutkan adanya pembedaan antar mengganti satu hukum dengan lebih dari satu, dan kekufuran tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Benar, mengganti syariah seluruhnya ( membabat syariah ) bisa ( dikatakan ) lebih jahat daripada yang melakukan pada sebagiannya, namun yang menjadi titik pembahasan adalah kekafiran yang tidak ada dalilnya , bukan masalah mana yang lebih jahat.
Maka dari itu dikatakan : jika mengganti syariat seluruhnya menjadi kafir, maka apakah hukum yang mengganti seperempatnya ? atau setengahnya ? atau dua pertiganya ? dan seterusnya .., hingga kita akan sampai pada satu pertanyaan yang akan menyibakkan tidak adanya dalil, yaitu : apakah hukum orang yang mengganti syariah seluruhnya kecuali satu hukum saja ?…jika dikafirkan , maka berarti telah menyelisihi apa yang telah ditetapkan dia sendiri bahwa manath ( illat = sebab ) takfir : adalah mengganti seluruhnya ! dan jika dia tidak mengkafirkannya maka berarti telah mendatangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal yang sehat !
· Saya berkata : jika telah jelas bahwa mengganti keseluruhan ini perkara yang tidak bisa ditentukan dengan tepat, maka ketahuilah pula bahwa takfir dengan perkara ini adalah hal yang tidak mungkin diterapkan walaupun menurut mereka yang menganggapnya kufur akbar ! sebab seluruh negeri kaum muslimin – yang belum berhukum dengan syariah – pasti menerapkan hukum agama Alloh walau pun pada perkara yang remeh, sedikit atau banyak, maka hilanglah illat takfir yaitu “ mengganti keseluruhan “.
Masalah keenam :
Sebagian orang yang utama tersebut mengkafirkan keadaan in i dengan berdalil aqidah talaazum ( saling berkaitan ) antara dzahir dan bathin yang telah ditetapkan Ahli Sunnah, hal ini tidak benar karena :
1. Ini adalah istidlal dengan hal yang tidak menunjukkan hal yang ingin ditetapkan
2. Ini adalah berdalil dengan perkara yang sedang diperselisihkan ( mahallunnizaa’ ).
Penjelasannya adalah ; akidah ahli Sunnah menetapkan bahwa jika seorang memiliki kebaikan atau kerusakan pada dzahir maka itu sesuai dengan kerusakan atau kebaikan yang ada di dalam bathin.
Berkata Ibnu Taimiyyah rahimahulloh : “ kemudian hati adalah pokok ; jika dalam hati ada pengetahuan atau keinginan maka hal itu akan tampak di badan secara otomatis, tidak mungkin berbeda dari apa yang diinginkan hati, karena itulah Nabi shollallohu alaihi wa sallam bersabda dalam hadits shahih : “ ketahuilah bahwa dalam jasad terdapat segumpal daging, jika ia baik maka akan baik seluruh jasad , dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh badan, ketahuilah bahwa ia adalah hati “, …apabila hati dalam keadaan baik karena memiliki amal, ilmu dan amal hati, maka otomatis akan baik jasad dengan ucapan yang baik, dan amal menjadi baik dengan iman mutlak, sebagaimana dikatakan para imam hadits ; ( iman adalah ) ucapan dan perbuatan, ucapan bathin dan dhahir, amalan batin dan dhahir, dan dhahir adalah mengikuti bathin menyertainya, kapan batin baik maka dhahir baik, kapan rusak maka rusak pula “ ( Al Fatawa 7/187 ).
Sebagai penerapan pokok ini, dapat diterangkan : tidak ragu lagi bahwa siapa yang mengganti hukum syariah seluruhnya maka ia memiliki kerusakan di batin yang sangat besar sesuai kadar yang ia tampakkan , yaitu : mengganti syariat Alloh seluruhnya .
Namun ingat, bahwa titik bahasan kita adalah memeriksa kerusakan yang ada di dhahir ini – yang ditimbulkan kerusakan semisal itu di bathin – apakah pelakunya sampai batas kufur akbar sehingga dihukumi dengan kufur akbar ? atau tidak ?
Sesungguhnya untuk menjawab pertanyaan ini, harus meneliti dalil-dalil syar’iy yang lain yang memberi hukum kepada dhahir ini, yang samasekali tidak berkaitan sedikitpun dengan masalah talaazum bayna dhahir wal bathin.
Kemudian jika mereka mengatakan ; kadar yang di dhahir itu jelas hukumnya kufur akbar .
Dijawab : manakah dalil bahwa kadar seperti itu menyampaikan pelakunya kepada kufur akbar ?… jika ia berdalil dengan akidah talaazum , maka ini adalah pendalilan dengan perkara yang diperselisihkan, yang tidak menunjukkan maksud, semestinya berdalil dengan dalil lain, ini yang diminta .
Sebagian contoh tambahan penerapan akidah talaazum ini : jika kita dapati pencuri / perampok tentu kita katakan bahwa tidak mungkin ia melakukan ,maksiat itu kecuali karena cacat pada imannya, semakin luas rusak/ cacat pada imannya maka semakin bertambah ia melakukan dosa ini, akan tetapi untuk menghukumi bahwa kerusakan iman i ni telah mengeluarkan dari agama islam atau tidak, maka kita harus melihat kepada dalil-dalil syar’iy yang menghukumi bahwa dosa yang tampak itu ( pencurian ) , maka ternyata kita dapati bahwa dalil-dali menghukumi bahwa dia kurang iman bukan hilan
g iman sehingga kita tidak hukumi kafir.
Dapat menjadi jelas lagi dengan contoh berikut : Ahli Sunnah tidak berselisih bahwa pezina tidaklah kafir walau pun berzina seribu kali !…maka anda dapati bahwa bertambahnya dosa ini ( zina ) telah menjatuhkan hukum bahwa bertambah pula kerusakan di bathin, namun menetapkan bahwa kerusakan ini menyampaikan kepada batas kufur yang mengeluarkan dari agama adalah tidak lagi berkaitan dengan akidah talaazum, tetapi diambil dari dalil syar’iy yang lain yang menjelaskan hukum dhahir ini .
Saya akan tutup pembahasan ini dengan apa yang disebutkan Al Albany rahimahulloh tentang firman Alloh Ta’ala ; “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 44) : barangsiapa beriman kepada syariat Alloh Tabaraka Wa Ta’ala, dan bahwa ia baik di setiap tempat dan waktu, namun ia tidak memutuskan – dalam perbuatan – dengannya ; baik seluruhnya atau sebagian atau satu bagian, maka ia mendapat bagian dari ayat ini ! mendapat bagian dari ayat ini, namun bagian ini tidak menyampaikannya hingga keluar dari lingkup islam “ ( Silsilah Al Huda Wa Nur , kaset 218, menit 29 )
Keadaan kedelapan : Taqnien ( menyusun undang-undang )
Bentuknya : memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan yaitu dengan hukum yang ia buat sendiri .
Artinya, dialah yang membuat hukum atau undang-undang itu, tanpa istihlal, tidak pula juhuud, tidak takdzieb atau pun tafdhiel atau menyamakan, dan tidak menisbatkan hukum yang ia buat kepada agama Alloh .
Hukumnya : kufur ashghar ( = tidak keluar dari agama islam ).
Dalilnya : tidak ada dalil yang menyebutkan takfirnya, sebab syariah tidak mengkaitkan kufur akbar dengan sumber hukum, sebagaimana dalil-dalil tidak membedakan antara seorang yang menghukumi dengan hukumnya sendiri dengan yang menggunakan hukum orang lain.
· Saya berkata : jika pembedaan itu benar tentu tidak akan dilalaikan oleh syariat, dan tentu akan datang dalil-dalil yang mendukungnya.
Keadaan ini berkaitan dengan empat masalah :
Masalah pertama :
Pemerintah yang membuat hukum yang menyelisihi syariat bisa jadi lebih besar kejahatannya daripada yang tidak melakukannya. Namun pembahasan kita adalah kekufuran yang tidak ada dalilnya, bukan tentang lebih berat atau lebih ringan kejahatannya.
Masalah kedua :
Sebagian tokoh yang berdalil atas takfir dengan keadaan ini mengatakan bahwa dengan membuat undang-undang berarti ia telah menyaingi Alloh Ta’ala dalam satu kekhususannya , yaitu : Tasyrie’ ( membuat syariat ).
· Saya katakan : yang benar adalah bahwa hal ini harus dirinci, sebab orang yang membuat undang-undang tidak lepas dari dua keadaan :
Keadaan pertama : melakukan hal itu dengan menganggap dirinya memiliki hak tasyrie’ dengan ia mengungkapkannya dengan lisan dan tidak sekedar melakukan ; maka dia kafir dengan kufur akbar tanpa ragu lagi ; karena ia menghalalkan perkara yang Alloh Ta’ala haramkan .
Keadaan kedua : melakukannya ( membuat aturan ) tanpa mengklaim hal itu ; maka dia tidak kafir karena tiga sebab :
1. Tidak ada dalil atas kekafirannya.
2. Ahli sunnah tidak mengkafirkan teman buruk yang merencanakan dosa dan menghiasinya dan mengajak kepadanya…orang seperti ini kafir menurut mereka, padahal ia tidak kafir dengan kesepakatan ahli sunnah.
3. Ahli sunnah tidak mengkafirkan tukang gambar yang tidak menghalalkan menggambar yang haram. Allah berkata tentang mereka dalam hadits qudsi : “ siapakah yang lebih dzalim daripada seorang yang hendak menciptakan seperti yang Aku ciptakan ? “ ( Bukhary 5953, Muslim 5509 ). Dan bersabda Rasululloh shollalloh alaihi wa sallam tentang mereka : “ manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyaingi ciptaan Alloh “ ( Bukhary 5954, Muslim 5494 ).
Dan tidak ada perbedaan antara keduanya, sebab penggambar / pematung telah menjadikan dirinya pencipta bersama Alloh, dan pembuat hukum menjadikan dirinya pembuat aturan bersama Alloh, sehingga siapa yang mengkafirkan pembuat aturan maka ia harus mengkafirkan pembuat patung/gambar . Keduanya sama…maka tukang gambar kafir menurut yang menetapkan ini , padahal ia tidak kafir dengan kesepakatan ahli sunnah .
· Saya berkata : kesepakatan ahli sunnah atas tidak kafirnya teman buruk dan tukang gambar adalah dalil qath’iy atas apa yang saya terangkan tadi. Ingatlah hal penting ini !
Masalah ketiga :
Sebagian orang tersebut berdalil atas kekafiran dengan keadaan ketiga ini dengan mengatakan bahwa seorang yang menyusun undang-undang menjadi thaghut yang hukumnya dirujuk selain hukum Alloh, pendalilan ini tidak benar dan dapat dijelaskan dari dua sisi :
Sisi pertama : pendapat ibni dibanguin dari dasar yang tidak benar, yaitu bahwa setiap thaghut pasti kafir ! kesalahan ini dilihat dari tiga hal ;
1. Kata thaghut dimaksudkan untuk : “ setiap pemimpin kesesatan “ , sebab kata ini diambil dari kata thughyan yang artinya : melampaui batas.
Berkata Al Qurtubhy rahimahulloh : “ yaitu : tinggalkanlah setiap yang disembah selain Alloh ; seperti setan dan dukun dan berhala, dan setiap yang mengajak kepada kesesatan “ ( tafsir 5/75, tafsir QS. 16 ( Nahl ) : 36 )
Berkata Al Fairuz Abady rahimahulloh : thaghut : … dan setiap pemimpin kesesatan, dan berhala, dan apa saja yang disembah selain Alloh, dan orang jahat dari ahli kitab ( Al Qamus Al Muhith 4/400, thogho ).
· Saya berkata : thughyan – jika begitu – kadang dikafirkan dan kadang tidak sampai derajat kafir, karena itulah Syaikh Ibnu Baz rahimahulloh berkata : “ maka batas bagimu adalah dengan menjadi seorang yang taat kepada Alloh, jika engkau melewati batas itu maka engkau adalah thaghut dengan apa yang kau lakukan itu….yang bisa kafir, bisa juga di bawah itu “ ( Syarh tsalatsatil Ushul , kaset 2, side b, produksi Bardain Riyadh ).
2. Ada sebagian ulama yang mensifati seorang sebagai thaghut dengan sekedar melihat perbuatan melewati batas, tanpa melihat keadaan pelaku :
a. Karena mereka mendefinisikan thaghut sebagai : “ setiap yang hamba melampaui batas baik dengan diibadahi , diikuti atau ditaati “ ( disebutkan ibnul qayyim rahimahulloh ( a’lamul muwaqiien 1/50 ) )
Ibnu Utsaimin rahimahulloh mengomentari dengan mengatakan : “ maksudnya yaitu yang ridha, atau dikatakan : dia thaghut dengan melihat orang yang menyembah , mengikuti atau mentaatinya ; karena ia telah melewati batas kedudukan yang diberikan oleh Alloh, sehingga perbuatan menyembah, mengikuti dan mentaatinya itu disebut thughyan, karena melampaui batas dengan itu “ ( Al Qaul Al Mufid 1/30 ).
· Saya berkata : maka tidak mesti seorang yang disifati thoghut adalah kafir ; karena bisa disebut thaghut dengan hanya melihat sikap orang kepadanya, bukan keadaan dia .
b. Sebagaimana para ulama menyebut benda-benda mati yang diibadahi selain Alloh sebagai thaghut, padahal jelas bahwa benda mati juga tidak disifati islam sebagai lawan kufur.
Berkata Ibnul Jauzi rahimahulloh : “ berkata ibnu qutaibah : setiap yang diibadahi : berupa batu atau gambar atau setan, maka dia jibt dan thaghut. Demikian diceritakan Zajjaj dari para ahli bahasa “ ( Nuzhatul A’yun An Nawadzir hal 410 , bab thaghut ) .
Berkata Ibnu Taimiyyah rahimahulloh : “ ia adalah ism jins ( kata jenis ) yang masuk padanya : setan, dan berhala dan dukun , dan dinar serta dirham dan selainnya “ ( Al Fatawa 16/565 ).
· Saya berkata : jika setiap thaghu
t adalah kafir tentu bis mengkafirkan benda-benda mati .
3. Para ulama juga menyebut para pelaku dosa yang tidak mengkafirkan sebagai thaghut .
Berkata Ar Raghib Al Ashfahany rahimahulloh : “ Thaghut adalah istilah bagi ; setiap yang melampaui batas dan setiap yang disembah dari selain Alloh …. dan karena itulah : disebut tukang sihir dan dukun dan yang jahat dari jin dan yang menyimpangkan dari jalan kebaikan sebagai thaghut “ ( Al Mufradaat hal 108 , thagha ).
Berkata Muhammad ibnu Abdil Wahhaab rahimahulloh : “ dan thaghut itu banyak , yang jelas ada lima : yang pertama setan dan pemimpin yang dzalim dan pemakan riba dan yang diibadahi dengan ia ridha dan setiap yang beramal tanpa ilmu “ ( Durar Saniyyah 1/137 ).
Berkata Ibnu Utsaimin rahimahulloh : “ dan ulama buruk yang menyeru kepada kesesatan dan kekufuran atau menyeru kepada bid’ah atau kepada menghalalkan apa yang Alloh haramkan atau mengharamkan yang Alloh halalkan adalah : THAGHUT “ ( Syarh Ushul Tsalatsah hal 151 ).
· Saya berkata : jika setiap thaghut kafir tentu tidak boleh dijelaskan dengan demikian, yang berkonsekuensi mereka mengkafirkan dengan dosa maksiat .
Sisi kedua : hal ini berkonsekuensi juga mengkafirkan orang yang Ahli sunnah telah sepakat ketidakkafirannya . yaitu seorang yang merencanakan dosa ; sebab tidak ada perbedaan – dalam taqnien – antara seorang yang menulis rencana maksiat dengan yang menulis undang-undang hukum yang selain Alloh turunkan, sebab keduanya telah melakukan taqnien dalam perkara yang haram .
Contohnya : segerombolan orang yang bertekad merampok dan mengangkat pemimpin serta membuat aturan, maka pemimpi ini yang telah mengajak mereka lalu merencanakan kejahatan dan perampokan serta menakuti kaum muslimin hingga menjalankannya, dialah pula yang memerintah , mereka ikut , melarang dan mereka mentaati, pemimpin seperti ini berarti telah melakukan taqnien ( rencana tertulis ) , namun ia tidak kafir .
· Saya katakan : jika pengkafiran dengan hal ini benar , tentu harus mengkafirkan pelaku dosa seperti ini, padahal ia termasuk pelaku maksiat yang Ahli sunnah bersepakat akan ketidakkafiran mereka .
Masalah keempat :
Keadaan ini adalah perkara yang paling sengit perdebatan antara penuntut ilmu, hanya saja ulama abad ini ; Ibnu Baz, AlBany, dan Ibnu Utsaimin rahimahumulloh bersepakat akan ketidakkafirannya.
Berkata Ibnu Baz rahimahulloh : “ jika ia membuat undang-undang yang berisi bahwa pezina tidak ada hukuman had, atau pencuri tidak terkena hukum had…. maka undang-undang ini bathil, dan jika pemimpin meyakini halal ( istihlal ) maka ia kafir “ ( Al Fatawa 7/124 )
Dan lihatlah pula ucapan Al Albany rahimahulloh tentang ketidakkafiran seorang yang menyusun undang-undang kecuali jika istihlal dalam “ Silsilah Al Huda Wa Nur “ ( kaset 849 , menit 72 ).
Berkata Ibnu Utsaimin rahimahulloh : “ berhukum dengan selain yang Alloh turunkan bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari agama , namun kufur amaly ( ashghar ) , karena pemerintah yang melakukannya berarti keluar dari jalan yang benar. Dan tidak dibedakan antara yang mengambil undang-undang buatan dari luar lalu menerapkan di negaranya dengan yang membuat dan menerapkan undang-undang buatan ini ; karena yang penting adalah apakah undang-undang ini menyelisihi undang-undang langit ? atau tidak ?[2] ( Fitnah Takfir hal 25, footnote 1 )
Keadaan kesembilan : Tasyrie’ Aam ( pembuatan aturan umum )
Bentuknya : memutuskan dengan selain yang Alloh turunkan dan menjadikan hukum ini berlaku umum bagi setiap yang di bawahnya .
Artinya : ia mengganti hukum Alloh dengan hukum selain-Nya, dan mewajibkan setiap orang yang di bawahnya melaksanakan hukum ini, tanpa istihlal, tanpa juhuud, tanpa takdzieb , tanpa tafdhiel, tanpa menyamakan dan tidak menisbatkan hukum yang dibuat kepada agama Alloh .
Hukumnya : kufur ashghar .
Dalilnya : tidak ada dalil yang mengkafirkannya, maka syariah tidak pernah mengkaitkan kufur akbar dengan pemberlakuan umum atau dengan mewajibkannya. Sebagaimana dalil-dalil tidak membedakan antara pemerintah yang menerapkan secara umum atau yang tidak demikian, atau antara pemerintah yang mewajibkan bagi yang dibawahnya atau yang tidak demikian .
· Saya katakan : jika pembedaan ini benar tentu tidak akan ditinggalkan oleh syariah, dan tentu akan datang dalil yang banyak yang mendukungnya .
Ada enam masalah berkaitan dengan hal ini :
Masalah pertama :
Benar bahwa seorang yang menetapkan hukum umum dan mengharuskan semua orang yang di bawahnya untuk mengikuti bisa dianggap lebih jahat daripada yang tidak membuat hukum umum atau mewajibkan. Tetapi pembahasan kita adalah : kekafiran yang tidak ada dalilnya , bukan meneliti yang lebih jahat .
Masalah kedua :
Sebagian orang yang utama berdalil akan kekafiran keadaan kedua ini dengan Laazim ( konsekuensi ) ; yaitu tidak mungkin seorang mengganti hukum Alloh dengan hukumnya lalu menjadikan hukumnya menjadi hukum umum bagi siapa saja yang di bawahnya kecuali pasti ia berkeyakinan bahwa hukumnya lebih bermanfaat dan lebih baik dari hukum Alloh, pendalilan ini terbantah dari empat sisi :
Sisi pertama : para ulama telah menetapkan bahwa lazim madzhab bukanlah madzhab kecuali jika ia mengetahui dan menetapinya . Dan bahwa seseorang mungkin saja meyakini yang bukan menjadi konsekuensi pendapatnya, walaupun disebut kontradiktif jika ia tidak berpendapat dengan lazim itu .
Berkata Ibnu Taimiyyah rahimahulloh : “ lazim madzhab belum tentu menjadi madzhab, bahkan kebanyakan manusia berpendapat dengan berbagai hal yang mereka tidak menerima konsekuensinya ; sehingga seorang yang berpendapat dengan pendapat yang berkonsekuensi ta’thil belum tentu berakidah ta’thil, bahkan kadang berpendapat itsbat namun ia tidak mengetahui konsekuensinya “ ( Al Fatawa 16/461 ) .
Beliau juga berkata rahimahulloh : “ adapun jika konsekuensi itu diridhai olehnya setelah jelas baginya ; maka itu uga pendapatnya , adapun jika tidak meridhainya, maka bukan pendapatnya, walaupun ia akan kontradiktif…. adapun jika ia menafikan konsekuensi itu maka tidak boleh dinisbatkan hukum konsekuensi itu kepadanya sama sekali “ ( Al Fatawa 29/42 ).
Beliau rahimahulloh juga berkata ; “ adapun ucapan seorang : apakah laazim madzhab adalah madzhab ? ataukah bukan madzhab ? maka yang benar : bahwa laazim madzhab seseorang bukanlah madzhabnya jika ia tidak menetapinya , sebab jika ia telah mengingkari atau menafikan maka penisbatan hal itu kepadanya adalah kedustaan atas namanya “ ( Al Fatawa 20/217 ) .
Sisi kedua :
Konsekuensi ini kadang tidak terjadi , dimana terkadang dijumpai seorang yang melakukan itu dengan masih meyakini bahwa syariah lebih bermanfaat daripada hukumnya ,seperti telah lalu pencontohan Ibnu Taimiyyah rahimahulloh dengan pendapat yang seakan berkonsekuensi ta’thil namun tidak otomatis orang tersebut termasuk ahli ta’thil .
· Saya berkata : tidak adanya konsekuensi itu menunjukkan bahwa kaidah ini tidak pasti ; sehingga tidak bisa dijadikan pegangan, terlebih dalam masalah pengkafiran yang tidak digunakan kecuali yang meyakinkan.
Sisi ketiga : bahwa Ahli sunnah tidak mengkafirkan kecuali dengan hal yang tidak ada kemungkinan lain padanya , sebab hukuman dicegah dengan kerancuan ( al huduud tudra’ u bi syubuhat ) , dan pengkafiran lebih berhak untuk dicegah .
Berkata Ibnu Taimiyyah rahimahulloh : “ siapa yang telah ditetapkan keislamannya dengan yakin maka tidak dapat dihilangkan ( status itu ) dengan syakk ( keraguan ) “ ( Al Fatawa 12/466 ) .
Dan berkata Muhammad Ibn Abdul Wahhaab rahimahulloh : “ kami tidak mengkafirkan kecuali yang para ulama seluruhnya telah bersepakat “ ( Durar Saniyyah 1/102 ) .
Sisi keempat : konsekunsi hal ini adalah harus mengkafirkan orang yang ahli sunnah bersepakat ketidakkafirannya, yaitu yang membuat aturan maksiat – yang di bawah kesyirikan – . Jika ada seorang ayah yang menetapkan maksiat pada keluarganya dan mewajibkan mereka, menyelesihi setelah diingkari dan tidak mendengar yang menasehati ; maka ia tidak kafir menurut Ahli sunnah, sedang menurut mereka yang menetapi pendapat ini maka ia kafir .
Masalah ketiga :
Sebagian mereka berdalil atas pengkafiran dengan keadaan ini berdasar hadits tahmiem yahudy ( lihat hal 22 ) , maka Alloh turunkan pada mereka ( sebagaimana dalam shahih Muslim 4415 ) :
{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41]
Artinya : hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya ( QS . Al Maidah 41 ) hingga firman Alloh :
{يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} [المائدة: 41]
Artinya : mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, Maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini Maka hati-hatilah”. ( QS . Al Maidah 41 )
Dan firman Alloh :
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 44 )
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim ( QS. Al Maidah : 45 )
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]
Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq ( QS. Al Maidah : 47 ).
Mereka berpandangan bahwa Alloh tidak menghukumi dengan kekafiran mereka kecuali karena mereka menjadikan tahmiem sebagai syariat umum . Dan pendalilan ini terbantah karena yahudi – yang dimaksud kafir dalam pendalilan dalam taysrie’ aam ini – telah kafir dengan selain tasyri ini, dapat dikjelaskan sebagai berikut :
1. Mereka mengingkari hukum Alloh pada pezina yang muhshan , inilah yang ditegaskan dalam banyak riwayat hadits, maka ketika Naby shollallohu alaihi wa sallam bertanya kepada mereka : “ kalian tidak mendapatkan rajam dalam taurat ? , mereka menjawab : kami tidak mendapatkan apapun ! ( Bukhary 4556 ), dan ketika pembaca mereka membacakan taurat , ia meletakkan tangannya di atas ayat rajam dan hanya membaca sebelum dan sesudah ayat rajam ! ( Bukhary 4556 ), dan pengingkaran ini adalah juhuud yang telah dijelaskan ( hal 15 ) bahwa sepakat bahwa ia kufur akbar .
2. Mereka melakukan tabdiel atau perubahan terhadap hukum Alloh pada zina yang muhshan, maka saat Beliau shollallohu alaihi wa sallam bertanya kepada mereka : “ apakah yang kalian dapatkan dalam taurat dalam hal rajam ? “ mereka menjawab : “ kami permalukan dan cambuk mereka “ ( Bukhary 3635 ), mereka telah merubah hukum Alloh lalu menisbatkan apa yang mereka buat sendiri kepada agama Alloh, inilah makna tabdiel yang telah lalu ( hal 20 ) bahwa telah disepakati bahwa ia kufur akbar. Karena itulah berkata Ibnu Abdil Barr rahimahulloh : “ dan dalam hadits ini pula : dalil bahwa mereka mendustakan taurat mereka , dan menisbatkan pendustaan mereka kepada Rabb mereka dan kitab mereka “ ( Tamhied 9 / 13 ) .
· Dengan ini : maka tidak benar berdalil dengan kisah ini untuk pengkafiran dengan Tasyrie’ Aam ; sebab yahudi terjatuh dalam dua hal yang Ahli Sunnah bersepakat akan kekafiran yang terjatuh walaupun dalam salah satu saja – apalagi keduanya – maka pengkafiran mereka dengan tasyrie’ aam membutuhkan dalil lain .
· Saya berkata : dan pengkaitan takfir dengan perkara dhahir – dalam banyak riwayat – yang ahli sunnah bersepakat atas kekafiran dengannya ( Juhuud atau Tabdiel atau keduanya ) lebih utama daripada dikaitkan dengan perkara yang diperselisihkan ini ( = tasyrie’ aam ) yang tidak ada dalil pengkafiran dengannya , dan tidak ada dalil bahwa kekufuran yahudi dikaitkan dengannya .
Masalah keempat :
Dahulu Ibnu Utsaimin rahimahulloh berfatwa pengkafiran dengan hal ini , hanya saja beliau rujuk / meralat kembali. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Fatwa terdahulu
Beliau rahimahulloh berkata : “ …. dan di antara mereka : ada yang menetapkan bagi manusia peraturan yang menyelisihi syariat islam , untuk menjadi jalan yang ditempuh manusia, maka mereka tidaklah menetapkan aturan yan g menyelisihi syariat islam kecuali pasti mereka meyakini bahwa aturan itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia, sebab diketahui secara pasti dengan akal, dan fitrah kelaziman bahwa seorang tidak akan berpindah dari satu jalan ke jalan lain yang menyelisihinya kecuali tentu ia meyakini keutamaan yang ia pilih dan kekurangan yang ia tinggalkan “ . ( Al Fatawa 2/143 ).
Beliau rahimahulloh juga berkata : “ sebab pembuat undang-undang yang menyelisihi islam ini ; hanyalah menetapkannya karena keyakinan bahwa itu lebih baik daripada islam dan lebih bermanfaat bagi manusia “ ( Al Fatawa 2/143 )
· Saya berkata : dalam fatwa ini ada tiga hal yang mesti diperhatikan :
1. Beliau berdalil untuk kekafiran pembuat hukum dengan laazim ( konsekuensi ), dan telah lalu ( hal 33 dan seterusnya ) bahwa pendalilan ini perlu ditinjau ulang.
2. Beliau mengembalikan pengkafiran dalam hal ini kepada akidah, maka sesungguhnya beliau sependapat dengan apa yang telah saya sebutkan dalam keadaan ini ( hal 33 ), hanya saja beliau mengkaitkan kekafiran dalam kondisi ini dengan laazim yang tidak pasti. Maka hendaklahmemperhatikan ini mereka yang berpegang dengan ucapan beliau dalam masalah ini dan berpandangan bahwa melihat keyakinan adalah irja ( murjiah ) !
3. Beliau tidak menetapi pendapat ini dan tidak menerapkan pengkafiran dengan laazim di selain masalah ini, jikalau pengkafiran dengan laazim adalah benar tentu selain beliau akan berpendapat dengannya dalam seluruh permasalahan pengkafiran.
Fatwa Terakhir
Beliau rahimahulloh berkata : “ jika ia mengetahui hukum syar’iy tetapi menghukumi dengan ini, atau menetapkan ini, dan menjadikannya undang-undang yang dijalani manusia ; ia meyakini berbuat dzalim dengan itu, dan bahwa yang benar adalah yang ada dalam Kitab dan Sunnah, maka kita tidak dapat mengkafirkannya dengan ini “ ( lihat fatwa dengan sempurna hal 29 ).
Masalah kelima :
Sebagian pihak mengklaim bahwa kondisi tasyrie’ aam tidak pernah terjadi kecuali di zaman belakangan ini, dibangun di atas kerangka ini : bahwa tidak benar berpegang bahwa ketidakakfirannya karena tidak ada dalil yang mengkafirkan, dan bahwa mutaqadimien / ulama terdahulu tidak mengkafirkan dengan kondisi ini. Hal ini salah karena dua perkara :
1. Semes
tinya juga tidak bisa berdalil untuk pengkafiran keadaan ini dalil apapun, dan ini tidak dikatakan oleh siapapun; karena digunakan dalil hal ini kisah tahmiem, dan telah lalu ( hal 34 ) jawaban pendalilan ini, dan bahwa manaath ( = sebab= illat ) pengkafiran dalam kisah ini bukan tasyrie’ aam.
2. Kondisi tasyrie’ aam ini telah terjadi sejak berabad yang lalu, dan tidak ada seorang pun dari ulama yang berfatwa pengkafirannya, diantara bentuknya : pajak yang diterapkan kepada muslimin di banyak negeri mereka sejak lama, dan diketahui bahwa pemerintah mewajibkan serta menghukum yang tidak mau membayarnya, padahal ini perkara haram, bahkan termasuk bentuk berhukum dengan selain yang Alloh turunkan, jika perkara ini mengkafirkan , tentu para ulama telah berbicara, dan menetapkan bahwa tasyrie’ aam itu kufur, dan tentu mereka tidak akan diam dari menjelaskan perkara yang mereka alami.
Masalah keenam :
Walaupun perkara ini termasuk perkara yang paling sengit perdebatan di kalangan akademisi, hanya saja tiga ulama besar abad ini : Ibnu Baaz dan Albany dan Ibnu Utsaimin rahimahumulloh sepakat atas ketidakkafirannya , ( lihat hal 39 ) .
[1] . ucapan beliau : ( tidak ada serang pun berkata dengan ( dzahir ) nya) : bisa difahami dari dua sisi; bisa jadi maksud beliau adalah pendapat Ahli Sunnah dan beliau tidak menyinggung khawarij, atau beliau bermaksud bahwa dosa kecil dan dosa besar masuk dalam keumuman ayat ini, yang khawarij tidak mengkafirkan kecuali dengan dosa besar saja.
[2] . maksud beliau rahimahulloh adalah : yang menjadi penilaian adalah apakah uu itu sesuai atau menyelisihi hukum syar’iy, dan tidak perlu dilihat sumber hukum itu, apakah pemerintah sendiri yang membuat atau mengambil dari selainnya ?
bersambung…
Penterjemah : Ustadz Abdul Hakim Lc
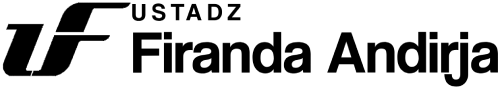







Assalamu’alaykum warrahmatullah wabarakatuh,
Barakallahu fiykum wa jazakumullaahu khayran yaa ustadz,
Afwan, ada sedikit salah ketik, pada “Keadaan Ketujuh : Istibdal ( mengganti )” di Masalah keempat tertulis:
Berkata Ibnu Hazm rahimahulloh : “ … Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( QS. Al Maidah : 45 )…“ ( Al Fashl 3/278 ).
Seharusnya di artikan:
Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim ( QS. Al Maidah : 45 )
Jazakumullahu khayran
Wassalamu’alaykum warrahmatullah wabarakatuh
Penjelasan yang sangat bagus ustadz. Sangat menjelaskan duduk permasalahannya.
Semoga seri kelanjutannya segera keluar. Dan semoga jika semua sudah selesai diterjemahkan, bisa diterbitkan atau dibuat ebook yang bisa di download.
Catatan : Mohon juga diterangkan perincian hukum mengenai “Demokrasi” dan “Konstitusi Negara” yang dikaitkan dengan penerapan qaidah-qaidah di tulisan yang lain ustadz.
Baarokalloohu fiik