Ahlus Sunnah wal Jama’ah menjadikan wahyu al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai cahaya yang menyinari jalan yang mereka tempuh. Hati, perasaan, akal, dan pikiran mereka tundukan di bawah naungan cahaya wahyu tersebut.
Adapun Ahlul Bid’ah maka agama mereka dibangun di atas perasaan mereka, atau hawa mereka, atau akal dan otak mereka. Dalil ayat maupun hadits apa saja yang tidak sesuai dengan perasaan dan akal mereka maka mereka tolak atau mereka simpangkan maknanya. Mereka menjadikan akal pendek mereka sebagai hakim yang menentukan kebenaran wahyu, jika sesuai dengan akal mereka maka wahyu tersebut mereka terima, jika tidak maka mereka buang atau mereka simpangkan maknanya. Akal pendek mereka didahulukan daripada wahyu yang turun dari Allah pencipta alam semesta ini.
Pengagungan Para Imam Mu’tazilah dan Asyaa’iroh Terhadap Akal
A. Para Imam Mu’tazilah
(1) ‘Amr bin ‘Ubaid (wafat 143 H), salah seorang pendiri madzhab mu’tazilah yang terkenal sangat zuhud. Akan tetapi terkenal menolak hadits-hadits yang shahih dengan akalnya. Al-Imam Adz-Dzahabi berkata :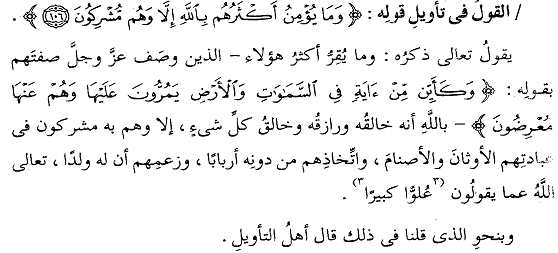
“Berkata Mu’aadz bin Mu’aadz : Aku mendengar ‘Amr bin ‘Ubaid berkata, “Jika ayat “Celaka kedua tangan Abu Lahab” berada di al-Lauh al-Mahfudz, maka Allah tidak punya hujjah/dalil terhadap anak Adam”.
Dan aku mendengarnya menyebut hadits As-Shoodiq al-Mashduuq (hadits Ibnu Mas’ud tentang janin 40 hari di rahim-pen) lalu ia berkata, “Kala aku mendengar al-A’masy menyebutkan hadits ini maka aku akan mendustakannya”…hingga ‘Amr bin ‘Ubaid berkata, “Kalau seandainya aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkannya maka aku akan menolaknya”
‘Aashim al-Ahwal berkata, “Aku tidur, lalu aku melihat ‘Amr bin ‘Ubaid menggaruk-garuk sebuah ayat (untuk menghapusnya-pen), maka akupun mencelanya. Lalu ia berkata, “Aku kembalikan lagi ayat yang sudah kuhapus ini?”, aku berkata, “Kembalikanlah !”. Lalu ia berkata, “Aku tidak mampu” (Siar A’laam An-Nubalaa 6/104-105, lihat juga Mizaan al-I’tidaal 3/278)
(2) Ibrahim An-Nadzzoom (yang wafat pada tahun 220 sekian Hijriyah, akibat jatuh dari kamarnya karena mabuk –silahkan lihat Siyar A’laam An-Nubalaa 10/541).
– Ia telah menganggap bahwa akal bisa menaskh(menghapus) dalil naql/wahyu. Setelah Al-Imam Ibnu Qutaibah (beliau wafat 276 H) menyebutkan tentang hadits-hadits shahih yang didustakan oleh An-Nadzzoom, lalu ia rahimahullah berkata: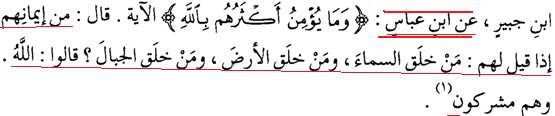
“Inilah perkataan An-Nadzdzoom sebagaimana telah kami jelaskan dan kami bantah. Dan ia juga memiliki perkataan yang lain tentang hadits-hadits yang dianggap menentang al-Qur’an dan hadits-hadits yang dianggap buruk dari sisi dalil akal, dan An-Nadzzoom menyebutkan bahwasanya dalil akal bisa menaskh-kan riwayat dan hadits-hadits” (Ta’wiil Mukhtalaf al-Hadiits, karya Al-Imam Ibnu Qutaibah hal 53, cetakan Mathba’ah Kurdistaan al-‘AAmiyah, cetakan tahun 1326 H)
– Ia juga membolehkan mugkinnya adanya kedustaan pada riwayat-riwayat yang mutawatir jika menyelisihi akal.
Abdul Qoohir Al-Baghdaadi berkata :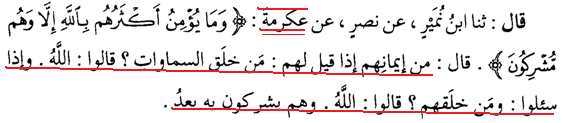
“Diantara perkara An-Nadzdzom yang memalukan adalah perkataannya bahwasanya khabar mutawatir –padahal perawinya sangatlah banyak, dan bervariasinya semangat dan motivasi-motivasi- bisa saja terjadi kedustaan. Padahal ia berpendapat bahwasa khabar ahad mengharuskan ilmu” (al-Farq baina Al-Firoq, karya Al-Baghdaadi, tahqiq : Muhyiddin Abdul Hamid, Mathba’ah Al-Madani, hal 143)
(3) Az-Zamakhsari (wafat 538 H) telah menggelari akal dengan sang Sultan. Ia berkata :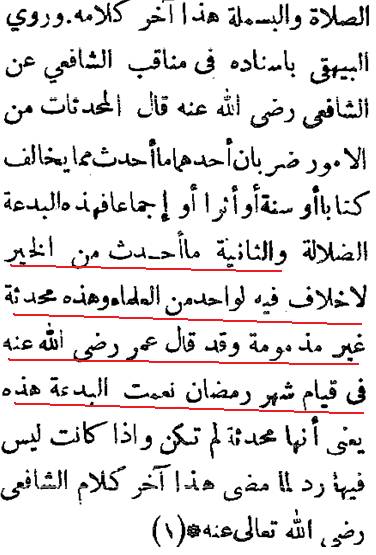
“Janganlah engkau menerima riwayat dari fulan dan fulan. Berjalanlah dalam agamamu di bawah bendera Sulthon. Tidaklah singa yang bersembunyi di sarangnya lebih perkasa dari seseorang yang berdalil mengalahkan lawannya. Dan tidaklah kambing yang kudisan yang terliputi angin yang berembun lebih hina dari seorang yang bertaqlid dihadapan pemilik dalil” (Athwaaq Adz-Dzahab karya Az-Zamakhsari, maqoolah ke 37, sebagaimana tercantum dalam Qolaaid al-Adab fi Syarh Athwaaq Adz-Dzahab, hal 71)
Al-Mirza Yusuf Khoon –tatkala menjelaskan perkataan Az-Zamakhsari ini- ia berkata :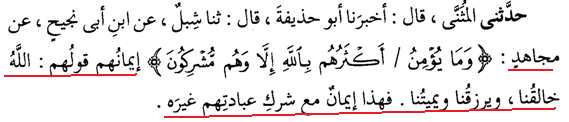
“Dalam kalimatnya ini Az-Zamakhsari mencela sikap taqlid dan ia berkata, “Janganlah engkau tenang dengan apa yang kau dengar berupa riwayat-riwayat yang musnad serta hadits-hadits yang dinukilkan. Akan tetapi tolonglah dalil naql dengan akal, genapkanlah riwayat dengan diroyah” (Qolaaid al-Adab fi Syarh Athwaaq Adz-Dzahab, hal 72)
Sangat jelas dalam sajak di atas bahwasanya Az-Zamakhsari memandang orang yang hanya mengikuti dalil naqli berupa riwayat dan hadits-hadits hanyalah seorang yang bertaqlid. Bahkan ia memandang bahwa orang yang seperti ini lebih hina dari pada pemilik dalil akal.
Az-Zamakhsari juga tatkala menafsirkan surat Yusuf ayat 111 ia berkata, “Karena qonun (hukum) yang dijadikan sandaran adalah sunnah, ijmak, dan qiyas, setelah dalil akal” (Al-Kasysyaaf : 3/331, tahqiq : Adil Ahmad Abdul Maujud, Maktabah Al-Ubaikaan, cetakan pertama). Di sini sangat jelas bahwasanya menurut Az-Zamakhsari bahwasanya akal lebih didahulukan dari pada sunnah, ijmak, dan qiyas.
B. Para Imam Asyaa’iroh
(1) Ibnu Faurok (wafat 406 H), ia telah menulis kitabnya “Musykil al-Hadits wa Bayaanuhu”. Dalam buku tersebut terlalu banyak dalil-dalil wahyu yang ia takwil dengan makna menyimpang.
Ia berkata di muqoddimah kitabnya tersebut :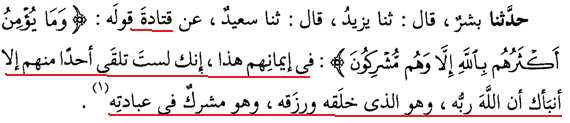
“Kami sebutkan dalam kitab tersebut hadits-hadits yang mashur yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dzohirnya mengesankan tasybiih (penyerupaan dengan makhluk-pen)” (Musykil al-Hadits wa Bayaanuhu, tahqiq : Daniel Jimariah, cetakan Ma’had al-Faronsi li ad-Dirosaat al-‘Arobiyah, Damaskus, hal 2)
Oleh karenanya mayoritas hadits-hadits yang menetapkan sifat-sifat Allah menurut akal Ibnu Faurok tidak bisa diterima dzohirnya karena menunjukkan tasybiih, karenanya iapun mentakwil/menyimpangkan dzohir hadits-hadits tersebut
(2) Abdul Qoohir al-Baghdaadi (wafat 429 H), ia telah mempersyaratkan agar suatu hadits diterima maka harus tidak bertentangan dengan akal. Ia berkata :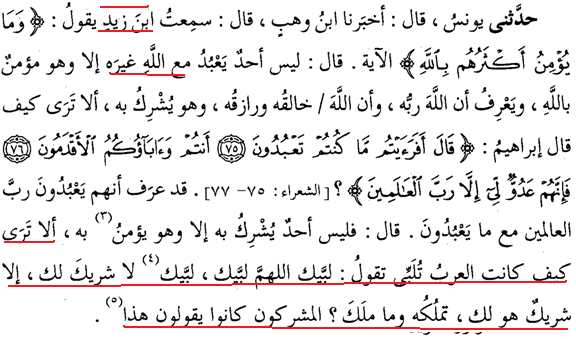
“Kapan saja sah suatu khobar (riwayat) dan matannya (makna lafal-lafalnya) bukanlah suatu hal yang mustahil menurut akal dan tidak ada dalil yang menunjukkan dinaskh hukumnya maka wajib untuk diamalkan” (Ushuul Ad-Diin hal 40, tahqiq : Ahmad Syamsuddiin, Daarul Kutub al-‘Ilmiyah, cetakan pertama 1423 H)
(3) Abu Hamid al-Gozali (wafat 505 H), ia berkata :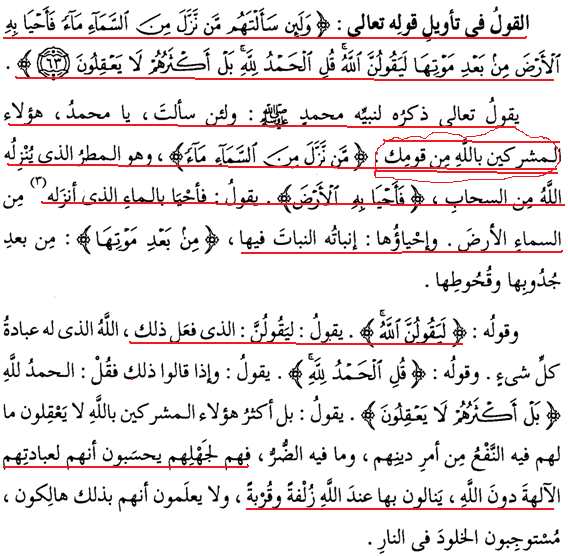
“Wasiat yang kedua, hendaknya dalil akal sama sekali tidak boleh didustakan, karena akal tidak bisa didus
takan. Kalau seandainya akal didustakan maka bisa jadi akal berdusta dalam penetapan syari’at, karena dengan akal-lah kita mengenal syari’at. Maka bagaimana diketahui kejujuran/kebenaran saksi dengan rekomendasi perekomendasi yang pendusta. Syari’at adalah saksi secara terperinci dan akal adalah perekomendasi syari’at” (Qoonun at-Takwiil hal 21, tahqiq : Mahmuud Bayjuu, cetakan pertama)
Lalu Al-Gozali menolak hadits-hadits yang menurutnya tidak masuk akal dengan mentakwil hadits-hadits tersebut. Iapun menolak adanya Allah diatas, juga menolak bahwasanya amal ditimbang, karena menurutnya amal adalah sesuatu yang abstrak tidak mungkin ditimbang, maka harus ditakwil. Demikian juga hadits tentang kematian didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk seekor kambing, maka ia menyatakan bahwasanya hal ini tidaklah mungkin mengingat bahwa kematian adalah sesuatu yang abstrak bukan sesuatu yang konkrit (lihat Qonuun At-Takwiil 21-22)
Al-Qoonun al-Kulliy
Istilah al-Qoonun al-Kulliy adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Fakhruddin Ar-Roozi (Muhammad bin ‘Umar bin Al-Husain, wafat 606 H). Al-Qoonun secara bahasa artinya hukum/undang-undang, adapun al-Kulliy secara bahasa artinya universal/keseluruhan. Maksud Ar-Roozi dengan al-Qoonun al-Kulliy yaitu menjadikan akal sebagai undang-undang yang berlaku secara universal dalam menentukan kebenaran dalil. Semua dalil baik dari al-Qur’an dan as-Sunnah harus ditimbang oleh akal.
Yang pada hakekatnya al-Qoonun al-Kulliy adalah bentuk “pengagungan akal di atas dalil”. Ar-Roozi tidaklah membawa sesuatu yang baru dalam hal ini, akan tetapi ia hanya melanjutkan para pendahulunya dari para imam al-Mu’tazilah dan para imam al-Asyaa’iroh –sebagaimana telah lalu nukilan perkataan-perkataan mereka-.
Ar-Roozi berkata –tentang al-Qonun al-Kulliy-:
“Ketahuilah bahwasanya dalil-dalil akal yang qoth’iy (pasti benarnya) jika telah menunjukkan akan tetapnya sesuatu lalu kita mendapatkan ada dalil-dalil naql (al-Qur’an dan hadits) yang dzohirnya mengesankan penyelisihan terhadap apa yang ditetapkan oleh dalil akal, maka kondisinya tidak akan lepas dari salah satu dari empat kemungkinan :
(Pertama) : Akal dan Naql kedua-duanya dibenarkan, maka ini adalah tidak mungkin, karena melazimkan pembenaran terhadap dua perkara yang saling kontradiktif
(Kedua) : Kita membatilkan kedua-duanya maka ini melazimkan pendustaan terhadap dua perkara yang saling kontradiktif dan ini juga mustahil
(Ketiga) : Kita mendustakan dzohirnya dalil-dalil naql (al-Qur’an dan Hadits) dan dzohirnya akal dibenarkan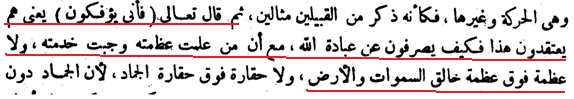
(Keempat 🙂 Atau membenarkan dzohirnya dalil naqli dan didustakan dzohirnya akal, dan tentunya hal ini adalah kebatilan, karena tidak mungkin kita mengetahui benarnya dzohir dari naql kecuali setelah kita mengetahui dengan akal kita adanya pencipta dan sifat-sifatnya, bagaimana penunjukan mukjizat akan kebenaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan munculnya mukjizat melalui tangan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kalau seandainya ada pencelaan terhadap pendalilan akal yang qoth’iy (pasti kebenarannya) maka jadilah akal itu diragukan dan tidak diterima keputusannya. Dan jika perkaranya demikian maka tentunya penetapan akal tidak bisa diterima dalam perkara-perkara usul/pokok ini (adanya Allah, sifat-sifat Allah, kebenaran Nabi dll-pen). Dan jika pokok-pokok (aqidah) ini tidak bisa ditetapkan maka jadilah dalil-dalil naql tidak berfaedah.
Kesimpulannya : Pencelaan terhadap akal untuk membenarkan naql melazimkan pencelaan terhadap akal dan naql sekaligus, dan bahwasanya ini adalah kebatilan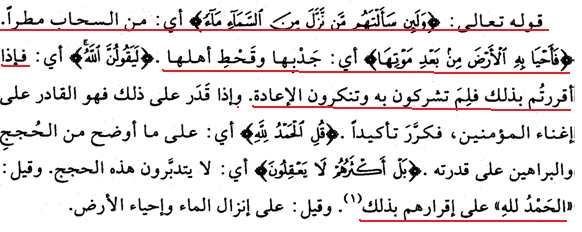
Dan tatkala empat kemungkinan di atas batil maka tidak tersisa kecuali memastikan sesuai dengan konsekuensi dari dalil-dalil akal yang qot’i : Bahwasanya dalil-dalil naql (al-Quran dan al-Hadits) tidaklah shahih atau dikatakan bahwasanya ia shahih akan tetapi maksudnya adalah tidak sesuai dengan dzohir lafalnya.
Kemudian jika kita membolehkan takwil maka kita menyibukkan diri –yaitu untuk mencari pahala/namun tidak wajib- dengan menyebutkan takwil-takwilan tersebut secara terperinci. Dan jika kita tidak membolehkan takwil maka kita serahkan ilmunya kepada Allah ta’aala. Inilah al-Qonun al-Kulliy (Undang-undang Universal) yang dikembalikan kepadanya seluruh dalil-dalil naql yang mutasyaabihaat” (Asaas at-Taqdiis 220-221, tahqiq : DR Ahmad Hijaazi As-Saqoo, Maktabah Al-Kulliyaat Al-Azhariyah)
SANGGAHAN
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitabnya “Dar’u Ta’aarud al-‘Aqli wa an-Naqli” telah menjelaskan lebih dari 40 sisi kerancuan al-Qoonuun al-Kully. Demikian juga Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam kitabnya “As-Showaa’iq al-Mursalah ‘alaa al-Jamiyah wa Az-Zanaadiqoh” juga telah membantah kerancuan al-Qoonun al-Kulliy dari puluhan sisi. Akan tetapi pada kesempatan ini kita hanya menukil dan meringkas beberapa sisi bantahan yang dipandang terpenting:
PERTAMA : Dalam al-Qonun Al-Kulliy Ar-Roozi mengesankan bahwa yang merupakan penunjukan qoth’iy (pasti benarannya) hanyalah dalil akal. Ini merupakan kekeliruan, karena seakan-akan tidak ada dalil naqliy (al-Qur’an dan al-Hadits) yang penunjukannya qotih’iy.
Pembagian yang benar tentang pertentangan dalil akal dan dalil naql adalah sebagai berikut”
- Jika keduanya (dalil akal dan dalil naql) sama-sama qoth’iy maka tidak mungkin ada pertentangan dan kontradiksi diantara keduanya
- Jika salah satunya qoth’iy (pasti kebenarannya) dan yang lainnya dhonniy (dipersangkakan kebenarannya) maka jika terjadi pertentangan yang didahulukan adalah dalil yang qoth’iy, apakah dalil qoth’iy tersebut merupakan dalil akal maupun dalil naql
- Jika kedua-duanya sama-sama dzonniy maka yang didahulukan adalah yang lebih roojih diantara keduanya, apakah yang rojih dalil akal ataupun dalil naql
Inilah pembagian yang benar. Akan tetapi yang menjadi problem ternyata Ar-Roozi memandang sebelah mata terhadap dalil naqliy, seakan-akan hanya dalil ‘aqliy (akal) sajalah yang qoth’iy. Dan inilah bid’ah tambahan yang diciptakan oleh Ar-Roozi, dimana ia memandang dalil naqliy sangat sulit dan hampir-hampir mustahil untuk menjadi dalil yang qoth’iy. Ia memandang bahwa dalil lafal (yaitu dalil naqliy dari al-Qur’an maupun al-Hadits) tidak akan memberikan faedah keyakinan kecuali setelah memenuhi persyaratan yang sangat ketat, yang persyaratan tersebut pada hakekatnya hampir-hampir mustahil atau bahkan mustahil untuk dipenuhi.
Ia berkata dalam kitabnya Muhassol al-Afkaar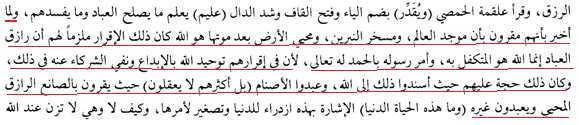
Masalah : Dalil lafal tidaklah memberi faedah keyakinan kecuali jika telah diyakini terpenuhinya 10 perkara, (1) terjaganya para perawi kosa kata lafal-lafal dalil tersebut, (2) I’robnya, juga terjaga tashrifannya (3) tidak adanya isytirook (lafal yang bermakna ganda) (4) tidak ada majaz padanya (5) tidak ada perubahan makna (6) tidak ada pengkhususan untuk individu-individu tertentu atau pengkhususan pada zaman tertentu (7) tidak adanya idlmaar (yaitu adanya lafal yang disembunyikan) (8) tidak adanya takdim dan ta’khiir (mendahulukan atau pengakhiran) dalam lafal-lafal tersebut, (9) serta tidak adanya naskh (10) tidak adanya penentang maknanya secara akal, yang mana kalau ada akal yang menentang maka akal yang did
ahulukan dari pada dalil, karena memenangkan/mendahulukan naql (dalil wahyu) dari pada akal melazimkan pencelaan terhadap akal, yang hal ini melazimkan pencelaan terhadap dalil karena dalil butuh kepada akal. Dan jika muntij/penghasil/pabriknya (yaitu dalil) adalah perkara yang dzonniy (persangkaan dan bukan sesuatu yang diyakinkan-pen) maka bagaimana lagi dengan hasilnya/prodaknya (hukum dari dalil tersebut-pen)” (Muhassol Afkaar al-Mutaakhirn wa al-Mutaqoddimin min al-‘Ulamaa wa al-Hukamaa’ wa al-Mutakallaimin, tahqiq : Tohaa Abdurrouuf Sa’ad, Maktabah al-Kulliyaat al-Aqzhariyahhal 51)
Coba renungkan 10 persyaratan di atas, sebagiannya saja mustahil untuk dipenuhi apalagi harus terpenuhi keseluruhannya !!
Perhatikan syarat yang pertama “Terjaganya/ma’sumnya para perawi kosa kota lafal dalil tersebut”, ini saja mustahil untuk dipenuhi.
Kemudian jika syarat pertama hingga syarat ke sembilan telah terpenuhi, toh keputusannya tetap pada akal sebagaimana yang tertera pada syarat yang kesepuluh. Tentunya akal yang dimaksud Ar-Rozi adalah akalnya dia sendiri !!! yang telah menganggap bahwa banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan aqidah (terutama tentang sifat-sifat Allah) tidaklah masuk di akalnya !!!
KEDUA : Hujjah/alasan yang selalu digembar-gemborkan oleh para pemuja akal adalah perkataan mereka “Akal merupakan asalnya Naql/syari’at, karena dengan akal-lah bisa diketahui kebenaran syari’at/naql”. Pernyataan ini bisa disanggah dari beberapa sisi :
Pertama : Taruhlah kita menerima pernyataan mereka tersebut, maka jika akal telah menunjukkan kebenaran syari’at (dalil naqliy) maka kita harus selalu menjadikan syari’at sebagai patokan kebenaran. Logikanya sebagai berikut :
Jika ada seorang mencari dokter lalu iapun ditunjuki oleh seorang tukang becak siapa dan dimana rumah dokter tersebut. Lalu pergilah orang tersebut berobat ke sang dokter, lalu sang dokter memberi resep obat. Tatkala pulang ia bertemu kembali dengan sang tukang becak, lalu menunjukkan resep dokter tersebut kepada sang tukang becak. Lalu tukang becak tersebut berkata, “Jangan kau percaya resep dokter tersebut, percayalah kepadaku bahwa resepnya itu keliru”. Dalam kondisi seperti ini manakah yang harus dibenarkan olehnya, apakah sang dokter ataukah sang tukang becak yang telah menunjukkan kepadanya tentang sang dokter??
Ilustrasi di atas adalah analogi antara tukang becak yang mewakili dalil akal dan dokter yang mewakili dalil naql/syari’at, yang keberadaan sang dokter telah ditunjukkan oleh sang tukang becak.
Kesimpulan dari ilustrasi di atas:
(1) Sang dokter tetaplah seorang dokter, meskipun tidak ditunjuki oleh sang tukang becak. Jadi kondisinya sebagai dokter tidak tergantung kepada penunjukan sang tukang becak.
Artinya : Syari’at tetap saja benar meskipun tidak diketahui akal seseorang. Nabi Muhammad tetaplah seorang Rasul utusan Allah, sama saja apakah orang-orang mengetahuinya ataukah mereka tidak mengetahuinya. Demikian juga wujud Allah, serta nama-nama dan sifat-sifatnya tetap saja benar, sama saja apakah akal orang-orang mengetahuinya ataukah akal mereka tidak mengetahuinya. Demikian pula apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kebenarannya tidak terpatok pada ilmu kita. Jika kita tidak mengetahui maka berita-berita tersebut tetap merupakan kebenaran. Penjelasan ini sesuai dengan kaidah “عَدَمُ ِالدَّلِيْلِ الْمُعَيَّنِ لاَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمَدْلُوْلِ الْمُعَيَّنِ” (Tidak adanya dalil tertentu tidak menunjukkan tidak adanya yang ditunjukkan oleh dalil tersebut)
(2) Kalau seandainya tukang becak tersebut tidak bisa menunjukkan keberadaan sang dokter maka masih ada tukang-tukang becak yang lain yang bisa menunjukkan keberadaan sang dokter.
Artinya : Jika ternyata akal para penolak sifat (dari kaum Mu’tazilah dan Asyaa’iroh) menganggap penetapan sifat-sifat Allah melazimkan tasybiih dan bertentangan dengan akal mereka, maka masih banyak akal yang tidak menganggap demikian. Bahkan menganggap penetapan sifat-sifat Allah merupakan bentuk kesempurnaan Allah subhaanahu wa ta’aala.
(3) Kalau seandainya para tukang becak tidak ada maka akan ada tukang-tukang yang lainnya yang akan menunjuki keberadaan sang dokter tersebut.
Artinya : Kalau seandainya akal tidak menunjukkan kebenaran syari’at atau bahkan menolak kebenaran syari’at tertentu atau khabar tertentu maka tidak melazimkan bahwa syari’at tersebut atau khabar tersebut juga tidak benar. Mungkin saja masih ada dalil-dalil yang lain (baik dalil fitroh, atau dalil sam’i) yang menunjukkan akan kebenarannya. Hal ini sebagaimana dikatakan “فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِدَلِيْلٍ مُعَيَّنٍ قَدْ يَكُوْنُ مَعْلُوْمًا بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى” Sesuatu yang tidak diketahui dengan penunjuk/dalil tertentu, bisa jadi diketahui dengan penunjuk-penunjuk yang lain”. Atau kalau dengan istilah kita “Banyak jalan menuju Mekah”. Kalau ada satu jalan tidak menyampaikan kita menuju Mekah, maka bukan berarti kota Mekah tidak ada, karena ternyata masih banyak jalan-jalan yang lain yang mengantarkan kepada Mekah. Sebagai contoh, kalau seandainya akal orang-orang Mu’tazilah dan Asyaa’iroh menolak adanya Allah di atas, maka fitroh manusia selalu menunjukkan bahwa Yang Kuasa berada di atas !!. Karenanya tatkala Ar-Roozi mengetahui bahwasanya dalil fitroh yang menunjukkan Allah di atas tidak bisa dipungkiri, maka iapun memaksa agar fitroh seseorang untuk dirubah. Setelah berusaha menolak Allah di atas Ar-Roozi berkata :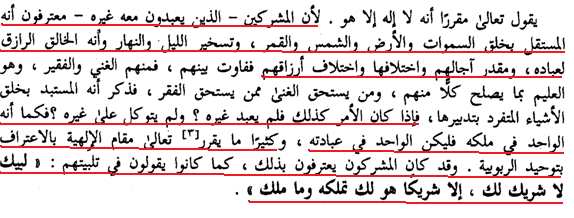
“Dan kami menutup bab ini dengan apa yang diriwayatkan dari Aristoteles bahwasanya ia menulis di awal kitabnya tentang masalah ketuhanan, “Barang siapa yang mulai mendalami ilmu-ilmu ketuhanan maka hendaknya ia memperbaru bagi dirinya fitroh yang lain” (Asaas At-Taqdiis hal 25)
Lihatlah apa yang dilakukan Ar-Roozi, seluruh dalil –yang jumlahnya sangat banyak- tentang Allah di atas ia takwil (simpangkan) seluruhnya, lalu dalil fitroh pun ia tolak, kemudian iapun bersandar dan tunduk kepada perkataan seseorang filosof Yunani yang tidak beragama (Aristoteles) untuk membuang fitroh yang ada dan digantikan dengan fitroh yang baru !!!
(4) Tentunya yang lebih dipercaya adalah perkataan sang dokter bukan perkataan sang tukang becak. Meskipun yang menunjukkan keberadaan si dokter adalah sang tukang becak akan tetapi setelah diketahui sang dokter adalah seorang dokter maka tentunya yang diambil perkataannya dalam masalah pengobatan adalah sang dokter bukan sang tukang becak.
Artinya : Jika akal telah menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus menerima semua pengkhabaran Allah, karena akal menunjukkan bahwa namanya Tuhan tidak mungkin salah. Demikian juga tentang Nabi, akal telah menunjukkan bahwa utusan Tuhan tidak mungkin salah dan keliru. Ini adalah konsekuensi dari menghargai akal dan membenarkannya.
(5) Justru kalau ia mempercayai perkataan sang tukang becak dan membuang resep dokter berarti ia pada hakikatnya telah mendustakan sang tukang becak pertama kali yang menunjukkan sang dokter. Tatkala ia membuang resep dokter berarti ia sebenarnya kurang atau tidak percaya dengan kedokteran sang dokter tersebut. Dan jika ia ragu atau tidak percaya dengan kedokteran sang dokter berarti pada dasarnya ia telah ragu atau tidak percaya dengan penunjukan/perkataan sang tukang becak bahwa sang dokter adalah seorang dokter.
Artinya : Jika kita mendustakan pengkhabaran Allah dan Rasulullah karena tidak sesuai dengan akal kita, maka pada hakikatnya kita sedang menolak akal kita. Karena aka
l telah menunjukkan Allah sebagai Tuhan tidak mungkin keliru, demikian juga Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin keliru. Jika lantas kita mendustakan ayat atau hadits maka menunjukkan kita telah mencela akal sejak awal !!. oleh karenanya penolakan dalil naqli pada hakikatnya adalah penolakan terhadap dalil akal itu sendiri. Karenanya pernyataan para pemuja akal “Menolak akal melazimkan menolak syari’at karena akal adalah asalnya syari’at” sesungguhnya merupakan pernyataan yang terbalik. Justru menolak kebenaran ayat dan hadits melazimkan penolakan terhadap akal !!
Kedua : Terlalu banyak perkara syari’at yang tidak bisa dipikirkan oleh akal, maka hal ini menunjukkan bahwa akal tidak bisa dikatakan sebagai “asal” syari’at.
Sebagai contoh permasalahan hari akhirat, banyak diantaranya yang tidak bisa ditembus oleh akal. Demikian juga permasalahan sifat-sifat Allah tidak mungkin ditembus oleh akal tentang kaifiatnya (bagaimananya), karena pembicaraan tentang sifat-sifat sesuatu dibangun di atas pembicaraan tentang dzat sesuatu tersebut. Karena akal tidak bisa mencerna bagaimana dzat Allah maka demikian pula akal tidak akan mampu mencerna secara rinci tentang bagaimananya (kaifiat) sifat-sifat Allah tersebut.
KETIGA : Jika kita menerima bahwasanya akal lebih didahulukan dari pada naql maka dengan akal siapakah yang kita gunakan untuk menimbang kebenaran al-Qur’an dan as-Sunnah??
Menurut Ar-Roozi akal yang tercanggih adalah akalnya Aristoteles seorang filosof Yunani yang tidak memiliki agama sama sekali. Akal Aristoteles lebih kuat daripada akalnya para sahabat, para tabi’in, para imam madzhab, bahkan akal para nabi ??!!
Dengan akal siapakah kita menimbang kebenaran Al-Qur’an dan as-Sunnah?!! Semoga Allah meridhoi Al-Imam Malik tatkala berkata: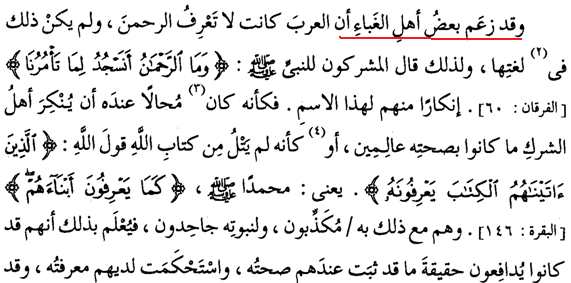
“Apakah setiap datang kepada kita seseorang yang lebih pandai berdebat lantas kita meninggalkan apa yang dibawa turun Jibril kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya karena debatnya??” (Siyar A’laam An-Nubalaa 8/99, lihat juga Hilyatul Auliyaa’ 6/324)
KEEMPAT : Diantara bukti bahwasanya dalil akal tidak bisa didahulukan di atas dalil naqli, ternyata akal para pemuja akal saling kontradiksi. Akal para imam Mu’tazilah –yang menolak seluruh sifat-sifat Allah- ternyata bertentangan dengan akal para imam Asyaa’iroh –yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah-.
Bahkan diantara para imam Asyaa’iroh ada diantara mereka yang akal mereka menetapkan sifat ketinggian Allah, demikian juga sifat kedua tangan Allah dan sifat mata Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abul Hasan al-‘Asy’ari dan juga Al-Baaqillaaniy. Lantas akal siapakah yang diikuti?, apakah akal pendahulu Asyaa’iroh ataukah orang-orang belakangan mereka seperti Ar-Roozi??
Kemudian diantara para imam Asyaa’iroh ada yang berselisih pendapat tentang takwilan-takwilan ayat-ayat dan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah. Ada yang menetapkan takwilan tertentu, sementara yang lain memandang bahwa takwilan tersebut batil??, dan sebagian yang lain memandang tidak perlu ditakwil akan tetapi diserahkan kepada ilmu Allah (tafwidh)??!! (Silahkan lihat penjelasan Ibnu Taimiyyah tentang contoh-contoh kontradiksi mereka di Majmuu al-Fataawaa 2/62, 4/50-53, 16/470, Minhaajus Sunnah An-Nabawiyah 3/288, 347, Dar Ta’aarudl al-‘Aqli wa An-Naqli 1/145-155, 193, 4/278-282, 5/243-245, 6/221-222, 7/41-43, al-Fataawaa al-Mishriyah 6/428)
Diantara contoh kontradiksi mereka adalah permasalahan melihat Allah di akhirat. Menurut akal Mu’tazilah Allah tidak bisa dilihat di akhirat, akan tetapi menurut akal Asyaa’iroh Allah dilihat di akhirat oleh para penduduk surga. Yang jadi permasalahan, kaum Asyaa’iroh menolak ketinggian Allah yang mereka ungkapkan dengan perkataan mereka “اللهُ لَيْسَ فِي جِهَةٍ” (Allah tidak di arah tertentu). Lantas apakah akal mereka (kaum Asyaa’iroh) bisa menerima jika Allah bisa dilihat tapi tanpa ada berhadapan dengan para penglihat???. Menurut akal sehat maka ini merupakan kemustahilan, tidak ada dalam kenyataan seseorang melihat sesuatu tanpa dihadapannya !!!. Karenanya kaum Mu’tazilah –diantaranya Az-Zamakhsariy dalam tafsirnya Al-Kassyaaf- menertawakan kaum Asyaa’iroh yang menyatakan Allah dilihat tapi tidak di arah tertentu !!!
Kota Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam-, 16-12-1433 H / 01 November 2012 M
Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja
www.firanda.com
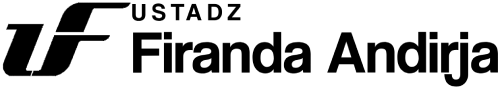








Assalamu’alaikum
Subhanallahu, tulisannya ajib banget ustadz, ini jg ada di majalah Assunnah y. Ijin sharing ustadz Syukron.