Perkataan-perkataan Syaikhul Isl
am Ibnu Taimiyyah Seputar Hajr
Ibnu Taimiyyah berkata, “Hajr yang disyari’atkan ada dua. Pertama, maknanya adalah meninggalkan kemungkaran. Kedua, memberi hukuman kepada pelaku kemungkaran.
Hajr Jenis Pertama: Meninggalkan Kemungkaran.
Allah berfirman:
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
“Dan apabila kalian melihat orang-orang yang memperolok-olokan ayat-ayat Kami maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kalian lupa (akan larangan ini), maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).” (al-An’aam: 68)
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ
“Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur-an bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan maka janganlah kalian duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kalian berbuat demikian) tentulah kalian serupa dengan mereka. (an-Nisaa’: 141)
Maksud dari hajr jenis pertama, agar pelaku hajr tidak menghadiri kemungkaran tanpa ada keperluan. Misalkan saja ada sekelompok orang meminum minuman keras lalu ia duduk bersama mereka. Begitu pula jika ada sekelompok orang yang mengundangnya untuk menghadiri acara walimah, sedangkan di dalam acara tersebut terdapat minuman keras dan suling (alat musik), maka hendaknya ia tidak memenuhi undangan mereka. Berbeda dengan orang yang menghadiri majelis-majelis kemaksiatan dengan tujuan untuk mengingkari perbuatan mereka, atau dia hadir di luar kehendaknya. Karena itulah dikatakan bahwa “orang yang menghadiri suatu kemungkaran seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut.”
Di dalam hadits disebutkan: “Barangsiapa yang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia duduk dekat meja yang digunakan untuk meminum minuman keras.” HR Abu Dawud (III/349) (3774), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
Hajr jenis pertama ini sebagaimana halnya seseorang yang meng-hajr dirinya sendiri dari perbuatan kemungkaran, sebagaimana sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam : “Orang yang berhijrah adalah orang yang meng-hajr (meninggalkan) apa yang dilarang oleh Allah.” HR Abu dawud (III/4) (2481), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Lihat al-Ihsaan (I/467) (230).
Termasuk hajr jenis ini adalah seseorang yang berhijrah dari negeri kekufuran dan kefasikan menuju negeri Islam dan keimanan. Ia meninggalkan hidup di tengah-tengah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak membiarkannya bebas melaksanakan perintah Allah.
Termasuk hajr jenis ini adalah firman Allah:
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
“Dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah.” (al-Muddatstsir: 5).
Hajr Jenis Kedua: Hukuman Kepada Pelaku Kemungkaran
Hajr dalam bentuk memberi pelajaran (hukuman), yaitu hajr kepada orang yang melakukan kemungkaran secara terang-terangan, sehingga dia bertaubat dari perbuatannya. Sebagaimana halnya Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pernah meng-hajr tiga orang sahabat yang tidak ikut jihad yang diwajibkan atas mereka, padahal mereka tidak memiliki udzur. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat tentang taubat mereka. Adapun orang yang menampakkan kebaikan, maka tidak di-hajr, meskipun pada hakekatnya adalah orang munafik.
Hajr jenis kedua ini seperti halnya hukuman ta’zir. Sedangkan ta’zir hanyalah diterapkan kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram, seperti meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, melakukan tindakan kezhaliman, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, dan menyeru kepada bid’ah yang menyelisihi al-Qur-an, Sunnah, serta ijma’ para Salaf yang menjelaskan kebid’ahannya.
Inilah hakikat perkataan sebagian Salaf dan para Imam, “Para penyeru kepada bid’ah tidak diterima persaksian mereka, tidak shalat di belakang mereka (tidak dijadikan imam shalat), tidak mengambil ilmu dari mereka, dan tidak menikahkan (muslimah) dengan mereka.”
Ini merupakan hukuman bagi mereka hingga mereka berhenti. Karena itu, para Imam Salaf membedakan antara ahli bid’ah yang menyeru kepada bid’ahnya dan ahli bid’ah yang tidak menyeru kepada bid’ahnya. Sebab, ahli bid’ah yang menyeru kepada bid’ahnya menampakkan kemungkaran, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang berbeda dengan orang yang menyembunyikan kemungkaran yang dilakukannya, karena ia tidak lebih buruk dibandingkan orang-orang munafik yang Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menerima hukum zhahir yang mereka tampakkan, dan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan hal-hal yang tidak tampak dari mereka kepada Allah, padahal beliau mengetahui kondisi kebanyakan mereka.
Disebutkan dalam sebuah hadits: “Sesungguhnya jika orang-orang melihat adanya kemungkaran kemudian mereka tidak berusaha mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman secara merata kepada mereka.” Hadits ini shahih. Lihat as-Shahiihah (1564).
Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan wajib diingkari, berbeda dengan yang tersembunyi. Sebab, kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi, maka Allah akan menimpakan hukuman kepada pelakunya secara khusus.
Hajr jenis kedua ini bervariasi penerapannya, sesuai dengan kondisi para pelaksananya, tergantung kuat atau lemahnya kekuatan mereka. Demikian juga banyak atau sedikitnya jumlah mereka. Sebab, tujuan dari hajr adalah memberi hukuman dan pelajaran bagi orang yang di-hajr, sekaligus agar orang umum tidak melakukan seperti perbuatan orang yang di-hajr. Jika maslahatnya lebih besar -dimana praktek hajr terhadap pelaku maksiat mengakibatkan berkurangnya keburukan- maka kala itu hajr disyari’atkan. Namun, apabila orang yang di-hajr, demikian juga orang lain tidak berhenti dari kemaksiatannya, bahkan semakin menjadi-jadi, dan pelaku hajr itu sendiri lemah, sehingga mudharat yang timbul lebih besar daripada kemaslahatan, maka hajr tidaklah disyari’atkan, bahkan sikap lemah lembut kepada sebagian orang lebih bermanfaat daripada penerapan hajr untuk kondisi semacam ini.
Terkadang, penerapan hajr kepada sebagian orang lebih bermanfaat dibandingkan bersikap lemah lembut.
Karena itulah Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersikap lembut kepada sebagian orang (yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan) dan meng-hajr sebagian yang lain. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam meng-hajr tiga orang yang tidak ikut jihad dalam perang tabuk, padahal mereka lebih baik daripada kebanyakan mu-allaf yang sedang dibujuk hatinya. Namun, mengingat para mu-allaf tersebut adalah para pemuka di kabilah-kabilah mereka dan ditaati, maka kemaslahatan agama diraih dengan cara bersikap lemah lembut kepada mereka. Adapun tiga orang yang tidak ikut jihad pada perang tabuk, maka mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman selain mereka banyak jumlahnya, sehingga dengan meng-hajr mereka tampaklah kekuatan dan kemuliaan agama, sekaligus untuk membersihkan mereka dari dosa.
Hal ini seperti halnya bersikap terhadap musuh. Terkadang disyari’atkan perang, terka
dang damai dengan mereka, dan terkadang dengan menerima jizyah dari mereka, semua itu tergantung kondisi dan kemaslahatan.
Jawaban Imam Ahmad dan para imam yang lain tentang permasalahan hajr dibangun di atas landasan ini (yaitu membandingkan antara mashlahat dan mudharat, pen). Oleh karena itu, Imam Ahmad membedakan (penerapan hajr) di daerah-daerah yang banyak timbul bid’ah –sebagaimana halnya bid’ah qadariyyah dan tanjim[1] di Khurasan, serta bid’ah tasyayyu’ (syi’ah) di Kufah- dengan daerah-daerah yang tidak banyak timbul bid’ah. Beliau juga membedakan antara para gembong bid’ah yang menjadi panutan dengan selain mereka.
Jika seseorang sudah mengetahui tujuan syari’at, maka seharusnya ia berusaha mencapai tujuan tersebut dengan menempuh jalan yang paling cepat mengantarkannya kepada tujuan tadi.
Jika hal ini jelas, maka ketahuilah bahwa praktek hajr yang disyari’atkan merupakan amalan ketaatan yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang namanya ketaatan itu harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan perintah-Nya. Barangsiapa yang menerapkan hajr karena hawa nafsunya atau mempraktekan hajr yang tidak diperintahkan untuk dilakukan (tidak menimbulkan mashlahat, justru mudharat, pen), maka ia telah keluar dari hajr yang syar’i. Berapa banyak manusia melakukan apa yang diinginkan hawa nafsunya, tetapi mereka mengira bahwa mereka melakukannya karena Allah.” Majmuu’ al-Fataawa (XXVIII/203-210).
Di masa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah terjadi perselisihan di antara Ahlus Sunnah yang tinggal di suatu kampung. Perselisihan itu hampir-hampir menyebabkan mereka saling berperang. Mereka berselisih dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan ‘aqidah, yaitu apakah orang-orang kafir melihat Allah pada hari kiamat? Mereka lalu mengirim utusan kepada Ibnu Taimiyyah untuk bertanya tentang beberapa permasalahan yang mereka hadapi.
Mengingat perselisihan mereka menyangkut permasalahan ‘aqidah, masing-masing tetap mempertahankan pendapat, sehingga hampir terjadi peperangan di antara mereka. Padahal mereka adalah sesama Ahlus Sunnah.
Ibnu Taimiyyah kemudian berkata, “Sebuah utusan telah datang (kepada kami), dari daerah kalian. Mereka mengabarkan kepada kami sebagaimana yang telah kami dengar tentang keadaan orang-orang di kampung kalian yang berpegang teguh dengan Sunnah dan jama’ah, malaksanakan syari’at Allah yang Allah turunkan melalui lisan Rasul-Nya r, menjauhi apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Arab badui di zaman jahiliyyah sebelum datangnya Islam, seperti saling menumpahkan darah, merampas harta sesama, memutuskan tali silaturrahim, keluar dari tali Islam, memberi harta warisan hanya kepada para lelaki, tidak kepada para wanita, meng-isbal pakaian (mengulurkannya hingga melebihi mata kaki), menyeru dengan seruan-seruan orang-orang jahiliyyah, yaitu (seperti) perkataan mereka, ‘Wahai Bani Fulan, atau wahai keluarga Fulan’, ta’ashshub (fanatik) terhadap kesukuan secara batil, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah berkaitan dengan (hukum-hukum) pernikahan, seperti ‘iddah dan yang semisalnya, kemudian hawa nafsu yang telah dihiasi oleh setan sehingga menyebabkan sekelompok dari mereka menyelisihi ‘aqidah orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam), yaitu kaum Muhajirin dan Anshar, mereka menyelisihi apa yang Allah syari’atkan bagi mereka, yaitu untuk beristighfar bagi orang-orang yang terdahulu (masuk Islam), sebagaimana firman-Nya:
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo’a:”Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyanyang”. (al-Hasyr: 10)
Mereka mencela para sahabat Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam dengan celaan yang tidak akan timbul dari seseorang yang imannya telah menghujam dalam hati.
Maka segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan kalian dari apa yang menimpa banyak orang, sekaligus memuliakan kita di atas banyak ciptaan Allah. Kami mohon kepada Allah yang Maha Agung, Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi, agar menyempurnakan nikmat yang Ia berikan kepada kami dan kalian, memberi taufik kepada kami dan kalian untuk melakukan perkara-perkara yang Ia cintai dan ridhai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dengan baik.” Majmuu’ Fataawa (XXIV/164).
Setelah Ibnu Taimiyyah mengingatkan mereka tentang kenikmatan yang mereka rasakan, berupa ‘aqidah dan manhaj yang benar, maka beliau mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, hingga beliau berkata -dalam rangka mengingatkan mereka tentang perintah Allah untuk bersatu dan melarang adanya perpecahan-:
“Ketahuilah –semoga Allah merahmati kalian, serta mengumpulkan kami dan kalian pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat-, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan al-Qur-an kepadanya. Allah mengutus beliau kepada kaum yang mengikuti hawa nafsu yang saling terpecah pecah, dan hati mereka tercerai-berai, dan pemikiran yang bermacam-macam, maka dengan perantaraan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam Allah menyatukan mereka, menyambung hati-hati mereka, dan menjaga mereka dari tipuan setan.
Setelah itu Allah jelaskan pokok yang penting ini, bahwa jama’ah (persatuan) merupakan tiang agama-Nya, maka Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar
-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan):”Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya.” (Ali ‘Imran: 102-107).
Ibnu Abbas berkata:
تَبْيَضُّ وُجُوْهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ
“Orang-orang yang wajahnya berseri-seri adalah Ahlus Sunnah dan orang-orang yang wajahnya hitam adalah ahli bid’ah.”
Lihatlah –semoga Allah merahmati kalian-, Allah telah menyeru kepada persatuan dan melarang dari perpecahan. Allah berfirman dalam ayat lain:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ
Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. (al-An’aam: 159)
Allah menyatakan bahwa Nabi-Nya berlepas diri dari orang-orang yang memecah agama mereka dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, sebagaimana Allah juga telah melarang kita dari perpecahan dan perselisihan dalam firman-Nya:
وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, (Ali ‘Imran: 105)
Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam sendiri membenci perdebatan yang mengantarkan kepada perselisihan dan perpecahan. Pada suatu ketika ia mendapati sebagian sahabatnya berdebat tentang masalah takdir, maka seolah-olah ada buah delima yang pecah di wajahnya (terdapat rona merah yang menunjukkan rasa marah pada wajah beliau, pen). Beliau lalu berkata:
أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ إِلَى هَذَا دُعِيْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
“Apakah kalian diperintahkan untuk berbuat seperti ini? Ataukah kalian diseru untuk melakukan ini? Kalian mempertentangkan ayat-ayat al-Qur-an antara yang satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa hanyalah karena hal seperti ini. Mereka saling mempertentangkan ayat-ayat Kitab Allah antara satu dengan yang lainnya.”[2]
Selanjutnya Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa para sahabat juga pernah berselisih, bahkan dalam permasalahan ‘aqidah, namun mereka tetap bersatu. Beliau berkata: “Dahulu para ulama dari kalangan para sahabat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, Tabi’in, dan generasi setelah mereka, jika berselisih tentang suatu perkara, mereka mengikuti perintah Allah sebagaimana dalam firman-Nya:
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisaa’: 59)
Mereka berdialog tentang permasalahan tersebut, dalam rangka musyawarah dan saling menasehati. Terkadang mereka berselisih dalam permasalahan ‘ilmiyyah (‘aqidah) ataupun ‘amaliyyah (fiqh), namun mereka tetap bersatu, bersahabat, dan bersaudara.
Memang benar, bahwa barangsiapa yang menyelisihi: (1) al-Qur-an yang jelas, (2) sunnah yang mustafidhah (masyhur), atau (3) ijma’ Salaf dengan penyelisihan yang tidak ada udzurnya, maka ia disikapi sebagaimana ahli bid’ah.
‘Aisyah, Ummul Mukminin, telah menyelisihi Ibnu ‘Abbas dan para sahabat lainnya dalam masalah Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam melihat Allah (yaitu pada malam isra’ mi’raj, pen). Ia berkata, “Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad ` melihat Rabbnya maka ia telah berdusta besar atas nama Allah.”
Padahal mayoritas umat sependapat dengan Ibnu ‘Abbas. Meskipun demikian, mereka tidak menyatakan bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Muhammad ` tidak melihat Rabbnya dan sejalan dengan Aisyah sebagai ahli bid’ah.
‘Aisyah juga mengingkari bahwa mayat-mayat bisa mendengar do’a orang yang masih hidup. Tatkala dikatakan kepada ‘Aisyah bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ
“Tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan dari pada mereka (orang-orang kafir yang mati di perang Badar).”
Maka ‘Aisyah menjawab, “Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam hanya berkata, ‘Sesungguhnya mereka (orang-orang kafir yang mati di perang Badar) sekarang sungguh mengetahui bahwa apa yang aku sampaikan kepada mereka adalah kebenaran….'” Majmuu’ Fataawa (XXIV/173).
Diriwayatkan juga dari Mu’awiyah bahwa beliau berkata tentang mi’raj (naiknya Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam ke langit), “Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam naik ke langit hanya dengan ruhnya (tidak dengan jasadnya),” maka orang-orang pun menyelisihi beliau.
Perbedaan pendapat yang seperti ini banyak jumlahnya.[3]
Adapun perselisihan mereka dalam masalah-msalah hukum (fiqh), maka sangat banyak.
Sekiranya untuk setiap permasalahan yang diperselisihkan oleh dua muslim lalu keduanya saling hajr, maka tidak akan tersisa bagi kaum muslimin persatuan dan persaudaraan.
Abu Bakr dan ‘Umar –yang keduanya adalah pemimpin kaum muslimin- pernah berselisih dalam beberapa masalah, namun mereka tidak menghendaki kecuali kebaikan.
Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata kepada para sahabatnya pada peristiwa Bani Quraizhah, “Janganlah salah seorang dari kalian shalat ‘Ashar kecuali di tempatnya Bani Quraizhah.” Ketika masuk waktu ashar, mereka masih berada di tengah perjalanan. S
ebagian mereka lalu berkata, “Kami tidak akan shalat kecuali di tempat Bani Quraizhah.” Akhirnya mereka shalat ashar di luar waktunya. Sebagian lain berkata, “Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tidak bermaksud agar kita mengakhirkan shalat ashar.” Mereka pun shalat ashar di tengah perjalanan. Dan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam sama sekali tidak mencela seorang pun dari kedua kelompok tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari hadits Ibnu ‘Umar.
Perselisihan ini, meskipun terjadi dalam permasalahan hukum (fiqh), namun seluruh perkara yang bukan termasuk perkara ushul (pokok) yang urgen, maka juga diikutkan (disamakan) dengan permasalahan-permasalahan hukum. Majmuu’ Fataawa (XXIV/172-176).
Setelah menjelaskan pentingnya persatuan, Ibnu Taimiyyah melanjutkan pembicaraannya dengan menjelaskan keutamaan mendamaikan kaum muslimin yang saling berselisih. Beliau berkata, “Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ
“Maukah kukabarkan kepada kalian suatu perkara yang lebih mulia daripada derajat puasa, shalat, sedekah, dan amar ma’ruf nahi mungkar? Para Sahabat menjawab, “Tentu ya Rasulullah.” Beliau shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Mendamaikan hubungan antara orang-orang yang bertikai, karena sesungguhnya rusaknya hubungan adalah pencukur, aku tidak mengatakan pencukur rambut, tetapi pencukur agama.”
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud,[4] dari az-Zubair bin al-‘Awwam.
Dalam hadits yang shahih, beliau juga bersabda:
لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ
“Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling, begitu juga yang lainnya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam.” HR Al-Bukhari (V/2302) (5879) dan Muslim (IV/1984) (2560).
Memang benar bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pernah meng-hajr Ka’ab bin Malik dan kedua sahabatnya y, ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Kemaksiatan mereka tampak dan dikhawatirkan mereka terkena sifat kemunafikan, maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pun meng-hajr mereka dan memerintahkan kaum muslimin untuk meng-hajr mereka. Bahkan memerintahkan ketiganya untuk menjauhi istri-istri mereka tanpa cerai.[5] Mereka di-hajr selama lima puluh hari, sehingga turun ayat dari langit yang menjelaskan bahwa Allah menerima taubat mereka.
Begitu juga ‘Umar, ia memerintahkan kaum muslimin untuk meng-hajr Shabigh bin ‘Asl at-Tamimi selama setahun, karena ‘Umar memandang bahwa ia termasuk orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat (samar). Setelah jelas kesungguhan taubatnya, ‘Umar pun memerintahkan kaum muslimin untuk menghentikan hajr mereka.
Dengan kisah-kisah ini dan yang semisalnya, maka kaum muslimin berpendapat adanya praktek hajr terhadap orang-orang yang nampak padanya tanda-tanda penyelewengan (kesesatan) dari kalangan orang-orang yang menampakkan dan menyerukan bid’ah, dan orang-orang yang menampakkan dosa-dosa besar.
Adapun orang yang menyembunyikan kemaksiatannya, atau melakukan bid’ah yang tidak sampai derajat kekufuran secara sembunyi-sembunyi, maka orang-orang seperti ini tidaklah di-hajr. Yang di-hajr adalah orang-orang yang menyeru kepada bid’ah. Karena hajr adalah salah satu bentuk hukuman, sementara orang yang dihukum adalah orang yang menampakan kemaksiatan baik secara perkataan maupun perbuataan.
Adapun orang yang menampakkan kebaikan kepada kita, maka kita terima apa yang tampak darinya, dan kita serahkan hakikat batinnya kepada Allah, karena sejelek-jeleknya ia adalah berada pada posisi orang-orang munafik yang Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menerima zhahir mereka dan menyerahkan batin mereka kepada Allah, tatkala orang-orang munafik tersebut datang kepada Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam sewaktu perang Tabuk sambil bersumpah dan mengajukan alasan mereka. Karena itu, Imam Ahmad dan mayoritas ulama sebelum maupun sesudah beliau, seperti Imam Malik dan selainnya, tidak menerima riwayat orang yang menyeru kepada bid’ah dan tidak bermajelis dengannya, berbeda dengan orang yang diam.
Para penulis buku-buku hadits yang hanya memuat hadits shahih pun telah meriwayatkan hadits melalui jalur sejumlah orang yang tertuduh dengan kebid’ahan yang diam (tidak menyeru kepada bid’ah), dan mereka tidak meriwayatkan hadits dari jalan para perawi yang menyeru kepada bid’ah.
Yang menyebabkan aku mengutarakan pembicaraan ini, karena utusan kalian mengabarkan beberapa perkara kepada kami, berupa perpecahan dan perselsisihan di antara kalian. Utusan kalian menyebutkan bahwa perkaranya terus berkembang sampai-sampai hampir terjadi peperangan. La Haula wa la Quwwata illa billah. Kepada Allah-lah tempat meminta untuk menyatukan hati-hati kami dan hati-hati kalian, mendamaikan orang-orang yang berselisih di antara kita, memberi petunjuk kepada kita kepada jalan keselamatan, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, memberikan berkah pada pendengaran kita, penglihatan kita, istri-istri kita, anak keturunan kita selama Ia masih menghidupkan kita, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan-Nya, memuji-Nya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, menerima kenikmatan-kenikmatan tadi, serta Ia sempurnakan nikmat-nikmat-Nya kepada kita.
Utusan kalian menyebutkan bahwa sebab perselisihan yang timbul di antara kalian adalah karena permasalahan apakah orang-orang kafir melihat Rabb mereka. Kami tidak pernah menyangka kalau karena permasalahan ini perkaranya sampai memuncak seperti ini, (karena sebenarnya) permasalahan ini adalah permasalahan yang ringan.” Majmuu’ Fataawa (XXIV/172-176). Barang siapa yang ingin mengetahui pembahasan masalah ini secara tuntas maka bacalah Majmuu’ Fataawa (VI/485-506)
Beliau juga berkata, “Pasal: Tentang Pertanyaan-Pertanyaan Ishaq bin Manshur (kepada Imam Ahmad). Al-Khallal menyebutkan pertanyaan tersebut dalam as-Sunnah, bab Mujaanabah Man Qaala al-Qur-an Makhluuq (menjauhi orang yang menyatakan bahwa al-Qur-an adalah makhluk).
Dari Ishaq, ia bertanya kepada Abu ‘Abdillah (Imam Ahmad), “Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa al-Qur-an itu makhluk?”
Imam Ahmad menjawab, “Berikanlah kepadanya seluruh bala!”
Aku (Ishaq bin Manshur) bertanya lagi, “Apakah ia (seorang Ahlus Sunnah) menampakkan permusuhan kepada mereka (orang-orang yang mengatakan bahwa al-Qur-an itu makhluk, pen) ataukah ia berbuat mudarah?”[6]
Beliau menjawab, “Penduduk (Ahlus Sunnah yang berada di) negeri Khurasan tidak kuat untuk berhadapan dengan mereka (Jahmiyyah).”
Jawaban ini, juga merupakan perkataan Imam Ahmad tentang Qadariyyah (sekte yang menolak adanya taqdir). Beliau berkata, “Sekiranya kita meninggalkan riwayat dari orang-orang Qadariyyah, maka kita akan meninggalkan riwayat dari mayoritas penduduk Bashrah.”
Demikian pula dengan sikap beliau tatkala bermu’amalah dengan mereka ketika beliau disiksa (disebabka
n fitnah al-Qur-an itu makhluq, pen), dimana beliau menjawab mereka dengan cara yang baik dan berbicara dengan mereka dengan hujjah. Ini menafsirkan apa yang terdapat dalam perkataan beliau dan sikap beliau tentang praktek hajr terhadap ahli bid’ah, larangan beliau untuk bermajelis dengan mereka, atau untuk berbicara dengan mereka. Namun beliau pernah pada suatu waktu meng-hajr beberapa orang yang termasuk para pembesar dan beliau juga memerintahkan (kaum muslimin) untuk meng-hajr mereka dikarenakan mereka memiliki sedikit bid’ah jahmiyyah….” Majmu’ Fatawa (XXVIII/210)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berkata, “Untuk memberi hukuman kepada orang yang zhalim dan men-ta’zir-nya disyaratkan adanya kemampuan. Karena itu, hukum syari’at bervariasi pada dua jenis hajr (di atas), antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, antara sedikit banyaknya pelaku kezhaliman yang mubtadi’, begitu juga kuat lemahnya mubtadi’ tersebut, sebagaimana halnya hukum syaria’t itu bervariasi pada seluruh jenis kezhaliman berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dimana setiap yang Allah haramkan merupakan kezhaliman….” Majmu’ Fatawa (XXVIII/211)
Beliau juga berkata, “Jika dalam penerapan hajr terhadapnya (pelaku kezhaliman atau mubtadi’) tidak menjadikan seorang pun takut dan berhenti, bahkan yang terjadi adalah tersia-siakannya banyak kebaikan yang diperintahkan untuk dilaksanakan, maka hajr tersebut tidak diperintahkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang Ahlus Sunnah yang tinggal di negeri Khurasan pada waktu itu, dimana mereka tidak mampu berhadapan dengan Jahmiyyah. Jika mereka tidak mampu untuk menampakkan permusuhan terhadap Jahmiyah maka gugurlah perintah untuk melakukan kebaikan ini (yaitu meng-hajr mereka), dan sikap mudarah kepada Jahmiyyah membuahkan tertolaknya mudharat dari seorang mukmin yang lemah, dan mungkin saja sikap mudarah ini menarik hati orang fajir yang kuat.
Demikian pula tatkala bid’ah Qadariyyah banyak menimpa penduduk kota Bashrah, apabila pengambilan riwayat hadits dari orang-orang Qadariyyah ditinggalkan, niscaya ilmu, hadits, dan atsar yang ada pada mereka akan punah.
Jika kewajiban-kewajiban berupa ilmu, jihad, dan selainnya tidak bisa ditegakkan kecuali dengan orang yang memiliki bid’ah yang mudharatnya lebih ringan dibandingkan jika kewajiban tersebut ditinggalkan, maka mencapai kemaslahatan dengan melaksanakan kewajiban, meskipun ada mudharat yang sedikit itu lebih baik dibandingkan tidak melaksanakannya. Karena itu, pembicaraan dalam masalah-masalah ini ada rinciannya.
Banyak dari jawaban Imam Ahmad dan para Imam lainnya keluar sesuai dengan soal yang diajukan oleh penanya, dimana para Imam tersebut telah mengetahui kondisi orang yang sedang ditanyakan, atau (jawaban tersebut) keluar secara khusus untuk (menyikapi) orang tertentu, dimana Imam yang memberi jawaban telah mengetahui kondisi yang sedang ditanyakan. Maka yang seperti ini kedudukannya seperti qadhaayal a’yaan (kasus kasus khusus tertentu) yang datang dari Rasululah r. Hukumnya hanyalah bisa ditetapkan kepada yang semisal kasus-kasus tersebut.
Sebagian orang menjadikan jawaban (para Imam tersebut) sebagai sesuatu yang umum. Mereka akhirnya menggunakan hajr dan pengingkaran yang tidak diperintahkan, padahal praktek hajr tersebut tidak wajib dan tidak pula disunnahkan. Bahkan bisa jadi mereka (karena menerapkan hajr bukan pada tempatnya) akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban atau perkara-perkara yang mustahab, dan dengan penerapan hajr tersebut mereka justru melakukan perkara-perkara yang diharamkan.
Golongan yang lain, mereka berpaling secara total dari jawaban para Imam tersebut, sehingga mereka tidak meng-hajr perkara-perkara yang diperintahkan (disyari’atkan) untuk di-hajr, berupa kejelekan yang berbentuk bid’ah.[7] Bahkan mereka meninggalkan bid’ah-bid’ah tersebut begitu saja -seperti orang yang tidak peduli-, bukan seperti orang yang meninggalkan bid’ah tersebut karena berhenti dan benci kepadanya. Atau bahkan mereka terjatuh dalam bid’ah tersebut. Dan terkadang mereka meninggalkan bid’ah karena berhenti dan benci kepadanya, namun mereka tidak melarang orang lain darinya.
Mereka tidak memberi hukuman dengan hajr dan semisalnya kepada orang-orang yang berhak untuk diberi hukuman, sehingga mereka menyia-nyiakan nahi munkar yang mereka diperintahkan untuk melakukannya, baik berupa perintah wajib maupun mustahab. Kondisi mereka berada di antara melakukan kemungkaran atau meninggalkan sikap mencegah kemungkaran tersebut. Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Ini sama dengan itu. Dan agama Allah adalah tengah di antara sikap yang berlebih-lebihan dan sebaliknya. Wallaahu a’lam.” Majmuu’ Fataawa (XXVIII/210-213).
Abu ‘Abdilmuhsin Firanda Andirja
Artikel: www.firanda.com
[1] Demikianlah yang tercantum dalam buku yang dicetak. Namun mungkin yang dimaksud adalah bid’ah tajahhum (bid’ahnya sekte Jahmiyyah). Wallaahu a’lam.
[2] Majmuu’ Fataawa (XXIV/170-172).
[3] Maksudnya perbedaan pendapat dalam masalah ‘aqidah yang bukan inti.
[4] HR Abu Dawud (4919), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
[5] Ketiganya menjauhi istri-istri mereka selama 10 hari
[6] Sebagian orang menyangka bahwa bersikap lembut terhadap pelaku kemaksiatan atau ahli bid’ah adalah bentuk mudahanah (bermuka dua) yang tercela, padahal perkaranya tidak mutlak demikian. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pernah ber-mudarah, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (V/2271) (5780), bab al-Mudaarah ma’an Naas, dan Muslim (IV/2002) (2591).
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ r رَجُلٌ فَقَالَ ((ائْذَنُوْا لَهُ فَبِئْسَ بْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ)) فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ
Dari ‘Urwah bin az-Zubair, ‘Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang pria minta izin untuk menemui Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam , maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Izinkanlah ia, sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek anak di kaum (kabilah)nya,” atau beliau shallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Ia adalah sejelek-jelek orang di kaum (kabilah)nya.” Kemudian tatkala orang itu masuk (menemui Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam ), maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pun berbicara kepadanya dengan lemah lembut. Aku (‘Aisyah) pun berkata kepada beliau r, “Ya Rasulullah, engkau telah mengatakan apa yang tadi kau katakan, kemudian engkau berbicara dengannya dengan lemah lembut?”. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan atau dijauhi masyarakat untuk menghindari kejelekannya.”
Perbedaan antara mudahanah dan mudarah diantaranya:
1.Imam al-Qurthubi berkata, “Mudarah adalah mengorbankan dunia untuk kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia, agama, atau keduanya. H
al ini hukumnya adalah mubah dan bisa jadi mustahab. Adapun mudahanah adalah mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam (dalam hadits di atas, pen) hanyalah mengorbankan perkara dunianya, yaitu menggauli orang tersebut dengan baik dan lemah lembut tatkala berbicara dengannya. Meskipun demikian beliau r tidak memuji pria tersebut dengan satu perkataan pun. Maka sikap beliau r (yang lemah lembut) tidaklah membatalkan celaan beliau terhadap orang itu”. Fat-hul Bari (X/454)
2.Ibnu Baththal berkata, “Mudarah merupakan akhlak orang-orang mukmin, yaitu bersikap rendah diri di hadapan manusia, berbicara dengan lemah lembut, dan meninggalkan sikap keras terhadap manusia. Ini termasuk sebab terkuat untuk mencapai persatuan.” Fat-hul Bari (X/528)
3.Beliau juga berkata, “Kata mudahanah diambil dari minyak (cat), yaitu menampakkan sesuatu dan menyembunyikan batinnya. Para ulama menafsirkan mudahanah yaitu bergaul dengan orang fasik dengan menampakkan keridhaan terhadap apa yang ada pada orang fasik tersebut tanpa adanya pengingkaran. Adapun mudarah adalah sikap lembut terhadap orang jahil (bodoh) dalam mengajarinya, dan sikap lembut terhadap orang fasik dalam rangka mencegahnya dari perbuatan (kemungkarannya) serta tidak bersikap keras kepadanya, dengan tidak menampakkan keridhaan terhadap apa yang ada pada orang fasik tersebut dan tetap mengingkarinya, dengan perkataan dan perbuatan yang lembut. Terlebih lagi jika dibutuhkan untuk menarik hatinya dan yang semisalnya.” Fat-hul Bari (X/529)
Syaikh Al-Albani berkata, “Para pensyarah hadits ini menyatakan bahwa orang yang datang meminta idzin kepada Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits ini adalah seorang munafik dan dia pemimpin sebuah kabilah. Dan banyak kaum mukminin yang lemah yang berada di bawah kekuasaannya. Kalau seandainya Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menolaknya dan tidak bersikap lemah lembut terhadapnya maka bisa jadi ia akan bersikap keras terhadap kaum mukminin yang lemah yang berada di bawah kekuasaannya. Maka sikap lembut Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terhadapnya merupakan siasat yang dilakukan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dan merupakan sikap mudaaroot dan bukan sikap mudahanah karena Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah mengucapakan sebuah kalimat yang menyelisihi syari’at. (Silsilah Al-Huda wan Nuur no 313)
Berkata Al-Munawi, “Sikap mudaaroot ini…sebagaimana perkataan Ali إِنَّا لَنَبُشُّ فِي وُجُوْهِ أَقْوَامٍ وَقُلُوْبُنَا تَلْعَنُهُمْ ((Sungguh kita tersenyum di hadapan wajah orang-orang padahal hati kami melaknat mereka)) (Faidul Qodiir III/568)
[7] Seperti yang banyak terjadi di kalangan sejumlah jama’ah yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah dewasa ini.
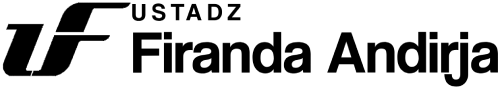








syukron akhi.
Assalamu’laikum ya Syaikhuna
Alhamdulillah wa bi idznillah, lebih terbuka pikiran ini setelah membaca artikel yang sangat bermanfaat ini.
Jazakallahu khoiran