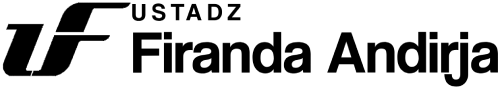Ibnu Taimiyyah berkata :“Tidak boleh bagi seorang pun memaksa manusia untuk mengikuti pendapatnya dalam masalah ijtihadiyyah. Namun hendaknya ia berbicara dengan hujjah ilmiah. Barangsiapa jelas baginya kebenaran salah satu dari dua pendapat maka ia mengikutinya. Dan barangsiapa yang taqlid kepada pendapat yang lain maka tidak boleh diingkari. Dan permasalahan-permasalahan yang seperti ini banyak….” (Majmuu’ Fataawa (XXX/79-80)
Hajr hanya boleh diterapkan pada seseorang yang menyelisihi ayat-ayat al-Qur-an yang jelas, atau hadits-hadits yang masyhur, atau ijma’ para Salaf. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyyah: “Memang benar, barangsiapa yang menyelisihi: (1) al-Qur-an yang jelas dan (2) Sunnah yang mustafidhah (masyhur), atau (3) ijma’ Salaf, dengan suatu penyesilihan yang tidak ada udzurnya, maka orang seperti ini disikapi sebagaimana menyikapi ahli bid’ah.” (Majmuu’ Fataawa (XXIV/172).
Adapun masalah ijtihadiyyah yang masih debatable di kalangan para ulama, maka tidak boleh disikapi dengan tahdzir, apalagi hajr.
Al-Qadhi ‘Iyadh berkata, “Tidaklah layak bagi seorang penegak amar ma’ruf nahi munkar untuk membawa manusia berjalan di atas ijtihad-nya dan madzhabnya, ia hanya boleh merubah kemungkaran yang disepakati untuk diingkari.”
Imam an-Nawawi mengadopsi pernyataan al-Qadhi ‘Iyadh tersebut, dan beliau berkata, “Adapun perkara-perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran, dan tidak boleh bagi seorang mufti untuk mengkritik orang yang menyelisihinya apabila ia tidak menyelisihi nash atau ijma’.” (Sebagaimana perkataan Imam Nawawi ini dinukil dalam At-Taaj wal Ikliil (IV/381), dan silahkan rujuk kepada perkataan beliau dalam Al-Minhaaj Syarh shahih Muslim 2/23-24)
Imam an-Nawawi juga berkata, “Hanyalah yang melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar adalah orang yang mengetahui perkara yang ia perintahkan dan perkara yang ia larang. Hal ini bervariasi sesuai dengan ma’ruf yang ia perintahkan dan kemungkaran yang ia larang. Jika (ma’ruf tersebut) termasuk perkara-perkara wajib yang nyata, dan (munkar tersebut) termasuk perkara-perkara diharamkan yang masyhur, seperti shalat, puasa, zina, khamr, dan semisalnya, maka setiap orang mengetahuinya. Namun jika perkaranya termasuk ucapan dan perbuatan yang rumit dan berkaitan dengan ijtihad, maka kaum muslimin yang awam tidak berhak masuk ke dalam area ini, dan mereka tidak boleh mengingkarinya. Hal ini khusus merupakan hak para ulama.
Selanjutnya, para ulama hanyalah (boleh) mengingkari perkara-perkara yang merupakan ijma’. Adapun perkara-perkara yang masih debatable, maka tidak ada pengingkaran. Sebab menurut salah satu dari dua pendapat, setiap mujtahid benar, dan pendapat inilah yang dipilih oleh banyak atau mayoritas ahli tahqiq. Sedangkan menurut pendapat kedua, yang benar hanyalah satu dan mujtahid yang salah masih tidak jelas bagi kita, dan ia tidak terkena dosa kesalahan tersebut. Namun jika ia menyeru dalam bentuk nasehat untuk keluar dari khilaf (perselisihan), maka hal ini baik, disukai dan dianjurkan untuk dilakukan, dengan cara yang lembut. Sebab ulama sepakat dalam anjuran untuk keluar dari perselisihan, jika tidak melazimkan adanya khalal dalam Sunnah, atau terjatuh dalam perselisihan yang lain.” (Al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim (II/23).
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang mengurus suatu urusan kaum muslimin, sedangkan madzhab orang yang bersangkutan adalah tidak bolehnya serikat badan, maka apakah boleh baginya untuk melarang orang lain (dari melakukan serikat badan)?
Beliau menjawab, “Dia tidak boleh melarang orang lain dari melakukan hal tersebut dan semisalnya, yang termasuk perkara-perkara yang diperbolehkan ijtihad di dalamnya, sementara ia sendiri tidak memiliki nash (dalil yang gamblang) dari al-Qur’an, Sunnah, atau ijma’, atau yang semakna dengan ijma’ tersebut. Terlebih lagi jika mayoritas ulama memandang bolehnya perkara tersebut, dan hal ini dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di mayoritas negeri.
Hal ini adalah sebagaimana seorang hakim tidak berhak membatalkan hukum hakim selainnya dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Demikian juga seorang mufti atau ulama, ia tidak boleh mewajibkan manusia mengikuti pendapatnya dalam masalah-masalah seperti ini. Karena itulah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid meminta opini Imam Malik untuk menjadikan manusia mengikuti al-Muwaththa’, karya beliau, dalam masalah-masalah seperti ini, Imam Malik pun melarang sang Khalifah. Imam Malik berkata, ‘Sesungguhnya para sahabat Rasulullah ` tersebar di berbagai negeri, dan setiap kaum mengambil ilmu sesuai dengan apa yang sampai kepada mereka.’
Seseorang telah mengarang sebuah kitab tentang ikhtilaf, maka Imam Ahmad berkata, ‘Janganlah engkau beri judul kitab tersebut ‘Kitab Ikhtilaf’ tetapi namailah kitab itu ‘Kitab as-Sunnah’.” (Kitab As-Sunnah”, demikianlah yang penulis dapatkan dalam buku cetakan Majmuu’ Fataawa (XXX/79-80), namun di jilid XIV/159 disebutkan “Kitab As-Sa’ah”, dimana Ibnu Taimiyyah berkata,
((Dan perselisihan dalam permasalahan hukum terkadang merupakan rahmat jika tidak mengantarkan pada keburukan yang besar karena samarnya hukum (yang benar). Oleh karena itu seseorang mengarang sebuah kitab yang ia beri judul “Kitab Al-Ikhtilaf” maka Imam Ahmad berkata, “Berilah judul Kitab As-Sa’ah (kelapangan dan keluasan)”, padahal kebenaran pada hakikatnya hanya satu. Dan terkadang merupakan rahmat Allah kepada sebagian orang adalah samarnya kebenaran tersebut dikarenakan jika nampak kebenaran tersebut mengakibatkan kesulitan bagi mereka, dan jadilah hal ini termasuk dalam bab firman Allah
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة : 101 )
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu (QS. Al Maidah 101)
Dan demikianlah sebagaimana makanan dan pakaian yang terdapat di pasar-pasar, bisa jadi pada hakikatnya merupakan barang-barang rampasan (curian), namun jika seseorang tidak mengetahui hal itu (lalu membelinya-pen) maka hukumnya halal baginya serta tidak berdosa. Hal ini berbeda jika dia telah mengetahui (bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang curia-pen). Maka tersamarkannya suatu ilmu yang bisa menyebabkan kesulitan terkadang merupakan rahmat…))
Dan penulis tidak tahu manakah yang benar dari keduanya (yang hal ini butuh muroja’ah lebih lanjut).
Jika yang benar adalah Kitab As-Sunnah maka hal ini dikarenakan perbedaan pendapat yang termaktub dalam kitab tersebut adalah perselisihan ijtihadiyyah yang dibangun di atas dalil, baik dari al-Qur`an maupun Sunnah, maka Imam Ahmad menganjurkan untuk memberi nama kitab tersebut dengan kitab as-Sunnah. Adapun khilaf yang tidak dibangun di atas dalil maka bukanlah merupakan khilaf yang hakiki. Sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim dalam I’laamul Muwaqqi’in (III/288). Wallaahu a’lam.).
Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa ijma’ (konsensus) para ulama merupakan hujjah yang sangat jelas (pasti kebenarannya) dan kuat, sedangkan perselisihan mereka merupakan rahmat yang luas. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata, ‘Tidak menyenangkanku apabila para sahabat tidak berselisih pendapat. Sebab jika mereka bersepakat pada satu pendapat lalu ada seseorang menyelisihi pendapat mereka maka sesatlah orang tersebut. Namun jika mereka berselisih lalu seseorang mengambil perkataan sahabat yang ini dan yang lainnya mengambil pendapat yang itu, maka perkaranya jadi lapang.’ (Jangan dipahami dari perkataan Ibnu Taimiyah dan ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz ini bahwa mereka menganjurkan berselisih pendapat. Mereka berbicara dari sudut pandang y
ang lain, yaitu menyatakan orang yang menyelisihi suatu pendapat sebagai orang yang sesat. Jika tidak ada khilaf, maka seseorang menjadi sangat mudah untuk mengatakan orang lain yang menyelisihinya sebagai orang yang sesat ahli bid’ah. Hal ini sesuai kaidah yang dijelaskan Ibnu Taimiyah bahwa seseorang tidak disikapi dengan mu’amalah ahli bid’ah kecuali jika ia menyelisihi salah satu dari tiga perkara, di antaranya adalah ijma’.) Demikian juga para Imam selain imam Malik, mereka berkata, ‘Tidak boleh bagi seorang faqih untuk membawa manusia di atas madzhabnya.’
Oleh karena itu, para ulama yang menulis tentang masalah amar ma’ruf nahi mungkar dari madzhab Syafi’i dan madzhab selainnya mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan ijtihadiyyah tidak boleh diingkari dengan tangan. Tidak boleh bagi seorang pun memaksa manusia untuk mengikuti pendapatnya dalam masalah ijtihadiyyah. Namun hendaknya ia berbicara dengan hujjah ilmiah. Barangsiapa jelas baginya kebenaran salah satu dari dua pendapat maka ia mengikutinya. Dan barangsiapa yang taqlid kepada pendapat yang lain maka tidak boleh diingkari. Dan permasalahan-permasalahan yang seperti ini banyak….” (Majmuu’ Fataawa (XXX/79-80)
Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “Kemungkaran yang wajib diingkari adalah perkara-perkara yang merupakan ijma’ (bahwa ia adalah kemungkaran, pen). Adapun perkara yang masih diperselisihkan, maka sebagian sahabat kami ada yang berkata, ‘Tidak wajib mengingkari perkara yang masih diperselisihkan yang dilakukan oleh seseorang karena ijtihad atau karena taqlid kepada seorang mujtahid dengan taklid yang dibolehkan. Al-Qadhi dalam bukunya al-Ahkaam as-Sulthaniyyah mengecualikan perkara-perkara yang khilaf-nya lemah, jika perkara-perkara tersebut mengantarkan kepada perkara yang telah disepakati keharamannya, seperti riba pada uang. Khilaf dalam permasalahan ini lemah, sedangkan hal ini mengantarkan kepada riba nasi’ah yang disepakati keharamannya. Juga seperti nikah mut’ah yang mengantarkan kepada zina.” (Jaami’ al-‘Ulum wal Hikam (II/254-255)
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata, “Kemungkaran yang diingkari harus merupakan kemungkaran menurut seluruh (ulama). Jika kemungkaran tersebut termasuk perkara yang diperselisihkan, maka orang yang melakukannya tidaklah diingkari. Sebab pelakunya memandang hal tersebut bukanlah kemungkaran. Kecuali jika khilaf-nya lemah dan tidak ada nilainya, maka pelakunya diingkari. Sebagaimana dikatakan:
وَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلاَّ خِلاَفًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظْرِ
Tidak semua khilaf bisa dianggap
kecuali khilaf yang memiliki sisi pandang
Jika engkau melihat seseorang memakan daging unta lalu shalat, maka janganlah engkau mengingkarinya. Sebab permasalahannya adalah masalah khilafiyyah. Sebagian ulama memandang bahwa wajib berwudhu karena memakan daging unta dan sebagian yang lain tidak memandang demikian. Namun, tidaklah mengapa engkau membahas permasalahan ini dengannya, dan engkau menjelaskan kepadanya kebenaran (apa yang menurutmu benar). Kalau engkau melihat seorang laki-laki menjual uang kertas sepuluh real dengan sebelas real, maka apakah engkau mengingkarinya atau tidak? Jawabnya, aku tidak mengingkarinya. Sebab, sebagian ulama memandang bahwa ini hukumnya boleh dan tidak ada riba pada uang kertas. Namun aku jelaskan kepadanya dengan berdiskusi, bahwa perbuatan ini adalah kemungkaran. Analogikanlah (perkara-perkara lain) dengan apa yang telah aku sebutkan.” (Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah, hal 364, penjelasan hadits no 34)
Berikut ini adalah beberapa contoh khilaf (perbedaan pendapat) di antara para ulama Ahlus Sunnah akan tetapi mereka tidak saling mengingkari. Namun mereka berusaha menjelaskan pendapat yang paling benar menurut mereka, tanpa adanya sikap saling menjatuhkan, terlebih lagi saling tahdzir, hajr, apalagi tabdi’.
– Khilaf antara Syaikh al-Albani rahimahullah dan Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah mengenai boleh tidaknya tentara Amerika berpangkalan di Arab Saudi untuk menghancurkan Irak. Khilaf ini bukanlah khilaf yang biasa-biasa saja, namun merupakan khilaf yang nyata. Meskipun demikian mereka tetap tidak saling hajr. Padahal kalau kita perhatikan, khilaf ini berkaitan dengan keselamatan orang banyak dan berkaitan dengan masa depan negeri Saudi. Keduanya saling mempertahankan pendapat, tetapi mereka tetap saling mencintai dan saling menghormati.
– Khilaf antara Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh al-Albani mengenai masalah sedekap setelah ruku’ (ketika i’tidal). Syaikh al-Albani memandang hal ini merupakan bid’ah. Sebaliknya, Syaikh Ibnu Baaz memandang bahwa hal ini disyari’atkan. Namun, apakah Syaikh al-Albani menyatakan bahwa Syaikh Ibnu Baaz adalah ahli bid’ah, atau mengatakan bahwa orang yang berpendapat seperti pendapat Syaikh Ibnu Baaz adalah ahli bid’ah? Tentu saja tidak. Padahal Syaikh al-Albani benar-benar meyakini bahwa hal itu merupakan bid’ah. Sedangkan setiap bid’ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di Neraka. Mungkin saja nanti ada orang yang membesar-besarkan masalah ini, lalu menjadikannya sebagai ajang perpecahan, dengan alasan bahwa bid’ah itu berbahaya dan kita tidak boleh meremehkan bid’ah sekecil apapun. Pernyataan tersebut benar jika yang dimaksud adalah bid’ah yang disepakati oleh para ulama. Adapun bid’ah yang masih diperselisihkan maka pernyataan ini tidak berlaku.
– Khilaf antara Syaikh al-Albani dengan para ulama Arab Saudi tentang jumlah raka’at shalat Tarawih. Syaikh al-Albani menyatakan bahwa shalat Tarawih lebih dari 11 raka’at merupakan bid’ah. Namun apakah beliau menyatakan bahwa orang yang menyelisihi beliau adalah mubtadi’? Tentu saja tidak. Bahkan beliau berkata, “Kami tidak membid’ahkan dan tidak juga menyesatkan siapa saja yang shalat tarawih lebih dari sebelas raka’at, jika tidak jelas baginya Sunnah dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya.” (Shalaatut Taarawih, hal 106) Beliau juga berkata, “Janganlah seseorang menyangka bahwa jika kami memilih pendapat (wajibnya) mencukupkan bilangan raka’at Tarawih sesuai Sunnah (yaitu sebelas raka’at) dan tidak boleh menambah bilangan tersebut, berarti kami telah menyesatkan atau membid’ahkan mereka yang tidak berpendapat demikian dari para ulama, baik ulama yang dahulu maupun yang akan datang, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, sehingga menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk mencela kami. Mereka menyangka bahwa pendapat kami tentang tidak dibolehkan atau bid’ahnya suatu perkara melazimkan bahwa siapa saja yang berpendapat bolehnya atau disunnahkannya perkara tersebut sebagai ahli bid’ah yang sesat. Sama sekali tidak melazimkan demikian. Ini adalah persangkaan yang batil dan kebodohan yang sangat. Sesungguhnya yang dicela adalah para ahli bid’ah yang menghalangi tersebarnya Sunnah dan menganggap baik seluruh bid’ah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penjelasan, bahkan tanpa taqlid terhadap para ulama, namun hanya sekedar mengikuti hawa nafsu dan mencari pujian orang awam….” (Shalaatut Taarawih, hal 35-36)
Beliau juga berkata, “Karena itu, kita lihat meskipun para ulama berselisih pendapat secara sengit pada sejumlah masalah namun mereka tidak saling menyesatkan dan tidak juga saling membid’ahkan satu sama lain. Satu contoh dalam hal ini, para ulama telah berselisih pendapat (bahkan) sejak zaman para Sahabat tentang masalah menyempurnakan shalat wajib (empat raka’at) ketika safar. Di antara mereka ada yang membolehkan, sedangkan sebagian lain melarangnya dan memandang bahwa hal itu adalah bid’ah yang menyelisihi Sunnah. Meskipun demikian, ternyata mereka tidak membid’ahkan orang yang menyelisihi pendapat mereka. Lihatlah Ibnu Umar, beliau berkata, “Shalat musafir dua raka’at, barangsiapa yang menyelisihi Sunnah maka telah kafir.” (Sebagaimana diriwayatkan oleh as-Sarraaj dalam Musnad-nya (XXI/122-123), dengan dua isnad yang shahih dari Ibnu ‘Umar). Meskipun demikian Ibnu ‘Umar tidak mengafirkan juga ti
dak menyesatkan orang-orang yang menyelisihi Sunnah disebabkan ijtihadnya. Bahkan, tatkala beliau shalat di belakang imam yang memandang menyempurnakan shalat (empat raka’at), maka beliau pun ikut menyempurnakan shalat bersama imam tersebut. As-Sarraj juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi ` shalat di Mina dua raka’at, begitu juga Abu Bakr, ‘Umar, dan ‘Utsman di awal masa pemerintahan beliau. Setelah itu ‘Utsman shalat di Mina empat raka’at. Jika Ibnu ‘Umar shalat bersama ‘Utsman maka beliau shalat empat raka’at, dan jika beliau shalat sendirian maka beliau shalat dua raka’at. Perhatikanlah, bagaimana keyakinan Ibnu ‘Umar terhadap kesalahan orang yang menyelisihi Sunnah yang shahih –dengan menyempurnakan shalat empat raka’at- tidak menjadikan beliau menyesatkannya atau membid’ahkannya. Bahkan beliau shalat di belakang ‘Utsman. Sebab, beliau tahu bahwa ‘Utsman tidaklah menyempurnakan shalat empat raka’at karena mengikuti hawa nafsu namun beliau melakukan demikian karena ijtihad beliau. Inilah jalan tengah yang menurut kami harus ditempuh oleh kaum muslimin untuk memperoleh solusi dari perbedaan pendapat yang timbul diantara mereka; yaitu masing-masing menampakkan pendapatnya yang menurutnya benar dan sesuai dengan al-Qur-an dan Sunnah dengan syarat tidak menyesatkan atau membid’ahkan orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya tersebut….” (Shalaatut Taarawih, hal 37-38)
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Diriwayatkan dari as-Salafus Shalih jumlah bilangan raka’at Tarawih yang beraneka ragam –dalam masalah ini-, sebagaimana perkataan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyyah, maka lapang bagi kita apa yang lapang bagi mereka. Kita telah didahului oleh mereka, maka tidak semestinya kita bersikap keras.” (Lihat Majmuu’ Fataawa (XIV/208).
Beliau juga berkata, “Ketahuilah, bahwasanya khilaf tentang jumlah bilangan raka’at shalat Tarawih -dan yang semisalnya; yang termasuk perkara-perkara yang dibolehkan ijtihad di dalamnya- hendaknya tidak dijadikan ajang perselisihan dan perpecahan umat. Terlebih lagi jika Salaf berbeda pendapat pada masalah ini. Tidak ada satu dalil pun yang melarang berlakunya ijtihad dalam perkara ini.” (Majmuu’ Fataawa (XIV/189).
– Khilaf antara Syaikh al-Albani dengan para Ulama Arab Saudi -di antaranya Syaikh Ibnu Baaz- tentang hukum jual beli kredit dengan harga yang berbeda dari harga kontan. Menurut Syaikh al-Albani hal itu adalah riba, namun apakah Syaikh Al-Albani men-tahdzir dan meng-hajr para ulama Arab Saudi dengan alasan bahwa mereka membolehkan riba, dan orang yang membolehkan riba terlaknat sebagaimana dalam hadits? Tentu tidak, karena ini adalah masalah khilafiyyah ijtihadiyyah.
Perhatikanlah, sungguh ajaib akhlak kedua ulama besar Ahlus Sunnah tersebut. Keduanya berselisih dalam banyak permasalahan yang sebagiannya bukanlah masalah ringan. Masalah-masalah tersebut bahkan terkadang terjadi berulang-ulang. Namun keduanya sama sekali tidak saling menjatuhkan, bahkan keduanya saling mencintai dan saling menghormati. Itulah akhlak para ulama kita. Bahkan Syaikh Bin Baaz sering mengatakan bahwa Syaikh Al-Albani merupakan mujaddid abad ini (Lihat Silsilah Al-Huda wan Nuur no 725). Demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin yang sering menyelisihi Syaikh Al-Albani dalam permasalahan ijtihadiah, namun meskipun demikian beliau pernah berkata “Syaikh Al-Albani adalah Muhaddits abad ini” (Lihat Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset no 880). Adapun “sebagian orang”, terkadang disebabkan satu masalah saja yang diperselisihkan -padahal masalah tersebut bukanlah masalah yang berat dan terkadang merupakan masalah dunia, bukan permaslahan agama- maka mereka jadikan alasan untuk saling menjauhi, saling menjatuhkan, saling mencerca saling men-tahdzir dan saling hajr, dan seterusnya. Wallahul musta’aan
Kesimpulan :
Untuk perkara-perkara yang menyangkut masalah ijtihadiyyah, maka tidak boleh diterapkan hajr. Begitu juga dengan sebagian permasalahan ‘aqidah yang bukan fundamental, namun merupakan masalah ‘aqidah yang diperselisihkan oleh para salaf, yang disebut dengan furuu’ al-Ushul. Sebab ada masalah ‘aqidah yang masih diperselisihkan oleh Salaf, sehingga menunjukkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara ijtihadiyyah. Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan secara panjang lebar tentang perselisihan para sahabat dalam sebagian permasalahan ‘aqidah, namun hal ini tidaklah menjadikan mereka saling hajr, karena perkara ‘aqidah yang mereka perselisihkan bukanlah perkara fundamental yang urgen (Sebagaimana telah lalu penukilan penjelasan Ibnu Taimiyyah akan hal ini dari majmu’ fatawa XXIV/172-174. Semisal dengan ini juga penjelasan Ibnu Taimiyyah dalam majmu’ fatwa XIX/122-123. Lihat penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang khilaf salaf dalam furu’ al-Ushul dalam “Kitaabul ‘Ilmi” hal 200). Maka perkara yang seperti ini disamakan dengan perselisihan dalam fiqh, sama sekali tidak mebutuhkan tahdzir apalagi hajr.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahillah berkata, “Semua perkara yang bukan termasuk perkara-perkara ushul (pokok) yang urgen, maka diikutkan dengan permasalahan-permasalahan hukum (fiqh).” (Majmuu’ Fataawa (XXIV/172-176))
bersambung…
Abu ‘Abdilmuhsin Firanda Andirja
Artikel: www.firanda.com